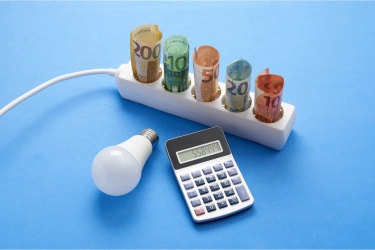Tantangan Bank Indonesia Pasca-Kebijakan Proteksionis AS
KEBIJAKAN proteksionis dan arah geopolitik Amerika Serikat pasca-era Donald Trump menimbulkan turbulensi baru dalam perekonomian global.
Oleh karena itu, lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF telah merevisi outlook pertumbuhan ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai respons atas tekanan global yang meningkat.
Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sebelumnya 5,10 (pra-tarif Trump, Januari 2025) persen menjadi 4,70 persen, atau turun 0,4 poin persentase (post-tarif Trump, April 2025).
Sementara itu, IMF juga menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia dari 4,9 persen (pra-tarif Trump, Maret 2025) menjadi 4,7 persen atau koreksi sebesar 0,2 poin (post-tarif Trump, Juni 2025.
Bahkan, IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekitar 4,7 persen pada 2026, di bawah rata-rata sebelum pandemi (5 persen–5,3 persen).
Revisi ini mencerminkan kekhawatiran atas dampak lanjutan dari melemahnya perdagangan internasional, tekanan pada ekspor komoditas, penurunan arus investasi asing langsung (FDI), serta ketidakpastian geopolitik yang membebani pasar keuangan.
Revisi outlook ini menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat bauran kebijakan fiskal dan moneter, meningkatkan daya saing sektor riil, serta memperluas sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Berhadapan dengan tantangan-tantangan seperti itu, BI sebagai otoritas moneter nasional menghadapi beban yang semakin berat untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan nilai tukar.
Dalam ulasan kali ini, penulis mencoba mengurai tantangan-tantangan utama yang dihadapi BI dalam konteks global pasca-Trump dan bagaimana lembaga ini harus meresponsnya secara strategis.
Tekanan pada ekspor dan defisit neraca perdagangan
Salah satu tantangan pertama yang muncul akibat kebijakan tarif Trump adalah penurunan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS), sekitar 11,3 persen dari total ekspor Indonesia.
Apabila AS menerapkan tarif yang lebih tinggi atau kebijakan dagang yang lebih agresif, maka ekspor Indonesia akan tertekan, menciptakan defisit neraca dagang yang lebih besar.
Persoalannya tidak berhenti di situ. Kebijakan Trump sudah tentu berdampak pada perekonomian negara lain yang sangat terhubung dengan AS, seperti China.
Artinya, pada tahap tertentu kebijakan tarif Trump akan memaksa Negeri Tirai Bambu itu mengendurkan permintaan ekspornya dari Indonesia.
Tat kala, China menurunkan permintaan produk ekspor utama dari Indonesia--diproyeksikan sebesar 7 persen pada tahun ini-- maka hal tersebut akan menggerus penerimaan devisa Indonesia secara signifikan.
Merosotnya penerimaan devisa akibat koreksi ekspor akan menekan nilai tukar rupiah, sedangkan penurunan surplus dagang memperlemah neraca transaksi berjalan.
Depresiasi rupiah pada gilirannya akan memicu risiko imported inflation, sehingga menambah tekanan inflasi domestik.
Penerapan kebijakan tarif Trump juga memicu relokasi besar-besaran investasi dari AS ke negara-negara dengan tarif lebih rendah. Sayangnya, Indonesia tidak menjadi pilihan utama para investor AS.
Akibatnya, jumlah investasi langsung asing atau foreign direct invesmenet (FDI) dari AS ke Indonesia diproyeksikan akan menurun secara signifikan.
Para analis global berpendapat, penurunan FDI AS ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia disebabkan tiga faktor utama.
Pertama adalah faktor melambatnya pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara besar seperti china, India, Brasil, dan Indonesia.
Kondisi tersebut membuat para investor global, terutama investor AS, menahan diri untuk membuat keputusan berinvestasi.
Kedua, faktor relokasi FDI AS ke negara dengan tarif lebih murah, seperti Vietnam atau Meksiko.
Faktor ketiga adalah melemahnya harga komoditas global di sektor pertambangan dan energi.
Tren ini berdampak investasi di sektor pertambangan dan energi di seluruh dunia.
Indonesia merasakan dampaknya karena secara historis selalu mengandalkan investasi di kedua sektor tersebut.
Implikasi bagi BI cukup kompleks. Kekurangan pasokan valuta asing dari FDI menyebabkan cadangan devisa menurun. Penurunan investasi turut melemahkan sektor riil, menghambat pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, ketergantungan pada hot money meningkat, memicu volatilitas nilai tukar yang lebih tinggi, sehingga memperberat tugas BI dalam menjaga stabilitas moneter dan kestabilan sistem keuangan nasional di tengah ketidakpastian global.
Tekanan ganda: Krisis di sektor moneter dan keuangan
Perang dagang yang dilancarkan Trump telah menimbulkan krisis di sektor moneter dan keuangan global, tak kecuali di Indonesia.
Dalam aspek moneter, mata uang Indonesia, rupiah, menghadapi tekanan depresiasi karena keluarnya modal asing dari pasar keuangan domestik (capital outflow).
Depresiasi rupiah meningkatkan imported inflation, yaitu inflasi yang berasal dari barang impor yang menjadi lebih mahal, dan daya beli masyarakat menjadi semakin lemah.
Masalah lain yang dihadapi BI adalah cadangan devisa yang menurun akibat ekspor yang menurun dan surplus perdagangan yang merosot.
Berhadapan dengan situasi tersebut, BI berada dalam posisi terjepit, karena memiliki ruang kebijakan moneter yang terbatas untuk menjaga stabilitas moneter dan keuangan nasional.
BI juga menghadapi tekanan di sektor pasar modal dan obligasi. Ketidakpastian ekonomi global ternyata telah menimbulkan sentimen negatif yang membuat investor menarik dana dari pasar modal negara berkembang yang rapuh.
Hal ini menyebabkan harga saham dan obligasi Indonesia tertekan sehingga meningkatkan risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan.
Telah disinggung di atas, salah satu bahaya yang muncul pasca-kebijakan tarif Trump adalah kemerosotan ekspor dan surplus perdagangan yang berdampak langsung pada menurunnya penerimaan devisa.
Kemerosotan penerimaan devisa pada gilirannya akan memicu risiko imported inflation, sehingga menambah tekanan inflasi domestik.
Dari sisi moneter, inflasi dimaknai sebagai kondisi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih besar daripada jumlah barang dan jasa.
Inflasi dapat menimbulkan masalah kompleks karena melemahkan daya beli masyarakat, tetapi membuat harga barang dan jasa menjadi semakin mahal.
Inflasi juga membuat nilai tukar rupiah merosot dibandingkan valuta asing. Keadaan ini dapat melemahkan daya saing produk Indonesia di pasar luar negeri (ekspor).
Jika pemerintah dan BI gagal mengendalikan inflasi, maka ekonomi Indonesia berada di pusaran lingkaran setan dan pada akhirnya jatuh terpuruk.
Repotnya, inflasi bisa bertransformasi menjadi ‘monster global’ yang sangat berbahaya ketika dikombinasikan dengan ketidakpastian ekonomi global.
Suka tidak suka, perang tarif Trump dan ketegangan geopolitik yang belakangan ini terjadi telah menguatkan ketidakpastian ekonomi global itu.
Contoh, saat Israel melakukan serangan ke Iran, ekonom dunia terguncang keras karena harga minyak mentah menembus angka 75 dollar AS per barel, tertinggi selama 6 bulan pertama tahun 2025.
Baru, setelah kedua negara itu bersepakat melakukan gencatan senjata (Selasa, 24/6), harga minyak bisa turun lagi menjadi 64,8 dollar AS per barel (Kamis, 26/6).
Namun, tak ada yang dapat menjamin 100 persen bahwa konflik di kawasan kaya minyak itu tidak pecah lagi. Jika konflik kemudian terjadi lagi, maka harga minyak dipastikan akan bergerak lebih tinggi lagi.
Dampaknya pun akan langsung menohok pada biaya produksi dalam negeri dan menyebabkan tekanan inflasi tambahan yang makin kuat lagi.
BI tidak bisa sendirian
Sekali pun memiliki otoritas tertinggi dan paling bertanggung jawab dalam urusan moneter, BI tidak bisa menghadapi semua tantangan yang kompleks ini sendirian.
Sebaliknya, BI perlu membangun sinergi lintas lembaga melalui koordinasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan, BKPM, OJK, dan sektor swasta untuk membangun daya tahan ekonomi nasional.
Untuk mengatasi pelemahan FDI, misalnya, BI perlu meningkatkan kerja sama dengan pemerintah dan OJK guna menjaga daya saing investasi, khususnya dengan memperkuat stabilitas makro dan kebijakan suku bunga yang kompetitif.
Guna mengendalikan inflasi, BI harus kuat dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan nilai tukar. BI harus merespons dengan menyesuaikan kebijakan moneter untuk menyeimbangkan antara menjaga nilai tukar dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sebagai solusi bagi krisis moneter dan keuangan, BI harus mengembangkan strategi stabilisasi nilai tukar sebagai prioritas utama. Namun di sisi lain, harus memperkuat bauran kebijakan dengan pendekatan koordinatif bersama Kemenkeu dan OJK.
Berhadapan dengan tekanan inflasi dan ketidakpastian global, BI perlu merancang dan menerapkan bauran kebijakan yang adaptif, fleksibel, dan terkoordinasi.
BI hendaknya menyusun kebijakan moneter proaktif seperti menerapkan suku bunga acuan yang fleksibel, dan menjaga stabilitas rupiah tanpa menghambat pemulihan ekonomi.
BI juga dapat mengintervensi pasar valas demi menjaga volatilitas rupiah melalui mekanisme pasar. Misalnya, melakukan operasi pasar terbuka (OMO) guna menstabilkan likuiditas jangka pendek.
Upaya lain yang dapat ditempuh adalah melakukan penguatan cadangan devisa dan mendiversifikasi sumber valuta asing melalui strategi hedging dan swap bilateral untuk memperkuat kerja sama dengan negara mitra seperti Jepang, China, dan negara ASEAN.
Cara berikutnya adalah mendorong peningkatan ekspor di sektor jasa seperti pariwisata dan layanan digital sebagai sumber devisa alternatif non-komoditas.
Strategi berikutnya adalah digitalisasi sistem pembayaran dan transaksi. Berkenaan dengan ini BI dapat memperluas penggunaan QRIS, BI-Fast, dan inovasi digital untuk mempercepat efisiensi ekonomi dan memperluas basis ekonomi domestik.
Selanjutnya, BI hendaknya juga mengelola ekspektasi pasar dan masyarakat melalui komunikasi yang transparan dan kredibel untuk menjaga kepercayaan terhadap kebijakan BI.
Dari uraian di atas, kita tak dapat memungkiri bahwa era pasca-tarif Trump membawa dinamika baru yang menantang bagi ekonomi global dan Indonesia.
BI menghadapi tekanan dari berbagai sisi baik dari sisi perdagangan, FDI, keuangan, maupun sisi moneter.
Berhadapan dengan tantangan yang kompleks demikian, respons BI harus bersifat sistemik, adaptif, dan terintegrasi.
BI harus terus memperkuat upaya-upaya sinergis seperti koordinasi fiskal-moneter untuk mengendalikan inflasi; kolaborasi dalam mendorong insentif bagi ekspor dan FDI; dan pemanfaatan teknologi dan data dalam memitigasi risiko keuangan, serta terus mengembangkan penguatan koordinasi lintas lembaga.
Jika BI tidak mengelola responsnya secara lengkap dan terpadu, maka tekanan-tekanan tersebut bisa mengaburkan momentum pemulihan ekonomi Indonesia yang telah dibangun pasca-pandemi Covid-19.
Jadi, hanya dengan kebijakan yang komprehensif dan kolaborasi erat, Indonesia tetap memiliki peluang untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meraih pertumbuhan inklusif, meski berada dalam pusaran ketidakpastian global.
Tag: #tantangan #bank #indonesia #pasca #kebijakan #proteksionis