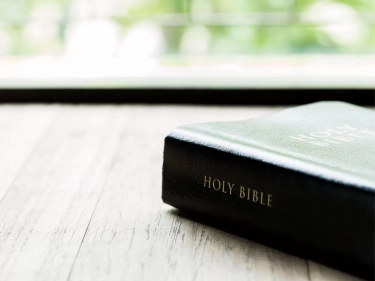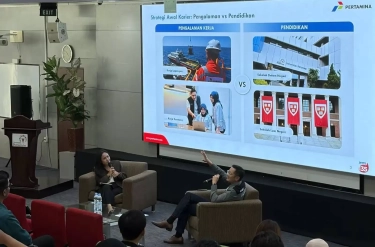Indonesia Butuh Lembaga Pencipta Lapangan Kerja
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto, dalam visi-misinya saat kampanye Pilpres 2024, menjanjikan penciptaan 19 juta lapangan kerja baru hingga 2029.
Namun hingga pertengahan 2025, kenyataan di lapangan masih jauh dari janji tersebut. Alih-alih tercipta lapangan kerja baru secara masif, justru gelombang PHK dan meningkatnya ketidakpastian kerja makin menguat.
Laporan World Economic Outlook yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF) pada April 2025 mencatat bahwa Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di Asia dalam hal tingkat pengangguran, dengan angka mencapai 5 persen, hanya sedikit di bawah China yang mencatat 5,1 persen.
Di kawasan ASEAN, posisi Indonesia justru menjadi yang tertinggi, mengungguli Filipina (4,5 persen), Malaysia (3,2 persen), dan jauh di atas Vietnam serta Thailand yang tingkat penganggurannya di bawah 2 persen.
Angka itu belum mencerminkan keseluruhan masalah. Jutaan pekerja “disamarkan” ke dalam kategori informal: ojek daring, pedagang asongan, buruh harian lepas, atau pekerja paruh waktu yang hidup tanpa perlindungan sosial.
Jika pekerja informal dihitung, maka lebih dari 60 persen angkatan kerja Indonesia berada dalam kondisi kerja yang rentan—ironi di tengah jargon kemajuan dan industrialisasi.
Fenomena NEET (Not in Employment, Education, or Training) juga menjadi bom waktu yang luput dari radar kebijakan.
Data dari ILO dan ADB menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat NEET tertinggi di Asia Tenggara, terutama di kelompok usia muda (15–24 tahun).
Sekitar 10 juta anak muda tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak menjalani pelatihan—mereka terputus dari sistem. Mereka kehilangan arah, dan negara kehilangan kendali atas bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan ekonomi.
Sementara itu, gelombang PHK terus menggerus rasa aman kerja. Industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki melakukan efisiensi besar-besaran. Start-up digital tumbang satu per satu.
Bahkan sektor yang selama ini dianggap relatif aman—seperti perbankan, media, dan logistik—mulai melakukan rasionalisasi.
Dalam dua tahun terakhir, ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaan. Namun, negara tampak hanya mencatat, tanpa satu pun aktor institusional yang secara khusus bertugas mencegah atau memulihkan krisis ketenagakerjaan secara sistemik.
Di berbagai kota, job fair berubah menjadi drama sosial. Ribuan pelamar memadati lokasi bursa kerja hanya untuk menemukan antrean panjang, informasi yang tidak jelas, dan jumlah lowongan yang tidak sebanding dengan pelamar.
Di Bekasi, kericuhan sempat pecah karena jumlah peserta melebihi kapasitas lokasi.
Di berbagai daerah, pelamar harus datang sejak subuh demi memastikan formulir pendaftaran tidak habis. Job fair menjadi simbol ironi: ia dirancang untuk memberi harapan, tapi justru memperlihatkan betapa terbatasnya peluang yang tersedia.
Gejolak sosial pun mulai menyeruak ke permukaan. Viralnya tagar #KaburAjaDulu bukan sekadar luapan frustrasi di media sosial, melainkan sinyal bahwa semakin banyak anak muda kehilangan kepercayaan terhadap negeri ini sebagai ruang hidup yang layak dan memberi harapan.
Bekerja ke luar negeri pun tak kunjung difasilitasi negara dengan sistem yang memudahkan dan bermartabat.
Mereka yang pergi bukan sedang mengejar mimpi indah, apalagi kekayaan. Mereka pergi karena didesak keadaan. Sebab di tanah kelahiran sendiri, peluang untuk hidup layak kian menyempit. Ini bukan soal ambisi—ini soal bertahan hidup. Mereka hanya ingin bekerja.
Di satu sisi, pemerintah kerap menyampaikan klaim keberhasilan dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan melalui program vokasi dan padat karya.
Kementerian Ketenagakerjaan, misalnya, melaporkan telah meningkatkan kompetensi ratusan ribu orang melalui pelatihan, pemagangan, dan sertifikasi.
Bahkan, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut bahwa sebanyak 3,59 juta lapangan kerja baru berhasil tercipta sepanjang Februari 2024 hingga Februari 2025, mengacu pada data BPS yang dirilis pada Mei 2025.
Angka ini diklaim turut mendorong penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,76 persen—terendah sejak krisis ekonomi 1998.
Namun, laporan-laporan semacam ini umumnya lebih menonjolkan output administratif—seperti jumlah peserta pelatihan—ketimbang outcome strategis berupa penyerapan tenaga kerja formal yang berkelanjutan.
Tanpa adanya audit independen dan mekanisme verifikasi transparan, publik sulit menilai seberapa besar dampak riil dari program-program tersebut terhadap ketahanan kerja nasional.
Kementerian Perindustrian pun sempat mengklaim bahwa mayoritas lulusan vokasi mereka terserap ke sektor industri. Namun, data tersebut bersifat sektoral, terbatas pada lembaga binaan langsung, dan tidak mencerminkan efektivitas program pelatihan secara nasional.
Klaim optimistis juga datang dari sektor hilirisasi. Dalam Human Capital Summit (Juni 2025), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa proyek hilirisasi dan transisi energi akan menciptakan sekitar 6,2 juta lapangan kerja langsung hingga 2030—meliputi sektor ketenagalistrikan, mineral, batu bara, dan kendaraan listrik.
Saat menanggapi kritik publik, ia bahkan melontarkan pernyataan “jangan kufur nikmat”—seolah optimisme saja cukup menggantikan kebutuhan akan data yang terverifikasi.
Jika ditarik secara keseluruhan, hingga pertengahan 2025 belum ada satu pun dari klaim sektoral tersebut yang disertai audit independen atau data publik yang dapat memverifikasi secara konkret berapa banyak lapangan kerja riil yang benar-benar tercipta.
Pada akhirnya, baik program vokasi maupun proyek hilirisasi menghadapi tantangan mendasar yang serupa: minimnya transparansi, lemahnya pengukuran dampak, dan absennya akuntabilitas kelembagaan.
Masyarakat tidak disuguhi metrik yang jelas antara program yang dijalankan dan jumlah pekerjaan yang benar-benar tercipta.
Tanpa perbaikan menyeluruh dalam tata kelola, seluruh upaya penciptaan kerja rentan terjebak dalam rutinitas birokrasi yang hampa—jauh dari solusi struktural atas krisis ketenagakerjaan nasional.
Lebih dari itu, publik terus menyaksikan pola yang berulang: gelombang pelatihan tanpa kepastian kerja, gelombang PHK yang merajalela, dan akhirnya gelombang kekecewaan yang diwariskan dari satu rezim ke rezim berikutnya.
Janji berubah menjadi ilusi. Ilusi berubah menjadi krisis. Dan krisis perlahan menjelma menjadi normal baru yang melelahkan secara sosial dan psikologis.
Janji Prabowo untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja hingga 2029 bukan sekadar angka besar. Ia adalah janji struktural yang membutuhkan kepemimpinan, desain kelembagaan, dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.
Persoalannya bukan hanya “berapa?”, melainkan juga “bagaimana?” dan “oleh siapa?”.
Ini bukan soal kegagalan satu presiden. Fenomena melesetnya janji penciptaan kerja adalah pola sistemik yang telah berulang dari satu rezim ke rezim berikutnya.
Janji membuka lapangan kerja telah menjadi semacam ritual politik: wajib diucapkan saat kampanye, tapi dibiarkan tanpa mekanisme eksekusi begitu pemilu usai.
Hingga kini, tidak ada satu pun institusi negara yang diberi mandat eksplisit untuk menciptakan lapangan kerja sebagai fungsi utama.
Kementerian Ketenagakerjaan lebih berfokus pada pelatihan dan hubungan industrial. Kementerian Pendidikan menangani peningkatan kualitas SDM. Kementerian Investasi mengurus ekosistem usaha.
Namun tak satu pun dari mereka yang bertanggung jawab langsung terhadap penciptaan pekerjaan sebagai output institusional yang dapat diukur, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara publik.
Akibatnya, janji penciptaan kerja terus mengambang sebagai omon-omon politik—tanpa eksekutor, tanpa strategi, tanpa kepemimpinan yang tegas.
Harapan publik patah berulang-ulang, sementara anak-anak muda—yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi nasional—dipaksa mengantre kerja di negeri sendiri, atau diam-diam kabur ke negeri orang secara ilegal, membawa tenaga, asa, dan harga dirinya.
Kekosongan lembaga negara
Begitu vitalnya urusan penciptaan lapangan kerja, Indonesia justru menghadapi ironi struktural. Tak satu pun lembaga negara yang secara eksplisit diberi mandat utama untuk menciptakan pekerjaan.
Indonesia punya kementerian yang mengurus pelatihan, pendidikan, investasi, hingga industri. Namun, tidak ada institusi yang bertugas secara langsung menciptakan pekerjaan sebagai target utama, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kementerian Tenaga Kerja lebih berperan sebagai regulator hubungan industrial, bukan eksekutor pencipta kerja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan fokus pada pengembangan kapasitas SDM, namun terputus dari kebutuhan nyata pasar kerja.
Kementerian Investasi dan Kementerian Perindustrian memfasilitasi iklim usaha, namun tidak menjamin terjadinya rekrutmen tenaga kerja secara luas.
Sementara kementerian lainnya berjalan sesuai sektornya masing-masing, tanpa koordinasi sistemik dalam urusan ketenagakerjaan nasional.
Situasi ini menciptakan kekosongan kelembagaan yang fatal. Tidak ada satu pun institusi yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika janji lapangan kerja tak terwujud. Setiap sektor melempar tanggung jawab, dan publik dibiarkan bingung harus bertanya kepada siapa.
Lebih dari itu, absennya lembaga pencipta kerja ini menjadikan upaya pembangunan tenaga kerja Indonesia berlangsung secara sektoral, tumpang tindih, dan sporadis.
Data pelatihan, serapan kerja, dan proyeksi pasar kerja tersebar di berbagai kementerian, dengan standar pelaporan yang tidak seragam.
Tak ada satu pun dashboard nasional yang mampu menunjukkan, secara real-time, berapa banyak lowongan kerja tersedia, berapa jumlah penganggur baru, dan bagaimana strategi negara merespons dinamika pasar kerja tersebut.
Selama ini, capaian pemerintahan lebih sering dinilai dari indikator seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau peningkatan ekspor.
Padahal, tanpa penciptaan lapangan kerja yang inklusif, pertumbuhan bisa bersifat semu—dan justru memperlebar ketimpangan sosial. Ketika pekerjaan menjadi hak yang tak dijamin, maka pembangunan kehilangan keadilan sebagai jiwa utamanya.
Padahal, konstitusi Indonesia secara tegas menetapkan bahwa pekerjaan adalah hak warga negara yang harus dijamin oleh negara.
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
Ini bukan sekadar deklarasi normatif, tapi mandat konstitusional yang menuntut negara hadir secara aktif dalam penyediaan kerja yang bermartabat.
Di era modern, kesejahteraan rakyat dimulai dari terpenuhinya hak atas pekerjaan yang layak. Tanpa kerja, rakyat bukan hanya kehilangan penghasilan, tetapi juga kehilangan martabat, arah hidup, dan peran dalam masyarakat.
Karena itu, penyediaan lapangan kerja tidak boleh dianggap sebagai program tambahan—melainkan sebagai fungsi utama negara dalam memenuhi amanat konstitusi.
Dalam konteks ini, janji menciptakan 19 juta lapangan kerja bukan hanya terasa berat direalisasikan, tetapi juga tidak memiliki fondasi kelembagaan yang memadai.
Tanpa institusi yang secara khusus diberi mandat, mustahil ada kepemimpinan tunggal yang mampu mengoordinasikan lintas sektor—dari pendidikan ke dunia kerja, dari investasi ke rekrutmen tenaga kerja, dari pelatihan ke penyediaan upah yang layak.
Kekosongan kelembagaan inilah yang membuat kebijakan ketenagakerjaan kita cenderung reaktif ketimbang strategis. Negara baru hadir saat krisis meledak, ketika gejolak sosial tak lagi bisa dibendung.
Padahal, tantangan ketenagakerjaan membutuhkan pendekatan yang antisipatif, kolaboratif, dan sistemik.
Tanpa lembaga yang secara khusus dirancang untuk menjawab tantangan tersebut, kita sesungguhnya sedang berjalan tanpa arah dalam lanskap ekonomi global yang terus berubah—dan melalaikan amanat konstitusi yang seharusnya menjadi fondasi utama kebijakan publik kita.
Usulan lembaga pencipta lapangan kerja
Sejak dekade 1980-an, banyak negara—termasuk Indonesia—terbawa dalam arus pemikiran neoliberal yang menyerahkan urusan penciptaan lapangan kerja sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
Negara cukup berperan sebagai fasilitator: menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyediakan infrastruktur dasar, dan menjaga stabilitas ekonomi. Sisanya, pasar diyakini akan bekerja secara otomatis menyerap tenaga kerja.
Pandangan ini menjadikan pekerjaan bukan sebagai tujuan utama pembangunan, melainkan sekadar efek samping dari pertumbuhan. Negara pun tidak merasa perlu membentuk lembaga khusus yang bertanggung jawab menciptakan kerja.
Kinerja pemerintahan lebih sering diukur dari seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi, seberapa besar nilai ekspor, atau seberapa baik peringkat kemudahan berusaha—bukan dari seberapa banyak rakyatnya memiliki pekerjaan yang layak dan bermartabat.
Di Indonesia, urusan penciptaan lapangan kerja tersebar di berbagai kementerian. Kementerian Ketenagakerjaan menangani pelatihan vokasi, hubungan industrial, dan pelindungan hak pekerja.
Kementerian Investasi serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berfokus pada penciptaan nilai tambah dan perluasan usaha.
Kementerian Pendidikan bertanggung jawab atas peningkatan kualitas sumber daya manusia. Begitu pula kementerian-kementerian lain yang menjalankan fungsi sektoral masing-masing, meskipun sebagian memiliki keterkaitan dengan isu penciptaan kerja.
Namun, tidak satu pun dari lembaga-lembaga tersebut yang secara eksplisit diberi mandat utama untuk menciptakan lapangan kerja sebagai output yang terukur.
Fungsi penciptaan kerja menjadi tercecer di banyak kementerian, tidak terkoordinasi, dan pada akhirnya sulit diukur efektivitasnya. Ketika janji-janji kerja tidak terpenuhi, tak ada institusi yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung.
Kekosongan kelembagaan ini tidak bisa terus dibiarkan. Di tengah tekanan global akibat disrupsi teknologi, krisis iklim, otomatisasi, dan ledakan demografi usia produktif, negara tidak lagi bisa berpangku tangan dan berharap pasar akan menciptakan pekerjaan.
Negara harus hadir secara aktif, strategis, dan terstruktur. Sebab pertumbuhan ekonomi tanpa penciptaan kerja hanya memperdalam ketimpangan.
Investasi tanpa daya serap tenaga kerja hanya memperluas frustrasi sosial. Pendidikan tanpa koneksi ke pasar kerja hanya memperpanjang antrean pengangguran terdidik.
Dalam konteks ini, Indonesia membutuhkan satu lembaga dengan mandat tegas, terukur, dan bertanggung jawab langsung atas penciptaan lapangan kerja.
Lembaga ini bisa berbentuk kementerian baru yang bersifat permanen, atau unit ad hoc yang bersifat operasional dan fleksibel.
Sebagai langkah awal, pembentukan Satuan Tugas Nasional Penciptaan Lapangan Kerja menjadi pilihan strategis.
Satgas ini adalah lembaga lintas sektor yang dibentuk melalui Keputusan Presiden, dan berada langsung di bawah koordinasi Presiden untuk memastikan efektivitas dan arah kebijakan berjalan konsisten.
Satgas ini dirancang menjadi simpul koordinasi nasional, yang bertugas mengonsolidasikan seluruh program penciptaan kerja yang saat ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
Tujuannya: memastikan seluruh kebijakan mengarah pada satu hasil nyata—pekerjaan baru yang konkret bagi rakyat.
Satgas ini akan memantau dan melaporkan secara berkala jumlah pekerjaan baru yang benar-benar tercipta dari setiap program dan kebijakan negara.
Ia juga akan mengintegrasikan basis data ketenagakerjaan nasional—menghubungkan sektor pendidikan, pelatihan, investasi, industri, hingga demografi dalam satu sistem informasi terpadu.
Yang membedakan, Satgas ini bukan lembaga baru dengan struktur gemuk, melainkan dapur koordinasi cepat lintas sektor.
Ia tidak mengambil alih kewenangan kementerian, tetapi menyelaraskan arah dan langkah semua pemangku kebijakan agar bergerak dalam satu garis lurus: penciptaan lapangan kerja nyata.
Tanpa birokrasi tambahan. Tanpa pencetakan jabatan baru. Tanpa proses politik yang berbelit. Satgas ini dirancang untuk bekerja cepat, efisien, dan berorientasi hasil.
Dengan kehadiran Satgas ini, untuk pertama kalinya pemerintah memiliki simpul kelembagaan yang bisa menjawab satu pertanyaan mendasar yang selama ini tak terjawab:
siapa yang bertanggung jawab menciptakan kerja?
Karena hingga kini, jawabannya nihil. Lapangan kerja terus menjadi janji kampanye lima tahunan—tanpa tuan, tanpa pelaksana, tanpa institusi yang bisa dimintai pertanggungjawaban.
Namun, Satgas ini bukan tujuan akhir. Ia adalah batu pijakan awal menuju transformasi kelembagaan jangka panjang.
Jika Satgas berhasil menunjukkan hasil konkret—mengintegrasikan pelatihan dan industri, menurunkan tingkat pengangguran, serta menciptakan peluang kerja baru yang nyata—maka dukungan publik dan legitimasi politik akan mengarah pada pembentukan Kementerian Lapangan Kerja sebagai lembaga permanen.
Pendekatan bertahap ini penting agar tidak menimbulkan resistensi politik dan birokrasi di tahap awal.
Mendirikan kementerian baru kerap menimbulkan tarik-menarik kepentingan, perdebatan anggaran, dan kekhawatiran akan pembengkakan birokrasi.
Satgas menjadi bentuk awal yang ringan dan lincah—jalan tengah yang memungkinkan negara mulai bekerja secara fokus tanpa menabrak struktur yang ada.
Sudah waktunya Indonesia berhenti menjadikan pekerjaan sebagai retorika kampanye. Lapangan kerja harus diinstitusikan, dijalankan, dan diawasi secara publik.
Negara yang gagal menciptakan kerja bukan hanya gagal secara ekonomi, tetapi juga kehilangan legitimasi sosialnya di mata rakyat.
Dalam praktik global, beberapa negara telah bergerak ke arah reformasi struktural serupa. Singapura melalui Ministry of Manpower tak hanya mengatur relasi industrial, tetapi juga secara aktif merancang sistem penciptaan kerja melalui "Workforce Singapore" dan "SkillsFuture".
Jerman memiliki Federal Employment Agency yang menjalankan fungsi desain pelatihan terintegrasi dengan pasar kerja.
Irlandia, setelah dihantam krisis ekonomi, membentuk Jobs Initiative Taskforce yang kemudian menjadi katalis pembentukan kebijakan kerja jangka panjang.
Semua negara ini menolak menyerahkan urusan kerja kepada pasar bebas semata. Mereka memilih hadir secara aktif—dan hasilnya jelas: stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Sebaliknya, Indonesia tertinggal. Kita belum memiliki lembaga yang bisa dimintai tanggung jawab atas target penciptaan kerja setiap tahun. Kita menyerahkan harapan besar ini pada pertumbuhan ekonomi yang tak selalu berpihak pada rakyat kecil.
Indonesia bisa belajar dari mereka, namun tetap dengan pendekatan kontekstual. Satgas adalah solusi awal yang efisien dan berorientasi pada dampak.
Jika terbukti berhasil, maka transformasinya menjadi kementerian bukan sekadar opsi, tapi keniscayaan.
Di tengah dunia yang berubah cepat karena otomatisasi, disrupsi teknologi, dan krisis iklim, negara tidak bisa terus berharap pasar menciptakan pekerjaan.
Negara harus hadir secara aktif. Penciptaan kerja tidak boleh menjadi efek samping pertumbuhan—ia harus menjadi tujuan utama.
Satgas adalah langkah pertama menuju tujuan itu. Kementerian Lapangan Kerja adalah bentuk final dari tanggung jawab negara atas hak dasar setiap warga: hak untuk bekerja.
Sudah waktunya Indonesia berhenti menjadikan pekerjaan sebagai janji politik lima tahunan. Sudah saatnya persoalan ketenagakerjaan diselesaikan secara matang, terencana, dan berkelanjutan.
Penciptaan lapangan kerja harus menjadi kebijakan yang diinstitusikan, dijalankan dengan komitmen, dan diawasi secara terbuka oleh publik.
Sebab, negara yang gagal menyediakan pekerjaan bukan hanya gagal secara ekonomi, melainkan kehilangan makna keberadaannya di mata rakyatnya.