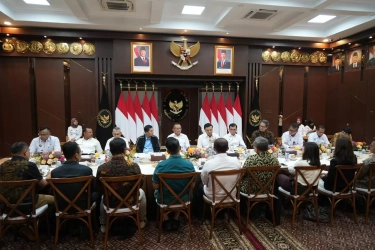Dakwaan Peradaban atas Kematian Anak
APAKAH kematian seorang anak sekolah dasar yang memilih mengakhiri hidupnya dengan seutas tali adalah tragedi tunggal yang berdiri sendiri, ataukah peristiwa itu sesungguhnya merupakan dakwaan paling keras terhadap peradaban yang kita bangun dengan penuh kebanggaan semu?
Pertanyaan ini bukan sekadar retorika di ruang diskusi akademis, melainkan fakta paling tidak pasti sekaligus paling penting yang menghantui kita hari ini: mengapa anak-anak yang seharusnya sibuk menertawakan dunia dalam permainan justru memilih menihilkan eksistensi mereka demi "meringankan" beban orang dewasa?
Di balik diamnya mereka di meja makan—yang sering kali kita terjemahkan secara naif sebagai kepatuhan—mungkin tersimpan jeritan paling nyaring yang gagal ditangkap oleh radar empati kita yang tumpul.
Fenomena memilukan ini tidak bisa lagi kita pandang sebelah mata sebagai kasus individual atau anomali statistik belaka.
Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat 25 kasus bunuh diri anak sepanjang tahun 2025 bukanlah sekadar deretan angka mati di atas kertas laporan tahunan, melainkan monumen kegagalan sistem perlindungan anak kita (KPAI, 2025).
Angka ini menjeritkan realitas bahwa sekolah, keluarga, dan masyarakat seakan telah bersekongkol dalam kebisuan emosional yang mematikan.
Anak-anak kita mungkin cerdas dan lincah mengoperasikan gawai canggih, tapi mereka gagap dan lumpuh ketika harus membahasakan rasa sakit batinnya.
Baca juga: Negara Sibuk Memberi Makan, tapi Lalai Menjamin Pendidikan
Budaya patriarki dan feodal yang menuntut mereka untuk "nrimo", patuh, dan tidak cengeng, secara sistematis telah mematikan kosakata emosi mereka sejak dini.
Ketika bahasa verbal tidak lagi tersedia untuk menyalurkan derita, maka tubuhlah yang mengambil alih narasi tersebut: melalui perilaku self-harm atau, yang paling tragis, bunuh diri (Talmon & Ditzer, 2023).
Bukti paling nyata dan menyayat hati dari tesis ini baru saja menampar kesadaran kita lewat tragedi di Ngada, Nusa Tenggara Timur, pada awal 2026 ini.
Seorang siswa SD berinisial YBS, yang baru berusia 10 tahun, memilih jalan pintas karena ibunya tidak mampu membelikan buku dan pena seharga kurang dari sepuluh ribu rupiah.
Kasus ini bukan sekadar soal kemiskinan ekonomi, melainkan bukti brutal bagaimana seorang anak menginternalisasi dirinya sebagai "beban biaya" bagi keluarganya.
Dalam logika sederhananya yang tragis, YBS melakukan kalkulasi: jika keberadaan saya menyusahkan ibu yang sudah lelah bekerja serabutan, maka ketiadaan saya adalah solusinya.
Ini adalah bentuk ekstrem dari apa yang disebut sebagai parentifikasi patologis, di mana anak secara tidak sadar mengambil alih tanggung jawab emosional dan beban hidup orangtuanya (Durlak et al., 2011).
YBS menjadi martir bagi kemiskinan struktural yang gagal diselesaikan oleh negara, meninggalkan surat terakhir yang meminta ibunya merelakan kepergiannya—sebuah pesan yang seharusnya menjadi tamparan keras bagi para pembuat kebijakan.
Sekolah sebagai pabrik kepatuhan
Selama puluhan tahun, institusi pendidikan kita perlahan, tapi pasti telah bergeser fungsi dari taman bermain yang memanusiakan menjadi "pabrik kepatuhan".
Meminjam istilah filsuf Michel Foucault, tubuh-tubuh mungil anak-anak kita sedang didisiplinkan menjadi docile bodies atau tubuh yang patuh semata (Foucault, 1977).
Sistem pendidikan kita mendesain anak untuk patuh demi memenuhi standar angka, akreditasi, dan administrasi, bukan untuk memanusiakan mereka sebagai individu yang unik.
Di atas kertas dan pidato pejabat, kita lantang meneriakkan jargon "Merdeka Belajar", tapi realitas di lapangan menunjukkan guru-guru yang terbelenggu oleh beban administratif aplikasi digital dan tuntutan birokrasi.
Baca juga: Rp 10.000, Hak Anak, dan Runtuhnya Negara Kesejahteraan
Ketika guru terlalu sibuk mengejar centang biru di aplikasi pelaporan kinerja, tatapan kosong murid yang sedang depresi di pojok kelas luput dari pengamatan (Alanoglu & Demirtas, 2021).
Lebih jauh lagi, sekolah sering kali tanpa sadar mengajarkan kurikulum tersembunyi (hidden curriculum): bahwa "yang kuat yang berkuasa."
Kasus perundungan sadis di Sukabumi, di mana seorang siswa SD dipatahkan tulang lengannya oleh teman sekelasnya, serta tragedi jatuhnya siswi SD dari lantai empat gedung sekolah di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, menunjukkan bahwa sekolah telah berubah menjadi arena Darwinian yang brutal.
Dalam kasus Sukabumi, intimidasi yang dialami korban agar tidak melapor menunjukkan adanya reproduksi kekerasan struktural: anak-anak meniru cara orang dewasa membungkam kebenaran dengan kekuatan.
Sementara itu, kasus di Pesanggrahan dan Sawahlunto menjadi bukti bahwa bullying bukan sekadar "kenakalan anak-anak" yang bisa dimaklumi dengan kalimat "namanya juga anak-anak", melainkan ancaman nyawa yang nyata.
Sekolah menjadi tempat yang tidak aman, di mana anak merasa diawasi, dinilai, dan dihakimi, bukan dilindungi.
Runtuhnya benteng masa kecil
Sosiolog Neil Postman puluhan tahun lalu sudah memperingatkan kita tentang The Disappearance of Childhood atau hilangnya masa kanak-kanak (Postman, 1994).
Kini, ramalan suram itu tergenapi dengan sempurna: dinding pemisah antara dunia anak dan dunia dewasa telah runtuh di bawah gempuran tekanan akademis, sosial, dan digital.
Gawai dan media sosial telah meruntuhkan privasi dan kepolosan masa kecil. Anak SD hari ini terpapar kecemasan eksistensial orang dewasa—mulai dari kekerasan verbal, seksualitas yang belum waktunya, hingga keputusasaan ekonomi seperti yang dialami YBS—tanpa memiliki kematangan mental yang cukup untuk memprosesnya.
Jean Baudrillard menyebut fenomena kepalsuan dunia modern ini sebagai simulacra: citra kebahagiaan palsu di media sosial yang menutupi batin yang keropos (Baudrillard, 1981).
Baca juga: Lebih Prioritas Mana: MBG atau Penciptaan Lapangan Kerja?
Anak-anak kita hidup dalam Panopticon Digital, merasa diawasi dan dinilai terus-menerus oleh netizen atau teman sebayanya, menciptakan tekanan psikologis tanpa jeda (Weissman, 2021).
Mereka melihat standar hidup yang tidak realistis di layar kaca, lalu membandingkannya dengan realitas hidup mereka yang mungkin penuh kekurangan. Kesenjangan inilah yang menciptakan lubang hitam keputusasaan di dada mereka.
Lantas, apa yang harus dilakukan? Kita tidak butuh sekadar seminar motivasi, spanduk "Stop Bullying" yang dipajang di gerbang sekolah, atau pidato pejabat yang penuh keprihatinan sesaat. Kita memerlukan revolusi empati yang sistemik dan radikal.
Pertama, negara harus hadir dengan mewajibkan Guru Bimbingan Konseling (BK) di setiap SD dengan rasio yang manusiawi (misalnya 1:150), bukan membebankan masalah psikologis anak pada guru kelas yang sudah kelelahan mengurus administrasi (Sukadari, 2021).
Kesehatan mental harus menjadi fondasi pendidikan, bukan sekadar ornamen pelengkap. Skrining kesehatan mental berkala harus sama wajib dan rutinnya dengan imunisasi fisik atau penimbangan berat badan.
Kedua, kita perlu merombak definisi "prestasi." Kurikulum Social Emotional Learning (SEL) harus menjadi menu utama pembelajaran, bukan sekadar ekstrakurikuler pilihan.
Mengajarkan anak cara mengelola rasa kecewa, mengenali emosi diri, dan membangun resiliensi (ketahanan mental) jauh lebih vital daripada sekadar memaksa mereka menghafal rumus yang jawabannya bisa ditemukan dalam hitungan detik di mesin pencari (Durlak et al., 2011).
Ketiga, dan yang paling sulit, adalah refleksi kolektif kita sebagai orangtua dan pendidik. Kita harus berhenti memandang anak sebagai trofi kebanggaan keluarga atau investasi masa depan yang harus memberikan imbal balik ekonomi. Kita harus mulai melihat mereka sebagai manusia utuh dengan segala kerentanannya.
Kita perlu menciptakan ruang aman di rumah dan di sekolah, di mana seorang anak tidak takut dihakimi atau dimarahi saat ia berkata, "Aku sedang tidak baik-baik saja."
Kasus bunuh diri anak di NTT, Jakarta, dan daerah lainnya adalah puncak gunung es dari penderitaan massal yang tak terlihat.
Jika kita tidak segera mengubah haluan—dari sistem yang memuja hasil akhir menuju sistem yang memuliakan manusia—maka sesungguhnya kita sedang mempersiapkan satu generasi rapuh yang mati kesepian di tengah keramaian.
Menyelamatkan satu nyawa anak jauh lebih berharga daripada seribu piagam penghargaan sekolah Adiwiyata sekalipun.