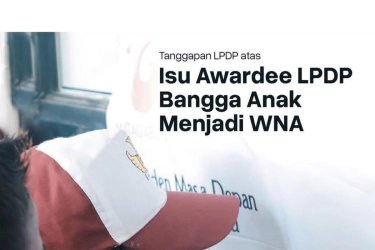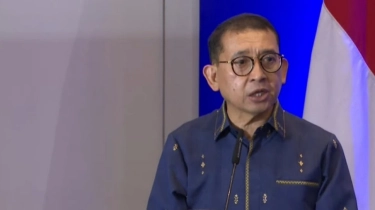Menata Ulang Politik Hijau: Refleksi Bencana Sumatera
SATU bulan lebih Sumatera hidup berdampingan dengan air dan lumpur. Banjir datang bukan hanya sekali, melainkan berulang, seolah menegaskan bahwa ini bukan kecelakaan, melainkan manifesto kegagalan tata kelola: Sebuah surat terbuka yang ditulis dengan air dan lumpur.
Pada titik ini krisis politik-ekologis menuntut pertanggungjawaban kolektif dari para pengambil keputusan, dan yang lebih penting dari partai politik sebagai arsitek utama kebijakan negara. Disini juga ironi “Politik Hijau” tersingkap: sebuah narasi yang spektakuler di panggung global, namun ringkih di tingkat implementasi lokal.
Politik hijau di Indonesia hari ini berada dalam kondisi dualitas yang merusak. Satu sisi, diagungkan dalam rencana pembangunan jangka panjang dan perjanjian iklim internasional, tapi lain sisi dikorbankan setiap kali berhadapan dengan kepentingan modal.
Bencana di Sumatera merupakan harga mahal dari praktik greenwashing elektoral dan kebijakan yang gagal menempatkan ekologi sebagai pilar kedaulatan. Alam direduksi hanya sebagai komoditas yang dapat dikonversi menjadi keuntungan politik dan ekonomi jangka pendek.
Karena itu, menata ulang politik hijau bukan lagi sekadar pilihan ideologis, melainkan keharusan etis demi menjamin keselamatan hidup dan keberlanjutan. Menata ulang politik hijau sama halnya menempatkan ekologi sebagai variabel strategis negara, setara dengan stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
Krisis lingkungan tidak lagi jadi isu sektoral, melainkan risiko sistemik yang berdampak pada ketahanan pangan, kesehatan publik, stabilitas sosial, dan beban fiskal negara. Di Indonesia kebijakan lingkungan acapkali hanya ditempatkan sebagai “pengendalian dampak”, bukan “perancangan sistem”.
Misalnya, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hanya berfungsi sebagai syarat administratif proyek, bukan instrumen korektif yang menentukan boleh atau tidaknya suatu kebijakan dijalankan. Padahal politik hijau menuntut perubahan paradigma: lingkungan bukan lagi pandang sebagai objek yang dikelola setelah keputusan ekonomi diambil, melainkan fondasi awal perumusan kebijakan publik.
Semua kebijakan, mulai dari perencanaan tata ruang, investasi, hingga strategi industri harus berdasarkan daya dukung lingkungan. Politik hijau harus hadir bukan sebagai jargon kampanye, namun sebagai reposisi radikal arah pembangunan. Karena tanpa koreksi mendasar terhadap logika politik yang memuja pertumbuhan tanpa batas, demokrasi akan terus mewariskan krisis ekologis dan menjadi beban lintas generasi.
Di sinilah relevansi pemikiran Robyn Eckersley tentang ecological democracy. Ia menegaskan bahwa negara modern harus bertransformasi menjadi green state, yang menjadikan keberlanjutan ekologis sebagai mandat etis dan konstitusional.
Demokrasi ekologis bukan sekadar partisipasi publik dalam isu lingkungan, melainkan integrasi nilai ekosentris ke dalam seluruh siklus kebijakan: perencanaan, penganggaran, implementasi, dan evaluasi.
Dalam hal ini, politik hijau tidak cukup hanya dipahami sebagai keberpihakan normatif pada alam. Harus dibaca sebagai agenda teknokratik: bagaimana negara merancang regulasi, insentif, dan mekanisme pengambilan keputusan yang menjadikan keberlanjutan ekologis sebagai variabel utama, bukan eksternalitas yang dikompensasi di akhir.
Lebih jauh, politik hijau menuntut reposisi peran negara dan partai politik: dari sekadar fasilitator pertumbuhan ekonomi menjadi pengelola risiko ekologis jangka panjang. Memiliki keberanian untuk menetapkan batas ekologis (ecological limits) dalam kebijakan pembangunan, meskipun berhadapan dengan tekanan modal dan kalkulasi elektoral.
Tanpa perubahan paradigma ini, politik hijau akan berhenti sebagai jargon. Akan terus dielu-elukan dalam manifesto, tetapi absen dalam desain anggaran, regulasi tata ruang, dan penegakan hukum lingkungan.
Dengan demikian, menata ulang politik hijau bukan soal menambah kata “hijau” dalam dokumen kebijakan, melainkan menata ulang cara negara berpikir, merencanakan, dan memutuskan. Karena jika tidak, krisis ekologis akan terus menjadi cermin paling jujur dari kegagalan politik kita sendiri.
Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
Konstitusi Indonesia telah memberikan arah pembangunan yang visioner: demokrasi ekonomi yang menekankan kebersamaan, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Tentu nilai-nilai ini bukan sekadar hiasan konstitusional, melainkan prinsip dasar untuk merumuskan ulang bagaimana pembangunan seharusnya dilakukan. Karenanya pembangunan mesti diarahkan pada transformasi paradigma dengan menempatkan pasal 33 UUD 1945 sebagai pilar utama untuk membangun ekonomi yang tidak hanya bertumbuh, tetapi juga berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak kepada rakyat.
Lebih jauh, reformasi hukum bukan hanya soal mengganti pasal, namun mengubah arah pembangunan: dari ekstraksi ke regenerasi, dari pertumbuhan ke perawatan, dari elitis ke partisipatif.
Ujian integritas partai politik
Partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi, harus menjadi lokomotif gagasan dan kebijakan publik. Namun dalam praktiknya, isu lingkungan acapkali diperlakukan sebagai dekorasi kampanye yang muncul di manifesto namun hilang di meja legislasi. Politik hijau berhenti sebagai slogan, tidak pernah benar-benar menjelma menjadi komitmen struktural.
Disadari atau tidak, demokrasi kita hari ini masih terlalu sibuk menghitung suara, namun abai menghitung daya dukung lingkungan. Pemilu berlangsung lima tahunan, sementara kerusakan ekologis terus mewariskan beban kepada generasi mendatang. Inilah paradoks demokrasi elektoral: sah secara prosedural, namun rapuh secara etis.
Alih-alih memperbaiki keadaan, demokrasi malah jadi mesin reproduksi krisis yang terus berulang dan membebani masa depan. Pada titik ini, demokrasi terperangkap dalam ruang deliberasi etis di arena tawar-menawar kepentingan, dimana keselamatan ekologis dikalahkan oleh keuntungan jangka pendek dan stabilitas politik semu.
Karena partai politik lebih akrab dengan investor dibandingkan dengan ekosistem, maka yang lahir bukan kebijakan publik, melainkan kebijakan transaksional. Hutan hanya menjadi komuditas, sungai menjadi saluran, dan tanah kehilangan makna sosial-ekologisnya. Dalam kerangka ini, etika politik ekologis jadi penting dan menuntut keberanian untuk mengatakan tidak pada kebijakan yang merusak lingkungan, meskipun itu menguntungkan dalam jangka pendek.
Disini partai juga diuji integritasnya: apakah benar-benar mewakili kepentingan rakyat, atau sekadar menjadi perantara modal dan oligar.
Seorang pemikir demokrasi ekologis John Dryzek mengingatkan bahwa krisis lingkungan adalah ujian paling serius bagi demokrasi modern. Menurutnya partai yang serius menangani krisis ekologis tidak cukup hanya merumuskan slogan hijau dalam platformnya tetapi harus menciptakan ruang deliberatif, memperluas partisipasi publik, dan menerapkannya dalam kebijakan nyata untuk menghadapi kerusakan lingkungan yang sistemik.
Ujian etika partai politik disini, bukan lagi soal ideologi kiri atau kanan, melainkan soal keberpihakan pada lingkungan hidup. Karena demokrasi tanpa ekologi adalah demokrasi yang bunuh diri secara pelan-pelan. Ketika partai politik gagal menjadikan lingkungan sebagai komitmen etis dan arah kebijakan, maka demokrasi akan kehilangan makna yang sebenarnya.
Bilamana itu terjadi, yang tenggelam bukan hanya rumah-rumah warga dan hutan yang rusak, namun juga harapan publik: politik sudah tak mampu menjaga kehidupan kolektif. Dan partai politik akan tercatat bukan sebagai penjaga demokrasi, melainkan sebagai aktor yang membiarkan demokrasi runtuh bersama rusaknya bumi.
Membaca bencana sebagai teks politik
Banjir yang meluluhlantakkan Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara bukan sekadar peristiwa alam yang datang tanpa sebab. Ini adalah teks politik yang dapat dibaca dengan gamblang nan jernih: tata kelola yang kompromistis, serta praktik ekonomi ekstraktif yang dilegalkan melalui kebijakan negara.
Di negara demokrasi, bencana ekologis hampir dapat dipastikan hasil dari sebuah keputusan politik. Namun ketika banjir melanda, ungkapan elite politik yang terdengar pertama kali di telinga kita hampir selalu sama, yakni, "ini bencana alam".
Pernyataan itu memang terdengar netral, bahkan menenangkan, tapi justru disitu pangkal masalahnya. Bencana banjir direduksi menjadi takdir, bukan akibat dari salah kebijakan. Dengan menyebut “banjir sebagai peristiwa alam” itu artinya seakan tanggung jawab politik disingkirkan dari meja kekuasaan.
Padahal di negara demokrasi seperti Indonesia, partai politik adalah jantung dari proses pengambilan keputusan publik. Melalui partai kebijakan itu dirumuskan, kekuasaan didistribusikan, dan arah pembangunan ditentukan. Karena itu, ketika bencana ekologis menjadi fenomena yang terus berulang. Pertanyaan sederhananya, mengapa sistem politik membiarkan kerusakan lingkungan berlangsung tanpa koreksi berarti?
Data Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) 2018, menyebutkan, bahwa Indonesia setiap tahunnya kehilangan hutan seluas 680 ribu hektar, dan merupakan terbesar di region Asia Tenggara.
Sedangkan data kerusakan sungai yang dihimpun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tercatat bahwa, dari 105 sungai yang ada, 101 sungai diantaranya dalam kondisi tercemar sedang hingga berat. Angka ini bukan hanya sekadar statistik lingkungan, melainkan indikator kegagalan tata kelola politik dan kebijakan pembangunan yang masih menempatkan aktivitas ekstraktif sebagai mesin utama pertumbuhan.
Ketika kerusakan dibiarkan berulang dan pengawasan melemah, sesungguhnya negara sedang memproduksi risiko ekologis yang kemudian hari menjelma menjadi bencana dan masyarakat yang menjadi korban.
Potret yang lebih gamblang terlihat dari data Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) yang mencatat bahwa sekitar 159 juta hektare lahan telah terkapling dalam izin investasi industri ekstraktif. Secara legal, penguasaan wilayah daratan oleh korporasi telah mencapai 82,91 persen, sementara wilayah laut berada pada angka 29,75 persen. Angka-angka ini bukan sekadar statistik administratif, melainkan cermin ketimpangan struktural dalam penguasaan ruang hidup yang berdampak langsung pada keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial.
Di negara demokrasi, partai politik seyogyanya hadir sebagai penjaga masa depan, bukan semata pengelola kekuasaan. Demokrasi bukan ansih soal pemilu, kursi parlemen, atau sirkulasi elite, melainkan sebagai sistem etika publik. Di mana di dalamnya melekat tanggung jawab kolektif untuk menjamin keadilan, termasuk keadilan ekologis. Karena tanpa komitmen tersebut demokrasi berisiko kehilangan makna substantifnya dan tereduksi menjadi prosedur semata.
Pun demikian, setiap kebijakan ekonomi baik yang dirumuskan oleh pemerintah maupun yang diperjuangkan oleh partai politik mesti diletakkan dalam kerangka konstitusional. Komitmen partai terhadap keberlanjutan lingkungan tidak boleh berhenti pada retorika kampanye atau simbolisasi kebijakan, melainkan harus teruji dan berani menolak praktik pembangunan yang merusak alam.
Tag: #menata #ulang #politik #hijau #refleksi #bencana #sumatera