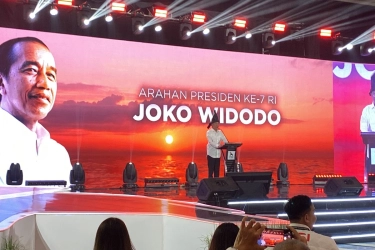Tambang dan Tanggung Jawab Negara
WACANA moratorium izin tambang kembali menyeruak di ruang publik nasional. Dari Nusa Tenggara Barat hingga Papua, berbagai organisasi masyarakat sipil menyerukan penghentian sementara penerbitan izin pertambangan mineral dan batubara. Desakan ini muncul seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap kerusakan ekosistem, konflik sosial di wilayah tambang, dan kebocoran penerimaan negara yang seharusnya mengalir ke kas publik.
Di balik riuh suara tersebut, moratorium bukan sekadar tuntutan emosional, melainkan refleksi dari kegelisahan atas arah tata kelola sumber daya alam yang kian menjauh dari mandat konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam beberapa tahun terakhir, geliat industri tambang di Indonesia menunjukkan paradoks ganda. Di satu sisi, sektor ini masih menjadi penopang utama penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penyerap tenaga kerja, dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Namun di sisi lain, tambang juga menjadi sumber konflik agraria, kerusakan lingkungan, serta simbol ketimpangan ekonomi yang mencolok.
Tidak sedikit masyarakat adat yang kehilangan ruang hidupnya, sungai-sungai yang tercemar limbah tailing, dan lahan produktif yang berubah menjadi kolam bekas galian. Situasi ini menimbulkan pertanyaan, apakah negara benar-benar sedang “menguasai” sumber daya alamnya, atau justru dikuasai oleh logika ekonomi ekstraktif yang mengabaikan keadilan ekologis?
Desakan moratorium sebetulnya bukan hal baru. Dalam sejarah kebijakan lingkungan Indonesia, pemerintah pernah memberlakukan moratorium izin baru untuk pembukaan hutan primer dan lahan gambut melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pada kurun waktu 2011–2019.
Langkah itu dinilai berhasil menahan laju deforestasi, meskipun menghadapi banyak celah implementasi. Artinya, moratorium terbukti dapat menjadi instrumen kebijakan transisional untuk memperbaiki tata kelola, bukan semata-mata penghentian aktivitas ekonomi. Pertanyaannya berikutnya, apakah moratorium tambang juga bisa memainkan fungsi serupa dalam konteks sumber daya mineral dan batubara?
Antara Regulasi Baru Pertambangan dan Hak Rakyat
Momentum pembaruan hukum di sektor pertambangan datang bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini mengandung empat materi muatan baru yang menarik untuk dikaji dalam konteks moratorium.
Pertama, adanya penyesuaian sejumlah ketentuan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, pengaturan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara yang dapat diberikan secara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi.
Ketiga, pemberian WIUP atau WIUPK untuk kepentingan pendidikan tinggi kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta dengan memperhatikan akreditasi dan luas wilayah. Keempat, penegasan bahwa penerimaan negara bukan pajak hasil pertambangan dikelola langsung oleh Menteri.
Sekilas, pengaturan tersebut terlihat progresif karena memberikan ruang bagi aktor ekonomi rakyat seperti koperasi dan UKM untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya mineral. Namun dalam praktik, kebijakan semacam ini justru dapat menjadi problematis apabila tidak diiringi mekanisme pengawasan yang ketat. Pengutamaan pihak tertentu tanpa sistem transparansi berpotensi melahirkan “izin prioritas” yang hanya berpindah tangan dari korporasi besar ke kelompok baru yang memiliki kedekatan politis.
Inilah sebabnya moratorium menjadi penting bukan untuk menghambat investasi, tetapi sebagai jeda kebijakan agar negara dapat menata ulang prinsip pemerataan dan keadilan dalam sistem perizinan.
Di tingkat peraturan pelaksana, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 juga membawa perubahan signifikan terhadap PP Nomor 96 Tahun 2021. Beberapa pasal yang diubah, antara lain Pasal 22 tentang persyaratan calon peserta lelang WIUP, Pasal 54 tentang jangka waktu operasi produksi, serta Pasal 56 yang menegaskan kriteria kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian.
Selain itu, terdapat tambahan Pasal 83A yang memperbolehkan penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan dalih peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dari perspektif hukum administrasi, baik UU 2/2025 maupun PP 25/2024 tidak melarang pemerintah untuk melakukan moratorium. Peraturan tersebut hanya mengatur tata cara dan kriteria pemberian izin, bukan mewajibkan agar izin baru selalu diterbitkan setiap tahun.
Dengan demikian, moratorium tetap dapat diberlakukan sepanjang didasarkan pada pertimbangan hukum yang sah, bersifat sementara, dan ditujukan untuk evaluasi kebijakan. Pemerintah memiliki dasar kewenangan untuk itu, baik melalui Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, maupun Instruksi Presiden.
Dalam sistem hukum Indonesia, moratorium bukan bentuk pelanggaran hukum, melainkan ekspresi dari fungsi negara untuk “menguasai” dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Dengan dasar tersebut, konsep moratorium tambang justru sejalan dengan amanat Hak Menguasai Negara.
Hak ini, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, bukan sekadar kewenangan formal untuk memberikan izin, tetapi mencakup fungsi mengatur, mengelola, mengusahakan dan mengawasi agar seluruh hasil pengusahaan sumber daya alam diarahkan untuk kemakmuran rakyat.
Artinya, negara bukan hanya bertugas sebagai regulator yang memberi izin, melainkan juga penjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan kelestarian ekologis. Dalam kerangka itulah, moratorium menjadi instrumen hukum yang sahih secara konstitusional.
Menata Kembali Makna Kedaulatan Sumber Daya
Moratorium izin tambang apabila dijalankan dengan desain hukum yang cermat, dapat menjadi momentum reformasi tata kelola sumber daya alam. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, moratorium tidak boleh hanya berwujud “pengumuman penghentian izin”.
Kebijakan itu harus disertai dengan serangkaian kebijakan struktural mulai dari audit nasional perizinan tambang, evaluasi kewajiban reklamasi dan pascatambang, peninjauan ulang penerimaan negara bukan pajak, serta integrasi data perizinan lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Audit perizinan menjadi langkah krusial karena banyak izin yang tumpang-tindih, berada di kawasan lindung, atau diberikan tanpa kajian lingkungan memadai. Dalam sejumlah laporan investigatif, termasuk yang diungkapkan oleh Publish What You Pay Indonesia dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), ditemukan ratusan izin pertambangan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan dan wilayah adat.
Di sisi lain, masih terdapat ribuan perusahaan yang menunggak kewajiban PNBP, sementara daerah penghasil tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang proporsional. Moratorium memberi kesempatan bagi negara untuk menata ulang sistem ini agar tidak terus-menerus menjadi ladang kebocoran fiskal dan ketidakadilan sosial.
Selain audit, pemerintah juga perlu menyiapkan rancangan mekanisme transisi pasca moratorium. Ketika moratorium dicabut, sistem perizinan baru harus lebih transparan, berbasis data, dan berorientasi pada keadilan sosial-ekologis. Salah satu rekomendasi yang banyak disuarakan adalah penerapan sistem informasi publik terpadu yang menampilkan seluruh peta WIUP, status izin, pemegang saham, hingga data kontribusi keuangan.
Langkah ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga menghidupkan semangat keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dari sisi ekonomi, moratorium juga memberi ruang bagi negara untuk mengalihkan fokus dari sekadar ekspor bahan mentah menuju hilirisasi dan nilai tambah. Pemerintah bisa menggunakan masa jeda ini untuk memperkuat infrastruktur industri pengolahan, memperluas investasi pada teknologi pemurnian, dan memperbaiki skema pembagian manfaat antara pusat dan daerah.
Dengan demikian, ketika aktivitas tambang kembali dibuka, ekonomi nasional tidak hanya bergantung pada ekstraksi, tetapi juga memiliki basis industri yang berkelanjutan. Namun, tentu tidak dapat diabaikan bahwa moratorium memiliki konsekuensi ekonomi jangka pendek.
Penundaan izin baru bisa menurunkan arus investasi dan berdampak pada penerimaan negara. Oleh sebab itu, perancang kebijakan perlu menyiapkan kompensasi yang adil bagi daerah penghasil serta menjamin kepastian hukum bagi investor yang sudah beroperasi secara sah. Prinsipnya, moratorium harus bersifat non-retroaktif, yakni tidak mengubah hak yang telah diberikan sebelum kebijakan diterapkan.
Dalam perspektif konstitusi, kebijakan moratorium tambang sebenarnya merupakan bentuk nyata dari pengamalan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Moratorium mengembalikan posisi negara sebagai pengendali, bukan sekadar penonton di tengah laju eksploitasi sumber daya alam. Di sinilah letak filosofi “Hak Menguasai Negara” yaitu negara memiliki mandat moral dan yuridis untuk memastikan kekayaan alam tidak dikuasai segelintir korporasi, melainkan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Jika izin tambang justru menimbulkan kerusakan lingkungan, menggerus ruang hidup masyarakat, dan mengurangi penerimaan negara, maka moratorium menjadi tindakan konstitusional untuk mengoreksi arah kebijakan yang menyimpang dari makna penguasaan oleh negara.
Lebih jauh, moratorium tambang seharusnya tidak dipahami sebagai upaya anti-investasi, melainkan sebagai strategi pause and reform—berhenti sejenak untuk memperbaiki kerangka hukum dan memastikan pembangunan ekonomi tidak mengorbankan generasi mendatang.
Dalam konteks keadilan antar generasi, moratorium dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk tidak menghabiskan sumber daya alam dalam tempo cepat tanpa memperhitungkan kapasitas regenerasi lingkungan. Energi, mineral, dan batubara adalah kekayaan terbatas; maka keadilan ekologis menuntut adanya pembatasan yang rasional dan terukur.
Pada akhirnya, ujian terbesar moratorium bukan pada perumusan kebijakan, melainkan pada pelaksanaannya. Tanpa sistem pengawasan yang transparan, moratorium berisiko menjadi slogan administratif yang tak berdaya menghadapi tekanan ekonomi-politik. Karena itu, partisipasi publik dan mekanisme keterbukaan informasi menjadi kunci keberhasilan.
Negara perlu memastikan setiap proses evaluasi perizinan dapat diawasi oleh masyarakat, akademisi, dan media. Hanya dengan cara itu, moratorium bisa benar-benar menjadi momentum pembelajaran kolektif untuk memperkuat tata kelola pertambangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Di tengah euforia investasi mineral kritis dan energi transisi global, Indonesia dihadapkan pada pilihan fundamental, apakah ingin terus berlari di jalur eksploitasi cepat dengan segala resikonya, atau menempuh jeda bijak melalui moratorium untuk menata kembali arah pembangunan.
Pilihan kedua tampak lebih sulit, tetapi justru lebih beradab. Moratorium tambang adalah bentuk keberanian politik dan moral untuk menegakkan makna sejati Pasal 33 UUD 1945. Kebijakan tersebut menandai bahwa negara tidak sedang tunduk pada kekuatan pasar, melainkan berdiri sebagai pengatur yang berpihak pada kemakmuran rakyat.
Sejarah membuktikan bahwa bangsa besar tidak diukur dari seberapa cepat ia menambang bumi, melainkan seberapa bijak ia menjaga warisan alam bagi anak cucunya. Moratorium tambang, bila dijalankan dengan niat tulus dan kerangka hukum yang kokoh, akan menjadi babak baru dalam perjalanan panjang kedaulatan sumber daya alam Indonesia dan dapat dinilai sebuah langkah menuju demokrasi energi yang adil, transparan, dan berkeadilan antar generasi.