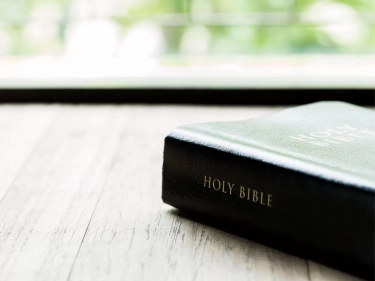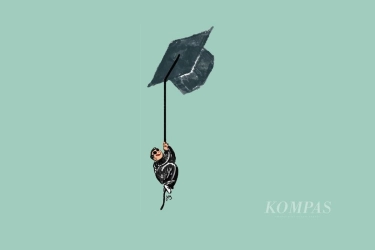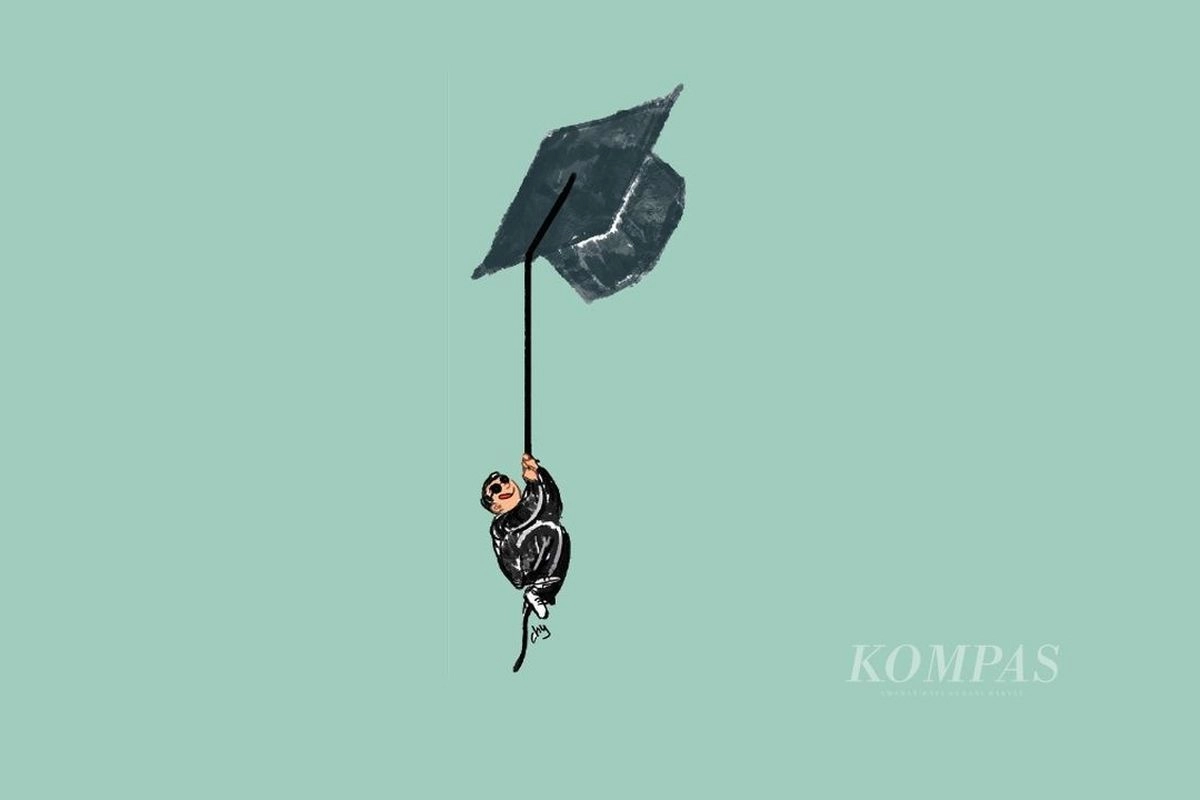
Ketika Guru Besar Turun ke Istana
DI RUANG sunyi kampus, seorang guru besar semestinya berdiri di menara ilmu—bukan di menara kuasa. Ia memegang mandat yang lebih luhur daripada sekadar jabatan: menjaga nalar bangsa dari gelapnya kekuasaan.
Namun, belakangan menara itu tampak bergoyang. Satu per satu intelektual kampus meninggalkan ruang akademik dan turun ke Istana, duduk di kursi birokrasi, menjadi staf ahli, komisaris, atau bahkan menteri.
Fenomena ini tidak lahir dari ruang kosong. Negara yang tengah mencari legitimasi moral kerap meminjam wajah akademisi untuk menutupi borok politik. Ilmu dipanggil bukan untuk menantang kekuasaan, melainkan untuk menjustifikasinya.
Dalam konteks itu, guru besar dihadapkan pada dilema: antara memegang teguh otonomi intelektual atau tunduk pada daya pikat kekuasaan.
Sebagai simbol tertinggi dunia akademik, guru besar bukan hanya pengajar dan peneliti. Ia adalah penuntun etik bangsa—penjaga api rasionalitas di tengah kabut populisme.
Karena itu, ketika ia “turun ke Istana”, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi pribadi, tetapi juga makna kemuliaan akademik itu sendiri.
Secara hukum, tidak ada yang melarang guru besar menjadi pejabat. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan jelas menyebutkan bahwa “Dosen dapat diangkat dalam jabatan pimpinan di perguruan tinggi dan/atau jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
Namun, hukum bukan satu-satunya ukuran moralitas. Bagi dosen yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), juga berlaku Pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menegaskan pentingnya penerapan merit system dan larangan rangkap jabatan yang menimbulkan konflik kepentingan.
Sementara PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS mewajibkan setiap pegawai melaksanakan tugas jabatan dengan penuh tanggung jawab serta tidak menyalahgunakan kewenangan.
Artinya, secara hukum guru besar boleh masuk dalam jabatan struktural pemerintahan, tetapi secara etika akademik, ruang itu tidak sesederhana hitam-putih.
Guru besar berada di wilayah logos, dunia rasio yang menuntut kebebasan berpikir, objektivitas, dan keberanian mengatakan yang benar.
Sementara pejabat berada di wilayah kratos, dunia keputusan yang sarat kompromi, strategi, dan kepentingan politik. Ketika dua dunia ini bertemu, benturan nilai tak terhindarkan.
Etika profesi dosen mengajarkan “kemandirian ilmiah” (academic independence). Ia menuntut jarak epistemik dari kepentingan politik praktis agar ilmu tak terkooptasi oleh kuasa.
Jika jarak itu hilang, maka kebenaran akademik bergeser menjadi pembenaran birokratik. Di titik itu, guru besar kehilangan wajah intelektualnya; ia berubah menjadi teknokrat yang berpikir dengan perintah, bukan dengan nurani.
Dalam sejarah kekuasaan, intelektual selalu digoda. Dari Plato hingga Machiavelli, dari Ibnu Khaldun hingga Hannah Arendt, kekuasaan memiliki daya pikat yang halus bagi pemikir.
Ia menjanjikan peluang untuk menerjemahkan ide menjadi kebijakan, teori menjadi tindakan. Namun, di balik janji perubahan itu, tersembunyi bahaya yang lebih lembut: penjinakan intelektual.
Birokrasi tidak mengenal keberanian intelektual; ia mengenal hierarki, kepatuhan, dan loyalitas. Di ruang itu, kata “kritik” mudah berubah menjadi “pengkhianatan”.
Guru besar yang dulu vokal di kampus, tiba-tiba menjadi bisu di kursi kekuasaan. Ia belajar memilih kata aman, bukan kata benar.
Godaan kekuasaan bukan hanya materi atau jabatan, tetapi pengakuan sosial. Seorang intelektual yang bertahun-tahun menulis di ruang akademik tiba-tiba merasakan sorotan lampu Istana—dilihat, didengar, dan disanjung.
Ia lupa bahwa dalam dunia filsafat, pengakuan tanpa kebebasan hanyalah pujian yang menipu.
Kampus didirikan sebagai ruang otonomi pengetahuan, bukan kantor perpanjangan tangan kekuasaan. Tradisi universitas lahir dari gagasan kebebasan ilmiah: universitas libera. Otonomi itu yang memungkinkan lahirnya peradaban dan kemajuan.
Namun, dalam praktik Indonesia modern, batas antara kampus dan kekuasaan kian kabur. Banyak perguruan tinggi berubah menjadi “pabrik legitimasi” yang sibuk membuat riset pesanan atau seminar yang mendukung kebijakan pemerintah.
Dosen senior menjadi tim perumus kebijakan, dan guru besar menjadi “penasihat politik” yang lebih sibuk di rapat kementerian daripada di ruang kuliah.
Kita lupa bahwa ilmu yang terlalu dekat dengan kuasa kehilangan daya subversifnya. Ia tidak lagi mempertanyakan, tetapi membenarkan.
Dalam bahasa filsafat kontemporer, hal ini disebut degenerasi epistemik—saat pengetahuan berhenti mengoreksi kekuasaan dan justru menjadi alatnya.
Otonomi akademik sejatinya bukan untuk menjauhkan guru besar dari politik, tetapi agar ia tetap mampu berdiri di hadapan politik tanpa kehilangan integritasnya. Kebebasan berpikir adalah bentuk paling tinggi dari pengabdian ilmiah.
Apakah salah jika guru besar menjadi pejabat? Tidak. Yang salah adalah ketika ia kehilangan kemampuan berpikir merdeka.
Negara memang membutuhkan ilmuwan yang masuk ke ruang kebijakan, tetapi bangsa juga memerlukan intelektual yang menjaga jarak agar tidak semua suara akademik menjadi gema kekuasaan.
Dalam tradisi Yunani kuno, Plato dalam Republic (473d–474b) menggambarkan cita-cita negara ideal yang dipimpin oleh philosopher-king—pemimpin yang berpikir seperti filsuf, bukan filsuf yang mengejar kekuasaan.
Dalam kenyataan modern, yang sering terjadi justru sebaliknya: filsuf yang terseret logika kuasa dan melupakan tanggung jawab moralnya.
Sebagaimana Max Weber menulis dalam Politics as a Vocation (1919), politik menuntut etika tanggung jawab (ethics of responsibility), sedangkan ilmu hidup dari etika keyakinan (ethics of conviction).
Ketika guru besar masuk ke dalam politik, dua etika itu saling tarik-menarik. Hanya mereka yang kuat menjaga prinsip yang mampu berdiri di antara keduanya tanpa kehilangan integritas.
Bangsa ini sedang kekurangan teladan moral dari dunia akademik. Banyak guru besar lebih nyaman menjadi komentator kebijakan daripada penjaga integritas ilmu di tengah mahasiswa.
Padahal, gelar profesor bukan sekadar mahkota intelektual, tetapi panggilan moral untuk menegakkan kebenaran di atas keberpihakan.
Hannah Arendt dalam The Human Condition (1958) mengingatkan bahwa ketika vita activa (dunia tindakan dan kekuasaan) menelan vita contemplativa (dunia refleksi), manusia kehilangan ruang berpikir bebas.
Begitu pula ketika intelektual larut dalam kuasa, ia kehilangan kemampuannya untuk berpikir jernih dan bertanya “mengapa.”
Sebagaimana diingatkan Søren Kierkegaard dalam Fear and Trembling (1843), kebenaran bukanlah persoalan kecerdasan, tetapi keberanian untuk tetap teguh di tengah godaan pragmatisme.
Guru besar yang memasuki ruang kekuasaan harus mampu menanggung kesepian moral itu—tetap jujur pada kebenaran meski ia berdiri di ruang kompromi.
Sejarah bangsa ini mencatat bahwa banyak pemimpin lahir dari rahim intelektual. Ki Hajar Dewantara, Mohammad Hatta, Soedjatmoko—mereka hadir di ruang kekuasaan bukan untuk mencari posisi, melainkan menjaga nilai. Mereka adalah contoh bagaimana ilmu dan moralitas dapat berjalan beriringan.
Hari ini, bangsa ini memerlukan sosok serupa: guru besar yang bukan sekadar turun ke Istana, tetapi membawa kampus ke Istana—membawa cara berpikir ilmiah, rasionalitas kebijakan, dan etika publik yang jernih. Sebab ilmu tanpa pengaruh hanyalah wacana, tetapi kekuasaan tanpa ilmu adalah bencana.
Sebagaimana Plato bayangkan dalam Republic, yang ideal bukanlah filsuf yang menjadi raja, melainkan raja yang belajar menjadi filsuf.
Di titik itulah guru besar menemukan kembali makna pengabdiannya: menghadirkan kebijaksanaan dalam kekuasaan tanpa kehilangan kebebasan dalam berpikir.
Ketika guru besar turun ke Istana, pertanyaannya bukan lagi apakah ia pantas, tetapi apakah ia masih bebas. Sebab kebesaran seorang guru besar tidak diukur dari jabatan yang ia duduki, melainkan dari sejauh mana ia menjaga nurani ilmu tetap tegak di hadapan kuasa.
Kebenaran akademik tidak boleh tunduk pada politik. Karena bila ilmu kehilangan otonominya, bangsa kehilangan cahaya pikirannya.
Dan di hari itu, Istana mungkin masih berdiri megah—tetapi menara ilmu telah runtuh dalam diam.