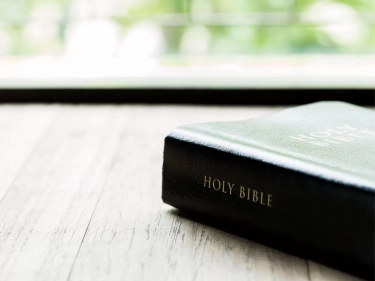''Shutdown'' dan ''Slowdown'': Gelap di Washington, Irit di Indonesia
KETIKA pagi turun di Washington D.C., gedung-gedung federal tampak muram. Pintu kantor tertutup, museum sepi, taman nasional dikunci rapat.
Bukan karena bencana, tetapi karena pemerintah Amerika Serikat “mati suri”. Anggaran tak disahkan, pegawai tak digaji, dan layanan publik berhenti total. Dunia menyebutnya government shutdown.
Di waktu yang hampir bersamaan, di Jakarta, para gubernur menyampaikan protes kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari Rp 919,9 triliun menjadi Rp 693 triliun.
Tak ada yang tutup, tetapi banyak yang tersendat. Negara tak padam, tapi bergerak lambat—slowdown fiskal.
Sekilas, dua peristiwa ini tampak jauh berbeda. Namun jika dicermati, keduanya sama-sama menunjukkan politik yang kehilangan ruang rasional dalam mengelola uang publik.
Amerika terjebak dalam perdebatan ideologis yang membekukan pemerintahan, sementara Indonesia terpaku pada tarik-menarik fiskal antara pusat dan daerah.
Di balik dua benua yang berbeda ini, sesungguhnya tersimpan persoalan serupa: bagaimana uang berubah menjadi alat tawar, bukan alat kerja.
Ketika politik bekukan negara
Di Amerika Serikat, shutdown bukan sekadar simbol kegagalan anggaran, melainkan hasil dari sistem politik yang dibangun di atas keseimbangan kekuasaan yang terlalu kaku.
Undang-undang yang dikenal sebagai "Antideficiency Act" melarang pemerintah federal mengeluarkan uang tanpa persetujuan Kongres.
Begitu tenggat waktu pengesahan anggaran lewat tanpa kesepakatan, seluruh mekanisme fiskal berhenti otomatis. Negara terkunci oleh hukum yang dibuatnya sendiri dan rakyat menanggung akibatnya.
Para politisi di Capitol Hill memperlakukan anggaran seperti medan tempur ideologi. Partai Republik menuntut pemangkasan pajak dan belanja sosial, sementara Partai Demokrat menekan untuk peningkatan dana kesehatan dan lingkungan.
Ketika kompromi gagal, rakyatlah yang menanggung beban: gaji tertunda, layanan publik lumpuh, dan ekonomi terguncang.
Ekonom internasional Prof. Laurence Goldstein dari Harvard Kennedy School menyebut, “Shutdown bukanlah kegagalan fiskal, melainkan kegagalan politik yang dikonversi menjadi bencana ekonomi.”
Kerugian tak hanya bersifat material, tetapi juga moral—karena publik kehilangan kepercayaan pada rasionalitas demokrasi.
Pada titik itu, hukum yang semestinya menjadi penuntun justru berubah menjadi jebakan. Politik kehilangan kemampuan berkompromi, sementara negara kehilangan kemampuan bergerak.
Daerah dipaksa hemat
Indonesia menghadapi krisis yang lebih halus, tapi tak kalah serius. Setelah APBN 2026 disahkan, pemangkasan TKD menimbulkan gejolak di antara para kepala daerah.
Mereka merasa terhimpit oleh kebijakan fiskal yang tak sebanding dengan beban pembangunan di lapangan.
Pemerintah pusat menilai banyak daerah boros, serapan anggaran rendah, dan belanja tak produktif.
Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menyebut, “Belanja daerah masih sering tidak punya dampak ekonomi langsung.” Kritik itu keras, tetapi juga menjadi panggilan untuk introspeksi bersama.
Di lapangan, banyak daerah menghadapi dilema. Mereka harus tetap menjalankan layanan publik, membayar pegawai, dan menuntaskan proyek infrastruktur, meski anggaran berkurang drastis.
Tak ada shutdown seperti di Amerika, tetapi perlambatan ekonomi lokal terasa dalam senyap. Pembangunan tersendat, semangat desentralisasi meredup, dan masyarakat menanggung imbasnya dalam bentuk layanan yang menurun.
Ahli kebijakan publik asal Inggris, Dr. Eleanor Chambers dari London School of Economics, menilai bahwa Indonesia kini berada di simpang jalan. “Kebijakan fiskal top-down dapat melemahkan desentralisasi yang menjadi dasar demokrasi Indonesia sendiri.”
Sementara itu, Dr. Hiroshi Tanaka, pakar manajemen keuangan internasional dari Tokyo University, menegaskan pentingnya keseimbangan antara kontrol dan kepercayaan.
“Jika pusat terlalu dominan, daerah kehilangan motivasi berinovasi. Namun bila dibiarkan bebas, korupsi meningkat. Solusinya ada pada transparansi berbasis data, bukan sekadar pemangkasan.”
Senada dengan itu, Prof. Amara De Vries, ahli pembangunan berbasis anggaran dari Utrecht University, berpendapat bahwa pemangkasan TKD seharusnya dibaca sebagai momentum pembenahan, bukan hukuman.
“Pembangunan berbasis anggaran tak cukup diukur dari besar dana, tetapi dari arah dan dampaknya terhadap masyarakat,” ujarnya.
Menemukan jalan tengah
Kedua sistem—Amerika yang terlalu kaku dan Indonesia yang terlalu lentur—memerlukan cara pandang baru agar tidak terus terjebak dalam lingkaran kebuntuan fiskal. Politik dan keuangan publik seharusnya bekerja dalam harmoni, bukan saling menyandera.
Pertama, perlu dibangun sistem anggaran refleksif, yakni mekanisme otomatis yang menyesuaikan prioritas saat krisis terjadi.
Ketika defisit membesar, pos non-esensial otomatis ditunda tanpa menunggu keputusan politik baru. Cara ini menjaga stabilitas tanpa menimbulkan kekacauan administratif seperti shutdown di Amerika atau pemangkasan mendadak seperti di Indonesia.
Kedua, dibentuk komisi fiskal independen lintas partai dan daerah untuk menengahi tarik-menarik kepentingan politik.
Komisi ini bukan lembaga pengawas, melainkan penjaga rasionalitas fiskal yang memastikan keputusan dibuat berdasar data dan urgensi, bukan tekanan politik.
Ketiga, diperkuat transparansi real-time berbasis digital, agar publik dapat melihat ke mana uang negara mengalir—dari Washington hingga Wonosobo.
Dengan open data yang mudah diakses, kepercayaan tumbuh dan politik anggaran menjadi lebih akuntabel.
Pada akhirnya, baik shutdown di Amerika maupun slowdown di Indonesia memperlihatkan kenyataan yang sama: uang negara bukan hanya alat pembangunan, tapi cermin kematangan politik.
Di Amerika, politik yang terlalu kaku membuat negara berhenti bergerak. Di Indonesia, politik yang terlalu cair membuat arah pembangunan kabur.
Keduanya butuh keseimbangan baru—bukan antara kanan dan kiri, pusat dan daerah, tetapi antara akal sehat dan keberanian untuk berubah.
Tag: #shutdown #slowdown #gelap #washington #irit #indonesia