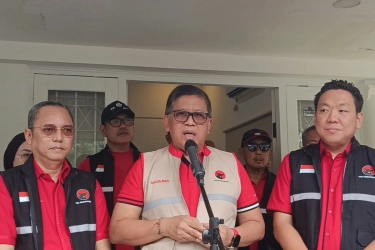4 Pulau Aceh untuk Sumut: Otonomi Kerdil, Tamparan di Wajah Perdamaian
DI TENGAH riuhnya janji desentralisasi dan otonomi khusus, narasi ironis kembali mencuat dari ujung barat Nusantara: kisah "hilangnya" empat pulau dari pangkuan Aceh.
Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, yang selama ini diakui dan dikelola oleh Kabupaten Aceh Singkil, tiba-tiba berpindah tangan secara sepihak ke Sumatera Utara melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.
Keputusan ini, yang menguap begitu saja dari meja birokrasi Jakarta, memicu gelombang protes dan kebingungan di Bumi Serambi Mekkah, merobek kain perdamaian yang terjahit.
Fakta ini, yang secara gamblang memperlihatkan arogansi kekuasaan pusat, dapat dianalogikan sebagai Jakarta yang seolah sedang bermain papan Monopoli, menggeser kepulauan seperti pion, tanpa sedikit pun mendengar suara lokal.
Ini bukan sekadar sengketa batas wilayah administratif semata. Lebih dari itu, kasus ini adalah cerminan telanjang dari krisis legitimasi dan efektivitas otonomi khusus Aceh pasca-MoU Helsinki.
Insiden ini secara fundamental mempertanyakan sejauh mana otonomi khusus benar-benar memberikan kekuasaan substantif, ataukah ia hanya menjadi simbol kosong di tengah upaya resentralisasi pusat yang tak kunjung berhenti?
Sejarah panjang relasi pusat-daerah di Aceh
Sengketa empat pulau ini bukanlah fenomena baru, melainkan episode terbaru dari ketegangan historis yang tak kunjung usai antara Jakarta dan Aceh.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui bahwa konflik ini telah berlangsung sejak tahun 1928.
Pola intervensi pusat yang berulang ini menunjukkan bahwa relasi kuasa antara Jakarta dan Aceh selalu diwarnai tarik ulur, bahkan setelah era Reformasi. Ini adalah "penyakit turunan" dalam hubungan pusat-daerah yang terus kambuh.
Pasca-Orde Baru, Indonesia mengadopsi desentralisasi secara besar-besaran pada 2001. Kebijakan ini, sebagaimana dianalisis oleh Ostwald (2016), dapat termotivasi secara politik untuk meredam tekanan sentrifugal dan separatisme yang mengancam stabilitas nasional setelah jatuhnya rezim Soeharto.
Namun, Hadiz (2010) dalam karyanya Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia menunjukkan bahwa desentralisasi, alih-alih menyelesaikan masalah, justru dapat membuka medan konflik kewenangan yang baru.
Elite-elite lokal memang memanfaatkan ruang otonomi. Namun, mereka tetap berhadapan dengan logika dominasi pusat dan seringkali terjerat dalam sistem kekuasaan "predatory" yang memanfaatkan desentralisasi untuk kepentingan elite.
Dalam sengketa pulau ini, terlihat jelas bagaimana pemerintah pusat memilih untuk menunjukkan amnesia historis yang mencolok di hadapan klaim Aceh.
Aceh bersandar pada bukti-bukti historis, sosiologis, bahkan administratif yang kuat: KTP warga yang menetap di pulau-pulau tersebut adalah KTP Aceh, infrastruktur fisik seperti prasasti, mushala, dan dermaga dibangun dengan dana Pemerintah Aceh pada tahun 2012, dan batas wilayah telah diketahui turun-temurun oleh masyarakat lokal.
Namun, Kementerian Dalam Negeri justru menolak peta topografi tahun 1978 dan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) sebagai referensi resmi, mendasarkan keputusannya pada analisis spasial yang “lebih relevan”.
Pendekatan ini menunjukkan kecenderungan pemerintah pusat untuk mengabaikan konteks historis dan realitas lokal yang mengakar demi "kebenaran" administratif yang lebih baru dan sepihak.
Hal ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga mengindikasikan bahwa keputusan pusat mungkin didorong oleh motif tersembunyi.
Salah satu motif yang paling santer terdengar adalah potensi kandungan minyak dan gas bumi (migas) di sekitar pulau-pulau yang disengketakan, serta rencana investasi besar dari Uni Emirat Arab (UEA) di sana.
Jika ini benar, maka sengketa ini bukan lagi sekadar masalah administratif, melainkan konflik yang didorong oleh kepentingan sumber daya.
Aspinall (2014) dalam analisisnya tentang "predatory peace" di Aceh, mengemukakan bagaimana elite pasca-konflik, termasuk mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), terlibat dalam praktik rent-seeking dan korupsi yang seringkali terkait dengan sumber daya alam.
Kondisi ini memperkuat narasi dominasi pusat yang berorientasi pada ekstraksi ekonomi, bukan pada keadilan administratif atau penghormatan otonomi.
Ini menguatkan kecurigaan bahwa "permainan Monopoli" Jakarta adalah manuver strategis untuk keuntungan ekonomi, bukan sekadar ketepatan batas wilayah.
Otonomi Khusus Aceh Pasca-MoU Helsinki
Pemberian otonomi khusus Aceh, yang diformalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (UU Pemerintahan Aceh) pasca-MoU Helsinki 2005, merupakan proyek kompromi monumental yang membuka jalan damai setelah konflik bersenjata berkepanjangan.
UU ini memberikan kewenangan luas bagi Aceh untuk mengatur urusan lokal, termasuk kehidupan beragama, pendidikan, adat, pengelolaan sumber daya alam, dan pembentukan partai politik lokal.
Namun, Aspinall (2014) mengindikasikan bahwa otonomi khusus ini "tidak menyentuh akar konflik relasi kuasa Jakarta–Aceh".
Kasus sengketa pulau ini menjadi bukti nyata kegagalan otonomi khusus dalam mencegah intervensi pusat yang bersifat sepihak, meskipun UU 11/2006 telah memberikan otonomi yang luas, pemerintah pusat tetap mempertahankan "kewenangan Pemerintah" dalam bidang-bidang strategis seperti kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, dan moneter/fiskal nasional.
Pemerintah Aceh memiliki bukti historis dan administratif yang kuat atas kepemilikan empat pulau tersebut.
Selain KTP warga dan pembangunan infrastruktur, terdapat pula dokumen resmi seperti Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Aceh Tahun 1988.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan menegaskan bahwa Keputusan Mendagri yang memindahkan pulau-pulau ini "cacat formil" karena jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, yang merupakan dasar hukum resmi pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan mengatur batas wilayahnya.
Lebih lanjut, MoU Helsinki merujuk pada batas wilayah 1 Juli 1956.
Tindakan pemerintah pusat yang menggunakan regulasi di bawah undang-undang untuk mengubah batas wilayah yang diatur oleh undang-undang dan dirujuk dalam perjanjian damai menunjukkan pengikisan hierarki hukum.
Apabila keputusan menteri dapat secara sepihak mengubah batas yang ditetapkan oleh UU dan diperkuat kesepakatan internasional seperti MoU Helsinki, maka hal ini secara fundamental merusak prinsip negara hukum dan asas lex superior derogat legi inferiori (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah).
Ini berarti status "khusus" Aceh bukan lagi hak konstitusional yang kokoh, melainkan hak istimewa yang rapuh dan mati di mata kehendak pusat.
Tindakan ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum bagi Aceh, tetapi juga menetapkan preseden berbahaya bagi daerah otonom lainnya di Indonesia, mengancam stabilitas hubungan pusat-daerah di seluruh Nusantara.
Ironisnya, pengikisan ini terjadi di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh saat ini, Muzakir Manaf, yang notabene adalah mantan Panglima Besar Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Kehadirannya di kursi pemerintahan seharusnya menjadi simbol penguatan otonomi dan perdamaian, namun justru menjadi saksi bisu betapa rapuhnya janji-janji pusat di hadapan realitas kekuasaan.
Krisis ini juga mengancam rapuhnya kepercayaan pasca-konflik di Aceh. Otonomi khusus adalah hasil dari kompromi besar, di mana Gerakan Aceh Merdeka (GAM) "rela mengubur mimpi merdekanya menjadi otonomi khusus" demi perdamaian.
Ketika perdamaian telah dicapai, Aceh justru kehilangan empat pulaunya. Tentu, itu sangat menyakitkan hati, seperti diungkapkan oleh Alkaf.
Perasaan dikhianati ini sangat dalam, mengingat pengorbanan besar yang telah dilakukan. Bräuchler (2015) dalam karyanya The Cultural Dimension of Peace menekankan pentingnya memahami dan menghormati konsepsi lokal tentang konflik, keadilan, dan rekonsiliasi, yang seringkali berakar pada narasi budaya dan historis.
Mengabaikan dimensi ini, seperti yang dilakukan pemerintah pusat, dapat membahayakan upaya rekonsiliasi.
Pelanggaran kepercayaan ini berisiko menghidupkan kembali keluhan historis dan sentimen alienasi dari negara Indonesia, berpotensi memicu bentuk-bentuk resistensi baru dan merongrong perdamaian yang telah susah payah dibangun.
Resistensi lokal
Resistensi masyarakat Aceh terhadap pemindahan empat pulau ini melampaui sekadar masalah batas wilayah administratif; ini adalah perjuangan yang mendalam untuk mempertahankan "harga diri" atau "marwah Aceh" dan identitas politik yang telah lama diperjuangkan.
Guru Besar Sosiologi Universitas Syiah Kuala, Ahmad Humam Hamid, secara tajam menyatakan bahwa bagi masyarakat Aceh, keputusan ini "bukan sekadar titik di peta, melainkan bagian dari ruang simbolik yang menyimpan memori konflik, perjuangan otonomi, dan perjanjian damai yang diperoleh dengan pengorbanan besar".
Pernyataan ini menggarisbawahi betapa teritori terkait erat dengan narasi historis dan jati diri kolektif masyarakat Aceh.
Dalam konteks ini, perlawanan Aceh mencerminkan bagaimana desentralisasi, seperti yang dijelaskan oleh Bräuchler (2015), seharusnya membuka ruang bagi ekspresi identitas lokal sebagai bentuk perlawanan terhadap “kewajaran” negara pusat.
Penekanan pada bukti-bukti sosiologis dan historis yang diwariskan turun-temurun, seperti pengakuan warga yang ber-KTP Aceh di pulau-pulau tersebut dan penggunaan dana Aceh untuk pembangunan infrastruktur di sana, adalah manifestasi dari perlawanan yang mengakar pada legitimasi lokal dan historis.
Ini adalah upaya untuk menegaskan kembali keberdayaan dan identitas mereka di hadapan pemaksaan dari pusat.
Bagi daerah pasca-konflik dengan identitas yang kuat, integritas teritorial tidak dapat dipisahkan dari martabat kolektif dan narasi sejarah mereka.
Tindakan sepihak oleh pusat, meskipun mungkin dibenarkan secara administratif dari perspektif mereka, secara tidak sengaja dapat memicu kebencian yang mendalam dan memobilisasi perlawanan berbasis identitas, yang pada akhirnya mengancam perdamaian dan stabilitas.
Para akademisi, anggota DPR RI dari Aceh, dan aktivis telah memperingatkan secara eksplisit bahwa keputusan sepihak ini berpotensi memicu ketegangan baru dan "memanaskan kembali relasi hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat".
Mereka menyebutnya sebagai risiko "api dalam sekam" yang dapat mengancam stabilitas pasca-konflik, mengingat sejarah panjang perjuangan Aceh untuk otonomi dan bahkan kemerdekaan yang berdarah-darah.
Desakan agar Presiden Prabowo mengambil alih persoalan ini dan membatalkan SK Kemendagri menunjukkan tingkat urgensi dan kekhawatiran akan eskalasi.
Ironisnya, kebijakan desentralisasi yang menurut Ostwald (2016) awalnya dirancang sebagai manuver politik untuk meredam tekanan sentrifugal dan meningkatkan stabilitas pasca-Soeharto, kini justru menjadi pemicu ketidakstabilan baru.
Hadiz (2010) telah mengkritik bahwa desentralisasi seringkali menciptakan "arena baru konflik" di mana elite lokal memanfaatkan peluang untuk kepentingan mereka.
Dalam kasus ini, ambiguitas administratif atau intervensi pusat yang berlebihan telah menciptakan titik nyala baru.
Ini mengungkapkan paradoks mendasar: kebijakan yang dirancang untuk mencegah separatisme dan meningkatkan stabilitas dapat, jika diimplementasikan dengan buruk atau ditegakkan secara sepihak, menjadi sumber ketidakstabilan baru.
Desentralisasi yang sejati membutuhkan bukan hanya kerangka hukum, tetapi juga kemauan politik yang konsisten, penghormatan terhadap otonomi lokal, dan proses konsultatif yang transparan untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan yang mengancam kohesi nasional.
Otonomi kerdil, tamparan di wajah perdamaian
Kasus sengketa empat pulau ini secara brutal menelanjangi kerapuhan otonomi khusus Aceh di hadapan dominasi pusat.
Jika hak dasar atas teritori, yang merupakan inti dari kedaulatan lokal dan identitas politik, dapat digeser begitu saja dengan keputusan sepihak Kemendagri, maka otonomi khusus yang dijanjikan dalam MoU Helsinki dan UU 11/2006 tak lebih dari simbol kosong.
Ini adalah pengkhianatan terhadap semangat perdamaian dan kompromi yang telah dicapai dengan pengorbanan besar.
Dugaan adanya kandungan migas di pulau-pulau yang disengketakan memperkuat narasi bahwa dominasi pusat seringkali didorong oleh kepentingan ekonomi yang terselubung, bukan semata-mata efisiensi administrasi.
Ini sejalan dengan kritik Aspinall (2014) tentang "predatory peace" di Aceh, di mana elite pasca-konflik, termasuk mantan GAM, terlibat dalam praktik rent-seeking dan korupsi, seringkali terkait dengan sumber daya alam, dan dana otonomi khusus pun belum berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat.
Konflik ini menggarisbawahi bahwa relasi kuasa Jakarta–Aceh masih didominasi oleh logika ekstraksi sumber daya, yang mengabaikan hak-hak dan martabat lokal.
Peristiwa ini secara telanjang menunjukkan bagaimana pemerintah pusat telah mengabaikan hierarki hukum, mengkhianati kepercayaan yang dibangun pasca-konflik, dan meremehkan bobot simbolis teritori bagi identitas Aceh.
Tindakan unilateral yang dianggap sewenang-wenang ini, yang tercermin dalam analogi "Jakarta bermain Monopoli," secara fundamental mempertanyakan ketulusan desentralisasi dan otonomi khusus.
Mungkin sudah saatnya kita menyebutnya apa adanya: otonomi kerdil, hak istimewa yang telah dimutilasi, hanya ada di atas kertas, namun mati di lapangan.
Dalam negara kepulauan yang beragam seperti Indonesia, integrasi nasional bergantung pada keseimbangan yang rapuh antara otoritas pusat dan otonomi daerah, yang dibangun atas dasar kepercayaan dan saling menghormati.
Ketika kekuasaan pusat dipersepsikan tidak terkendali, sepihak, dan didorong oleh kepentingan ekstraktif, hal itu berisiko mengasingkan daerah-daerah, terutama yang memiliki sejarah konflik.
Ini dapat menyebabkan kebangkitan sentimen separatis atau ketidakpuasan yang meluas, yang pada akhirnya merongrong persatuan yang ingin dipertahankan oleh pemerintah pusat.
Untuk menjaga keutuhan bangsa dan merawat perdamaian yang telah diraih dengan susah payah, pemerintah pusat harus segera meninjau ulang keputusan ini.
Dialog konstruktif yang menghormati sejarah, identitas, dan martabat masyarakat lokal adalah satu-satunya jalan ke depan.
Mengabaikan suara lokal dan menggeser batas wilayah seperti pion di papan Monopoli hanya akan menabur benih konflik baru, mengancam fondasi perdamaian dan integrasi nasional yang rapuh.
Tanpa penghormatan tulus terhadap kekhususan dan kedaulatan teritori, otonomi khusus Aceh akan selamanya menjadi janji hampa, sebuah ironi pahit di tengah upaya membangun Indonesia yang adil dan beradab.
Tag: #pulau #aceh #untuk #sumut #otonomi #kerdil #tamparan #wajah #perdamaian