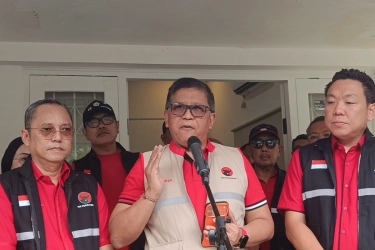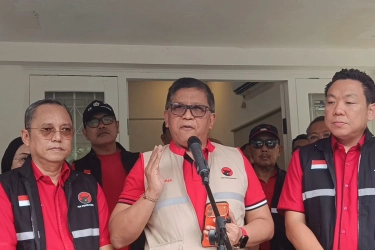Kemiskinan 60 Persen di Tengah Penguasaan Tanah 60 Keluarga
ADA bom waktu ketidakadilan sosial yang terus berdetak di Indonesia. Bom ini bukan baru ditanam—ia telah lama tertanam dalam-dalam dan diwariskan dari satu rezim ke rezim berikutnya.
Semua orang mengetahuinya: dari elite politik, akademisi, pengamat ekonomi, hingga rakyat kecil di pelosok negeri.
Namun, situasi ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian mendasar. Ketimpangan yang terjadi tak lagi sebatas persoalan struktural; ia telah menjelma menjadi ketimpangan brutal yang menyatu dalam sistem dan mengakar dalam budaya keseharian.
Kondisi ekstrem ini terkait dengan distribusi sumber daya dan akses terhadap ekonomi yang terkonsentrasi secara tidak adil di tangan segelintir elite.
Di sisi lain, jutaan rakyat Indonesia terpinggirkan dari akses terhadap tanah, pekerjaan layak, dan kesejahteraan dasar sebagai prasyarat untuk dapat hidup secara bermartabat.
Kementerian ATR/BPN (7 Mei 2025) baru berani secara resmi dan terang-terangan melansir bahwa satu keluarga menguasai 1,8 juta hektare tanah. Ini setara tiga kali luas Pulau Bali.
Pernyataan resmi ini juga mengungkap data bahwa dari total 70 juta hektare yang berada di kawasan non-hutan, 46 persen—atau kurang lebih 30 juta hektare—dikuasai oleh hanya 60 keluarga besar pemilik korporasi.
Ini berarti, hal yang selama ini hanya dianggap sebagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, kini akhirnya diakui dan diumumkan secara resmi oleh negara.
Inilah realitas yang menyakitkan: ketika segelintir elite menikmati jutaan hektare tanah, sementara jutaan keluarga Indonesia tak memiliki sepetak tanah untuk bercocok tanam, membangun rumah, atau sekadar bertahan hidup.
Di sisi lain, Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 menyebutkan bahwa 60,3 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional—yakni dengan penghasilan di bawah 6,85 dollar AS per hari (PPP 2017), atau setara kurang dari Rp 110.000 per hari.
Data ini menyatakan secara terang bahwa mayoritas rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan, di tengah ketimpangan yang kian melebar dan nyaris tak terkendali.
Secara klasifikasi ekonomi, Indonesia tergolong sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. Namun, faktanya Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan proporsi penduduk miskin terbesar di dunia, setelah Afrika Selatan, Namibia, dan Botswana.
Kenyataan ini adalah ironi yang memalukan, bahkan menjadi aib besar bagi negara sebesar Indonesia—yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, surplus tenaga kerja muda, dan potensi industri yang sangat besar.
Semua modal itu seharusnya cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, jika dikelola secara baik dan berkeadilan.
Fakta lain yang semakin menegaskan tantangan struktural ekonomi Indonesia adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, yang menunjukkan bahwa sekitar 60 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal.
Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan potret buram dunia kerja kita yang rapuh dan rentan. Para pekerja informal ini hidup tanpa perlindungan jaminan sosial, tanpa kepastian pendapatan, dan sangat mudah terguncang oleh krisis ekonomi—baik lokal maupun global.
Lebih memprihatinkan lagi, bahkan di sektor formal, tak sedikit pekerja yang tergolong working poor—mereka yang memiliki pekerjaan, tapi penghasilannya tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
Fenomena ini menunjukkan bahwa bekerja saja tidak otomatis membawa seseorang keluar dari kemiskinan, terutama jika sistem pengupahan dan struktur ekonomi tidak adil.
Jika kita mencermati tiga fakta utama yang telah dipaparkan—yaitu ketimpangan kepemilikan tanah, tingginya angka kemiskinan absolut berdasarkan standar internasional, dan dominasi sektor informal—maka menjadi jelas mengapa Indonesia masih terperangkap dalam middle income trap, atau jebakan negara berpendapatan menengah.
Ini adalah bukti nyata stagnasi ekonomi—ketika negara gagal menembus ambang kemajuan dan terus terjebak dalam kelas menengah.
Untuk keluar dari jebakan ini tidak cukup dengan kebijakan tambal sulam, program populis sesaat, atau teori ekonomi elitis warisan masa lalu yang tak berpijak pada realitas sosial.
Diperlukan lompatan besar— paradigma baru pembangunan ekonomi berbasis manusia yang melihat populasi besar bukan sebagai beban, melainkan sebagai aset strategis.
Diperlukan niat kuat politik (political Will), inovasi kebijakan, dan kemauan untuk menggugat ketimpangan struktural yang selama ini dilanggengkan.
Tanah dikuasai segelintir orang
Perebutan tanah adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah peradaban manusia. Sejak zaman kuno, tanah bukan hanya diperebutkan atas nama negara, kekuasaan, atau ekspansi kekaisaran, tetapi juga demi kepentingan individual dan status sosial.
Tanah adalah sumber kehidupan, dan karena itu, menjadi objek dominasi yang paling fundamental.
Dalam tradisi Romawi Kuno, terdapat pepatah berbunyi: "Terra mater est omnium rerum" — tanah adalah ibu dari segala sesuatu.
Pandangan ini menunjukkan bahwa bagi bangsa Romawi, tanah tidak hanya menyediakan pangan dan kekayaan, tetapi juga menjadi sumber kehormatan, status sosial, dan bahkan spiritualitas kekuasaan.
Siapa yang menguasai tanah, diyakini tidak hanya menguasai dunia, tetapi juga menapaki jalan menuju “surga”—bukan dalam makna religi semata, tetapi dalam bentuk kejayaan, martabat, dan kontrol atas nasib sesamanya.
Dalam sistem feodalisme yang mendominasi Eropa Abad Pertengahan, tanah adalah alat utama dalam struktur kekuasaan. Raja dan bangsawan menguasai wilayah luas dan membagi-bagikannya kepada para loyalis dalam bentuk manor, dengan imbalan kesetiaan militer.
Tanah menentukan siapa yang menjadi tuan, dan siapa yang menjadi hamba. Tanpa tanah, seseorang tidak punya posisi sosial, tidak punya suara politik, dan tidak memiliki jaminan hidup.
Perkembangan kapitalisme pada abad ke-18 dan ke-19 memperkenalkan perubahan dalam relasi terhadap tanah. Tanah tak lagi semata-mata simbol kekuasaan feodal, tetapi menjadi komoditas yang bisa dibeli, dijual, disewakan, dan dijadikan agunan.
Hak milik pribadi atas tanah diperkuat melalui hukum, sementara proses enclosure di Inggris misalnya, merampas tanah komunal rakyat kecil untuk kepentingan agraria industri.
Inilah awal dari ketimpangan modern dalam penguasaan tanah—di mana hukum melindungi kepemilikan, tetapi tidak selalu melindungi keadilan.
Memasuki era kolonial, penguasaan tanah menjadi instrumen utama penaklukan. Di berbagai wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin, tanah rakyat adat disita, disertifikasi ulang atas nama negara kolonial, dan dialihkan ke tangan korporasi asing maupun tuan tanah baru.
Kolonialisme bukan hanya ekspansi militer, tetapi juga proyek sistematis pemindahan kepemilikan dan otoritas atas tanah.
Di era modern, penguasaan tanah tidak lagi hanya bermotif politik, tetapi juga finansial. Tanah menjadi objek spekulasi pasar, sumber rente, dan instrumen akumulasi kapital.
Dalam banyak kasus, sistem hukum negara justru memperkuat ketimpangan ini, alih-alih memperbaikinya.
Ketika tanah semakin terkonsentrasi di tangan segelintir elite, dan jutaan orang kehilangan akses bahkan untuk tempat tinggal atau bertani, maka yang terjadi bukan sekadar ketimpangan ekonomi, tetapi krisis keadilan struktural.
Di Indonesia, sejarah penguasaan tanah tidak terlepas dari pengaruh kolonialisme yang menempatkan tanah sebagai alat kekuasaan dan eksploitasi.
Pada masa penjajahan Belanda, sistem Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) digunakan untuk menguasai dan memaksa rakyat Indonesia menanam komoditas ekspor yang menguntungkan bagi pemerintah kolonial. Sementara tanah yang dulunya dikuasai oleh rakyat adat dialihkan ke tangan pengusaha Belanda dan pemerintah kolonial.
Dengan cara ini, tanah bukan hanya dijadikan alat untuk menghasilkan kekayaan bagi kolonialisme, tetapi juga untuk mempertahankan kontrol atas rakyat pribumi.
Setelah Indonesia merdeka pada 1945, meskipun ada perubahan secara politik, penguasaan tanah tetap menjadi persoalan besar.
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang disahkan pada 1960 bertujuan mendistribusikan tanah secara lebih adil dan menyelesaikan masalah penguasaan tanah yang timpang.
Namun, realitasnya tidak sesuai dengan harapan. Meski UUPA secara teori mengakui hak agraria rakyat, dalam praktiknya, konsentrasi penguasaan tanah tetap berlangsung di tangan segelintir elite—baik itu korporasi besar, keluarga kaya, maupun aparatur negara.
Pada masa Orde Baru, penguasaan tanah oleh negara melalui program transmigrasi dan proyek pembangunan besar-besaran justru semakin menambah ketimpangan.
Tanah yang sebelumnya dimiliki oleh masyarakat adat atau petani kecil, sering kali diambil alih oleh negara untuk kepentingan proyek-proyek industrialisasi.
Sementara itu, program transmigrasi yang ditujukan untuk mendistribusikan penduduk ke daerah-daerah baru justru sering kali menyisakan ketidakadilan dalam hal akses tanah dan pekerjaan.
Di era pasca-Reformasi, ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia semakin mencolok. Data Kementerian ATR/BPN (7 Mei 2025) yang menyebutkan, satu keluarga menguasai tanah seluas tiga kali luas Pulau Bali—46 persen tanah dikuasai oleh hanya 60 keluarga korporasi merupakan ironi yang besar.
Ketimpangan ruang tanah di Indonesia bukan hanya terjadi di darat—laut pun mulai dikuasai. Di banyak pesisir, pagar-pagar laut berdiri tegak, membatasi ruang hidup nelayan tradisional, seolah laut bukan lagi milik rakyat, tapi milik korporasi.
Di balik klaim investasi dan pembangunan, yang terjadi adalah perampasan ruang hidup. Laut yang dulu terbuka kini dikavling, dijual, dan dipagari. Nelayan yang berani melawan, justru dikriminalisasi.
Ketika laut diprivatisasi, bukan hanya ikan yang hilang dari jaring mereka, tapi juga martabat dan masa depan.
Inilah paradok dari negara yang mengatakan negaranya berazaskan Pancasila. Tanah sebagai sumber penghidupan justru dikuasai segelintir elite, sementara 60 persen rakyat hidup dalam kemiskinan.
Ini bukan sekadar anomali, tetapi cermin retak dari ketimpangan sosial dan ekonomi yang kian akut.
Ketidakadilan ini tidak hanya mengancam kesejahteraan rakyat, tetapi juga ketahanan negara. Ketidakmampuan negara untuk mendistribusikan tanah secara adil memperburuk ketimpangan yang ada, memperpanjang ketidaksetaraan, dan menambah jurang pemisah antara yang kaya dan miskin.
Bekerja, tapi tetap miskin
Di Indonesia, bekerja belum tentu berarti keluar dari kemiskinan. Secara logika umum, ketika seseorang sudah bekerja, ia seharusnya memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar—pangan, sandang, papan, serta akses terhadap layanan sosial. Namun, kenyataannya berkata lain.
Setiap hari, jutaan orang Indonesia bekerja keras. Mereka berangkat pagi, pulang malam, bahkan ada yang menjalani dua hingga tiga pekerjaan sekaligus.
Namun, jangankan hidup layak, untuk bertahan hidup pun sering kali tak cukup. Mereka bukan pengangguran, tapi juga bukan bagian dari masyarakat yang sejahtera. Inilah yang disebut sebagai working poor—pekerja miskin.
Pekerja miskin adalah mereka yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya sangat rendah, tidak stabil, dan jauh dari layak.
Mereka bekerja tanpa perlindungan sosial, terjebak dalam sistem kerja yang eksploitatif, dengan biaya hidup yang terus naik, sementara upah tetap stagnan.
Saat ini, belum ada kategori resmi dalam statistik pemerintah yang secara khusus mengidentifikasi pekerja miskin. Namun, berbagai indikator ketenagakerjaan bisa mencerminkan keberadaan kelompok ini.
Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pekerjaan tertentu, terutama sektor informal, sangat rentan terhadap kemiskinan.
Banyak pekerja di sektor ini yang menerima upah mendekati atau bahkan di bawah garis kemiskinan nasional.
Mayoritas pekerja di Indonesia berada di sektor informal—sekitar 60 persen. Mereka bekerja tanpa jaminan kesehatan, tanpa kontrak kerja, dan tanpa kepastian penghasilan. Mereka hidup dalam ketidakpastian, mudah terdampak krisis, dan sulit mengakses perlindungan negara.
Tingkat ketimpangan ekonomi juga memperburuk kondisi ini. Salah satu indikator utama ketimpangan adalah Gini Ratio, di mana mengukur sejauh mana distribusi pendapatan atau kekayaan merata dalam suatu masyarakat.
Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mencatat Gini Ratio berkisar antara 0,37 hingga 0,39—angka yang menunjukkan ketimpangan cukup tinggi.
Ini artinya, distribusi kekayaan dan pendapatan masih sangat timpang, dengan sebagian besar hasil ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir kelompok atas.
Fenomena pekerja miskin juga terlihat jelas dalam ekosistem kerja digital atau gig economy, seperti pengemudi ojek online.
Mereka bekerja keras hampir tanpa henti, terikat oleh algoritma dan target yang terus berubah. Meski disebut sebagai “mitra”, kenyataannya mereka tak memiliki posisi tawar yang kuat.
Upah mereka dapat berubah sewaktu-waktu, insentif dipotong sepihak, dan tidak ada jaminan sosial layaknya pekerja formal.
Dalam banyak kasus, para pengemudi ini menjadi wajah nyata dari eksploitasi modern—bekerja sepanjang hari demi penghasilan tak pasti, tanpa perlindungan ketika sakit, kecelakaan, atau bahkan ketika perusahaan tempat mereka bergantung tiba-tiba mengubah kebijakan.
Dalam laporan Bank Dunia, kelompok working poor menjadi perhatian utama. Mereka tidak tercatat sebagai penganggur dalam statistik resmi, tapi kondisi hidup mereka nyaris tidak berbeda dari orang miskin, bahkan sering kali lebih tersembunyi dan terabaikan.
Meskipun mereka bekerja keras setiap hari, pekerjaan tersebut tidak cukup untuk mengangkat mereka dari jurang kemiskinan, dan sering kali terperangkap dalam keadaan yang tidak jauh berbeda dari mereka yang tidak bekerja sama sekali.
Inilah yang menjadi persoalan struktural yang harus dihadapi oleh sistem ketenagakerjaan di Indonesia.
Jika pekerjaan yang mereka miliki tidak mampu mengangkat seseorang keluar dari kemiskinan, maka kita tidak hanya menghadapi masalah ketenagakerjaan, tetapi juga krisis struktural dalam pembangunan ekonomi.
Pembangunan ekonomi yang tidak dapat menciptakan pekerjaan yang layak dan mencukupi kebutuhan dasar masyarakat akan memperpanjang ketimpangan sosial dan menguatkan jurang pemisah antara segelintir orang yang memiliki kekayaan dan mayoritas yang terpinggirkan dalam kemiskinan.
Selain itu, gelombang PHK yang terus menghantam Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Di tengah transformasi digital dan globalisasi ekonomi, banyak sektor tradisional yang mengalami penurunan, sementara sektor baru belum mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah memadai.
Tercatat, dalam enam bulan pertama pemerintahan Prabowo Subianto, angka PHK semakin meningkat. Hal ini menunjukkan ketidakstabilan dalam pasar kerja yang dapat memperburuk situasi ketenagakerjaan dan menciptakan lapisan pekerja baru yang semakin terpinggirkan.
Dengan tantangan ini, sudah saatnya Indonesia mengambil langkah tegas untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya—berprinsip pada kesetaraan dan kesejahteraan.
Setiap pekerja berhak mendapatkan upah layak, jaminan sosial memadai, serta peluang nyata untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Tanpa perubahan mendasar dalam kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi, jutaan pekerja akan tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang menahun, dan ketimpangan sosial yang terus berkembang akan semakin mengancam stabilitas sosial dan politik negara.
Ketidakadilan diungkap, penindakan minim
Dalam kerangka teori ekonomi klasik dan kontemporer, tanah dan tenaga kerja tidak hanya dipandang sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai pilar utama kesejahteraan sosial, legitimasi kekuasaan politik, dan ketahanan suatu negara.
Pemikiran para ekonom seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Karl Marx, serta pengembangan lebih lanjut oleh ekonom kelembagaan seperti Douglas North, Daron Acemoglu, dan James A. Robinson, menegaskan bahwa tiga elemen utama pembentuk kekayaan nasional adalah tanah (land), tenaga kerja (labor), dan modal (capital).
Ketika dua dari tiga elemen tersebut—yakni tanah dan tenaga kerja—terkonsentrasi pada segelintir elite, konsekuensinya adalah munculnya kemiskinan struktural yang dilembagakan.
Kondisi ini memperdalam ketimpangan sosial dan pada akhirnya melemahkan fondasi kedaulatan negara.
Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan baru telah mengutarakan ambisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dan mencapai kemandirian nasional.
Namun demikian, ambisi tersebut akan sulit tercapai apabila persoalan mendasar terkait ketimpangan akses terhadap tanah dan pekerjaan tidak ditangani secara serius dan sistemik.
Dalam sejarah pembangunan ekonomi, Indonesia pernah mengalami trauma akibat pendekatan trickle-down effect yang diadopsi oleh pemerintahan Orde Baru.
Pendekatan ini dipengaruhi oleh pemikiran ekonom Soemitro Djojohadikusumo—tokoh ekonomi penting Orde Baru sekaligus ayah dari Presiden Prabowo Subianto.
Teori ini berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh kelompok atas akan "merembes" ke bawah dan membawa manfaat bagi kelompok miskin.
Dengan kata lain, jika negara berhasil mencetak lebih banyak orang kaya, kesejahteraan rakyat miskin akan ikut terangkat.
Namun, berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa pendekatan ini gagal menciptakan distribusi kekayaan yang adil. Dalam praktiknya, hampir tidak ada orang kaya yang merasa cukup dengan kekayaan yang telah dimilikinya, sekalipun sudah berlimpah.
Analogi yang tepat untuk menggambarkan fenomena ini: ketika satu “ember” kekayaan telah penuh, mereka tidak membiarkan airnya merembes ke bawah, melainkan segera menyiapkan ember baru untuk menampung limpahan berikutnya.
Rembesan yang terjadi bukanlah ke masyarakat miskin secara luas, melainkan hanya kepada pekerja-pekerja bergaji murah yang menjadi roda penggerak dalam sistem ekonomi mereka.
Model ekonomi berbasis trickle-down effect telah menciptakan ketimpangan yang signifikan di Indonesia.
Dalam praktiknya, aliran kekayaan yang dijanjikan akan merembes ke bawah justru tidak terjadi. Sebaliknya, kekayaan semakin terkonsentrasi di tangan segelintir elite ekonomi, meninggalkan mayoritas masyarakat dalam kondisi stagnan atau bahkan terpinggirkan.
Ketimpangan ini tidak hanya memicu kecemburuan sosial, tetapi juga menjadi akar dari krisis multidimensi yang memuncak pada akhir 1990-an. Krisis tersebut berpuncak pada kejatuhan rezim Soeharto dan pecahnya konflik sosial besar, termasuk kerusuhan Mei 1998.
Peristiwa itu memperlihatkan betapa ketegangan sosial-ekonomi dapat dengan cepat berubah menjadi konflik horizontal—khususnya antara kelompok ekonomi dominan, yang banyak berasal dari etnis Tionghoa, dan masyarakat pribumi yang merasa tersisih secara struktural.
Kegagalan sistemik dari model pembangunan berbasis trickle-down ini masih terasa hingga kini. Ketimpangan yang kronis menjadi warisan yang terus menghantui Indonesia.
Dari laporan Credit Suisse Global Wealth Report tahun 2023 mencatat bahwa 10 persen kelompok masyarakat terkaya di Indonesia menguasai lebih dari 75 persen total kekayaan nasional. Ini adalah bukti nyata bahwa teori "merembes ke bawah" tidak pernah benar-benar bekerja.
Fakta ini menjadi pengingat bahwa kebijakan ekonomi tanpa keadilan distribusi dan inklusi sosial bukan hanya gagal menyejahterakan, tetapi juga bisa menjadi bahan bakar konflik horizontal dan ancaman bagi stabilitas nasional.
Jika pemerintahan baru tetap bertumpu pada pendekatan pembangunan dari atas ke bawah (top-down) tanpa perubahan struktural yang nyata, maka ketimpangan akan terus terpelihara, dan keadilan ekonomi hanya akan menjadi slogan kosong—jauh dari kenyataan.
Selain itu, pendirian super holding company bernama Danantara oleh Prabowo menimbulkan pertanyaan serius tentang konsentrasi kekuasaan ekonomi dan potensi penguatan dominasi korporasi di bawah kendali negara.
Jika tidak dikawal dengan transparansi dan prinsip-prinsip keadilan sosial, langkah ini dapat memperbesar jurang ketimpangan serta memperkuat posisi elite dalam menguasai sumber daya nasional.
Lebih lanjut, terdapat kekhawatiran publik bahwa pengungkapan kasus-kasus ketidakadilan di awal pemerintahan Prabowo—seperti kasus pagar laut, dugaan korupsi Pertamina, serta laporan Rp 984 triliun dana negara yang dikorupsi, tapi minim penindakan—hanya akan menjadi alat pergantian aktor kekuasaan, bukan sarana menuju reformasi sistemik.
Tanpa perubahan paradigma dan arah kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat banyak, pergantian elite hanya akan memperpanjang siklus eksklusi sosial dan reproduksi kemiskinan struktural.
Mengungkap data ketidakadilan tanpa diikuti kebijakan afirmatif yang nyata hanya akan berakhir sebagai simbolisme kosong—sekadar omon-omon tanpa perubahan.
Fenomena yang kerap terjadi dalam praktik kebijakan publik di Indonesia adalah kegagalan dalam tindak lanjut implementatif.
Masyarakat bahkan sudah terbiasa mengasosiasikannya dengan istilah “masuk angin”— ungkapan satir yang menggambarkan heroik awal yang tinggi, tapi perlahan menguap yang diduga ada kesepakatan terselubung di balik layar.
Untuk mewujudkan bangsa yang berkeadilan, pembangunan ekonomi tidak bisa lagi sekadar mengukur angka-angka statistik yang kering.
Pemerintah harus berani meredefinisi kemajuan, dengan menggiring setiap kebijakan menuju tujuan lebih besar, yaitu menciptakan distribusi kekayaan yang adil, menjamin akses setara terhadap sumber daya, dan mengatasi ketimpangan struktural yang telah lama membelenggu rakyat.
Hanya dengan menempatkan manusia sebagai inti dari setiap kebijakan ekonomi, Indonesia dapat mengubah paradigma yang selama ini berfokus pada pertumbuhan semu menjadi kesejahteraan nyata, di mana setiap lapisan masyarakat merasakan hasilnya.
Sudah saatnya bangsa ini digerakkan menuju revolusi ekonomi yang berpijak pada keadilan sosial—demi kehidupan yang lebih baik, lebih merata, dan lebih bermartabat bagi semua.
Ini bukan utopia atau hanya omon-omon, selama ada kemauan politik yang kuat dan keberpihakan nyata kepada rakyat.
Tag: #kemiskinan #persen #tengah #penguasaan #tanah #keluarga