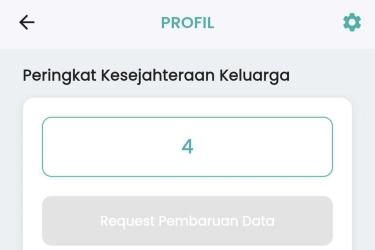Saatnya Negara Berpihak pada Gig Economy
PERUBAHAN dunia kerja sedang berlangsung secara senyap, tapi dampaknya fundamental. Hubungan kerja yang dahulu bertumpu pada status karyawan tetap, jam kerja baku, dan gaji bulanan kini bergeser menuju pola kerja berbasis proyek, tugas, dan platform digital—yang dikenal sebagai gig economy.
Di Indonesia, fenomena ini bukan lagi gejala pinggiran, melainkan menjadi penyangga hidup jutaan orang. Gig economy sering dipromosikan sebagai simbol fleksibilitas dan kemandirian.
Namun, di balik narasi tersebut, tersimpan persoalan mendasar, yaitu ketiadaan perlindungan sosial memadai.
Di titik inilah pertanyaan kebijakan publik menjadi relevan—apakah negara hanya akan memanfaatkan gig economy sebagai mesin pertumbuhan, atau sungguh-sungguh berpihak pada para pekerjanya?
Secara global, potensi sektor ini tidak terbantahkan. Laporan Business Research Insights mencatat nilai pasar gig economy diproyeksikan mencapai 674 miliar dollar AS pada 2026 dan melonjak menjadi lebih dari 2.500 miliar dollar AS pada 2035, dengan laju pertumbuhan tahunan hampir 16 persen.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, tapi Kesenjangan Melebar
Pertumbuhan ini terutama didorong oleh sektor e-commerce, layanan antar, dan transportasi berbasis aplikasi yang meningkat hingga 92 persen secara tahunan pada 2024.
Indonesia, dengan bonus demografi dan penetrasi digital luas, berada di posisi strategis untuk memetik manfaatnya. Pemerintah pun melihat peluang tersebut.
Gig economy disebut sebagai salah satu penopang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon sebagaimana dikutip dari Warta Ekonomi menyebut sektor ini sebagai bagian dari tiga mesin pertumbuhan utama, bersama manufaktur dan pariwisata.
Namun, optimisme makroekonomi ini belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi mikro para pekerja.
Studi komprehensif KANTAR menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 41,6 juta pekerja gig atau pekerja mandiri, setara dengan 50 persen dari total pekerja informal dan sekitar 60 persen dari angkatan kerja nasional menurut data Sakernas BPS.
Yang kerap luput dari perhatian, mayoritas pekerja gig ini tidak berada di sektor digital modern, melainkan di pertanian, perikanan, konstruksi, manufaktur, dan perdagangan.
Hampir 40 juta di antaranya merupakan pekerja kerah biru yang menghadapi risiko kerja tinggi, pendapatan tidak menentu, dan perlindungan minimal.
Fleksibilitas memang menjadi ciri utama gig economy. Namun, fleksibilitas itu sering memiliki sisi gelap.
Banyak pekerja dibayar per tugas atau hasil kerja tanpa jaminan pendapatan minimum. Kontrak tertulis kerap tidak tersedia, terutama di sektor tradisional.
Akses terhadap jaminan kesehatan, perlindungan kecelakaan kerja, pelatihan, dan pengembangan karier masih terbatas.
Baca juga: Negara dan Oligarki
Bahkan secara global, satu dari tiga pekerja gig mengaku khawatir terhadap risiko pencurian atau kekerasan saat bekerja. Situasi ini menjadi semakin mendesak jika dikaitkan dengan kondisi pengangguran nasional.
Badan Pusat Statistik mencatat, per November 2025 terdapat 7,35 juta pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran tertinggi berasal dari lulusan SMK (8,45 persen), disusul SMA (6,55 persen) dan bahkan lulusan perguruan tinggi (5,38 persen).
Fakta ini menunjukkan bahwa sistem kerja konvensional semakin sulit menyerap tenaga kerja terdidik, sementara gig economy menjadi katup pengaman—meski tanpa jaminan keberlanjutan.
Pengalaman internasional memberikan pelajaran penting. Inggris memperkenalkan kategori hukum worker, yang berada di antara karyawan tetap dan kontraktor independen, sehingga pekerja platform tetap memperoleh hak dasar seperti upah minimum dan cuti.
Spanyol melalui Rider Law mengakui pengemudi platform sebagai pekerja dengan perlindungan ketenagakerjaan penuh.
Singapura memilih pendekatan kolaboratif dengan memperluas skema jaminan sosial, pelatihan ulang, dan tabungan pensiun bagi pekerja mandiri tanpa mematikan fleksibilitas pasar tenaga kerja.
Indonesia sebenarnya telah memulai langkah awal, antara lain dengan mendaftarkan jutaan pekerja sektor informal dan gig dalam program jaminan sosial berbasis kartu pintar. Namun, kebijakan ini masih bersifat administratif dan fragmentaris.
Tantangan utama tetap belum terjawab: definisi hukum gig worker yang jelas, standar kontrak yang adil, transparansi skema bagi hasil, serta perlindungan di sektor berisiko tinggi.
Negara tidak perlu memilih antara fleksibilitas dan perlindungan. Keduanya dapat berjalan beriringan jika dirancang secara cermat.
Diperlukan kerangka kebijakan adaptif yang melibatkan pemerintah, platform digital, pelaku usaha, serikat pekerja, akademisi, dan komunitas pekerja gig. Tanpa itu, gig economy berisiko menjadi wajah baru dari kerentanan lama: kerja keras tanpa kepastian.
Gig economy telah menjadi bagian tak terpisahkan dari masa depan kerja Indonesia. Karena itu, negara tidak cukup hanya memanfaatkannya sebagai mesin pertumbuhan.
Negara harus berpihak pada manusia di balik algoritma. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bukan semata persoalan angka, melainkan juga soal keadilan, martabat, dan keberlanjutan hidup para pekerja.