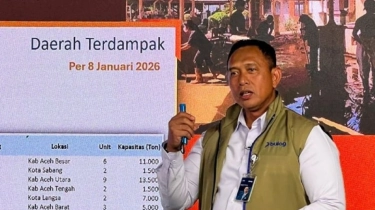Tambang untuk Rakyat, Rakyat yang Mana?
PERATURAN Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba) disambut dengan tepuk tangan oleh banyak kalangan.
Di atas kertas, aturan ini menjanjikan desentralisasi manfaat sumber daya alam, membuka ruang bagi koperasi, UMKM, organisasi masyarakat, institusi keagamaan bahkan perguruan tinggi untuk ikut serta mengelola tambang.
Pemerintah menyebutnya sebagai wujud “demokratisasi” sumber daya alam, langkah agar kekayaan bumi negeri ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir konglomerat dan investor asing, melainkan juga oleh rakyat banyak di sini.
Namun, sebagaimana banyak kebijakan “populis” sebelumnya, keindahan di atas kertas tidak selalu sejalan dengan praktik di lapangan.
PP 39/2025, yang merupakan perubahan kedua atas PP 96/2021 dan turunan dari Undang-Undang Minerba yang baru, perlu dibaca dengan kacamata realitas politik ekonomi Indonesia, sebuah sistem yang masih berputar di poros patronase dan hubungan klientelistik antara kekuasaan dan pemilik modal.
Pokok-pokok pikiran dalam peraturan ini memang tampak visioner. Ia membuka peluang bagi entitas kecil seperti koperasi dan badan usaha milik daerah untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga 2.500 hektar.
Proses perizinannya dijanjikan lebih sederhana melalui sistem daring OSS, sementara kementerian koperasi mendapat mandat untuk memverifikasi kelayakan administrasi dan keanggotaan koperasi.
Tujuan akhirnya jelas: mendorong pemerataan ekonomi, menciptakan keadilan sosial, dan memastikan sumber daya alam benar-benar “dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Namun, jika kita menilik sejarah pengelolaan tambang nasional selama dua dekade terakhir, narasi “prorakyat” ini justru tampak sebagai ulangan lama dengan kemasan baru.
Di dunia nyata, struktur penguasaan tambang nasional tidaklah sederhana. Dari batu bara di Kalimantan, nikel di Sulawesi, hingga emas di Papua, industri minerba (mineral dan batu bara) di Indonesia dikuasai oleh segelintir pemain besar.
Beberapa di antaranya adalah konglomerasi yang memiliki hubungan erat dengan elite politik, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Perusahaan-perusahaan tambang raksasa itu memiliki daya tawar ekonomi sekaligus kekuatan politik dan jejaring yang memungkinkan mereka menjadi bagian dari lingkar kekuasaan, bukan sekadar mitra bisnis pemerintah.
Di lapis bawah, kita menyaksikan fenomena tambang rakyat dan tambang ilegal, dari penambangan emas tanpa izin di Kalimantan Barat hingga aktivitas serupa di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Sumatra.
Meskipun sering disebut “rakyat kecil”, sebagian besar tambang ilegal ini justru beroperasi di bawah perlindungan oknum aparat, politisi lokal, atau bahkan kepala daerah.
Mereka membentuk rantai ekonomi bayangan yang hidup dari patronase, pelindung politik di atas, pelaku di bawah, dan aliran uang di antara keduanya.
Dalam konteks ini, wacana pelibatan koperasi dan UMKM lewat PP 39/2025 tampak menjanjikan, tapi juga penuh risiko.
Ketika patronase menjadi sistem yang mengatur hampir seluruh mekanisme ekonomi dan politik di negeri ini, partisipasi “rakyat” dalam pengelolaan tambang bisa dengan mudah berubah menjadi sekadar perpanjangan tangan dari jejaring kekuasaan.
Pada tataran ide, keterlibatan koperasi, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil memang terdengar ideal. Negara seolah hendak mengembalikan sumber daya alam ke tangan rakyat.
Namun, bila kita perhatikan lebih seksama, di balik skema ini terdapat peluang besar bagi para aktor politik untuk memperluas jaringan ekonomi mereka dengan legitimasi hukum baru.
Program “80.000 koperasi Merah Putih” misalnya, digadang-gadang menjadi motor ekonomi kerakyatan.
Namun, dalam konteks politik pascapemilu, koperasi jenis ini tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa sebagian besar penggeraknya merupakan relawan politik yang berperan dalam pemenangan kekuasaan saat ini.
Maka, ketika PP 39/2025 memberi ruang bagi koperasi untuk mengelola tambang, secara de facto negara tengah membuka pintu besar bagi distribusi proyek ekonomi kepada jaringan politik yang telah berjasa dalam kontestasi elektoral.
Hal ini tentu bukan asumsi tanpa dasar, melainkan pembacaan atas pola yang berulang. Dalam sejarah ekonomi politik Indonesia, berbagai inisiatif nasionalisasi atau lokalisasi sumber daya seringkali berakhir sebagai ajang redistribusi rente bagi kelompok yang dekat dengan kekuasaan.
Sejak masa Orde Baru, hubungan antara negara, bisnis, dan elite politik sudah membentuk simbiosis yang nyaris tidak terpisahkan.
Setiap kebijakan ekonomi besar selalu memiliki dimensi patron klien yang menentukan siapa yang mendapat akses, dan siapa yang dikeluarkan dari lingkar kekuasaan.
Analisis Eve Warburton dalam bukunya “Resource Nationalism in Indonesia: Booms, Big Business, and the State" (2023), memberikan kerangka teoretis yang membantu kita dalam memahami fenomena ini.
Warburton menunjukkan bahwa nasionalisme sumber daya alam di Indonesia bukanlah gerakan ideologis murni yang lahir dari semangat kedaulatan rakyat, melainkan produk dari pertarungan kepentingan antara bisnis domestik besar dan kekuasaan negara.
Menurut Warburton, dua hal menjadi kunci dalam memahami arah kebijakan sumber daya, kekuatan instrumental dan kekuatan struktural dari bisnis domestik.
Kekuatan instrumental mencakup kemampuan pelaku bisnis besar untuk memengaruhi kebijakan melalui jaringan politik, patronase, dan hubungan pribadi dengan pejabat.
Sementara kekuatan struktural merujuk pada posisi ekonomi mereka, sebagai pengendali ekspor, penyedia modal, dan pemilik infrastruktur yang membuat negara bergantung pada mereka.
Dalam konteks demokrasi patronase seperti Indonesia, dua kekuatan ini menyatu dalam hubungan yang saling menguntungkan.
Bisnis besar mendukung kekuasaan melalui pembiayaan politik, sementara negara memberi imbalan berupa akses terhadap sumber daya strategis.
Hasilnya adalah bentuk “nasionalisme sumber daya” yang paradoksal, secara retoris antiasing dan prorakyat, tetapi secara praktis memperkuat dominasi oligarki domestik.
Warburton juga menunjukkan variasi antar sektor, di sektor pertambangan, nasionalisme sering tampil paling keras karena aktor-aktor domestiknya memiliki kapasitas finansial dan politik yang kuat untuk menggantikan peran investor asing.
Hal ini sejalan dengan tren di Indonesia, di mana kebijakan divestasi asing dan pembatasan ekspor bahan mentah disertai penguatan posisi perusahaan lokal yang dekat dengan elite politik dan kekuasaan.
Maka, jika kita membaca PP 39/2025 melalui kacamata Warburton, tampak jelas bahwa kebijakan ini bukan sekadar tentang “pemerataan” sumber daya, tetapi tentang konsolidasi kekuasaan ekonomi di tangan jaringan politik domestik yang telah mapan.
Pertanyaannya kemudian, siapa sesungguhnya yang benar-benar akan menikmati keuntungan dari kebijakan ini?
Mungkin secara formal, koperasi akan mengantongi izin usaha tambang. Namun, siapa yang membiayai operasionalnya? Siapa yang menyediakan peralatan dan para ahli, siapa pula yang menanggung risiko, dan menjadi mitra penjualan hasil tambang?
Pengalaman menunjukkan bahwa entitas kecil seperti koperasi sering hanya menjadi “bendera” bagi investor besar yang tidak ingin tampil di depan, atau bagi jaringan politik yang mencari legitimasi “kerakyatan” dalam menguasai sumber daya.
Dalam kasus koperasi merah putih, negara memberikan modal melalui bank-bank pelat merah, sehingga negara sekaligus menancapkan instrumen kontrol kepada puluhan ribu koperasi yang seharusnya lahir dari bawah, tapi sekarang justru dipaksakan dari atas.
Dengan kata lain, PP 39/2025 berpotensi melahirkan bentuk baru dari ekonomi politik tambang, bukan antara asing dan domestik, melainkan antara rakyat sebagai simbol dan elite sebagai pengendali.
Koperasi bisa saja menjadi nama di atas kertas, tetapi di baliknya beroperasi perusahaan besar atau jaringan relawan politik yang memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan.
Dalam situasi ini, pelibatan UMKM dan koperasi bukan berarti pemerataan, melainkan perluasan kontrol politik atas ekonomi.
Keterlibatan mereka di sektor tambang bisa menjadi alat untuk memperkuat basis dukungan politik, terutama jika izin dan proyek diberikan kepada koperasi yang secara informal merupakan bagian dari jejaring relawan penguasa.
Secara teoretis, kebijakan ini dapat dipahami sebagai bentuk “nasionalisme sumber daya” versi domestik.
Negara tampil sebagai pelindung rakyat, tetapi dalam praktiknya menjadi mediator yang menyalurkan manfaat kepada kelompok tertentu.
Warburton menyebut gejala ini sebagai “post-boom resource nationalism”, nasionalisme sumber daya yang tidak lagi dipicu oleh lonjakan harga komoditas, melainkan oleh kebutuhan politik untuk mempertahankan legitimasi dan menyalurkan patronase kepada pendukung.
Dalam kerangka itu, PP 39/2025 lebih merupakan instrumen politik dari pada kebijakan ekonomi murni.
Aturan baru ini menciptakan kesan bahwa kekuasaan berpihak kepada rakyat, tetapi sekaligus memperkuat mekanisme kontrol terhadap masyarakat melalui ekonomi.
Ketika koperasi dan UMKM menjadi penerima izin tambang, mereka secara ekonomi tergantung pada negara, dan secara politik akan merasa berutang kepada penguasa yang memberi akses tersebut.
Pada akhirnya, kita bisa memproyeksikan bahwa penerapan PP 39/2025 tidak akan mengubah pola dasar penguasaan sumber daya di Indonesia.
Tambang akan tetap dikuasai oleh jaringan politik dan bisnis besar yang bisa jadi itu ke itu saja, meskipun dalam bentuk yang lebih terselubung dan “beraroma rakyat”.
UMKM dan koperasi akan hadir di permukaan, tapi kebanyakan dari mereka adalah bagian dari jaringan relawan dan pendukung politik.
Di balik retorika pemerataan, kekuasaan justru semakin terpusat. Kontrol atas sumber daya alam menjadi sarana untuk mempertahankan kekuasaan, bukan demi menyejahterakan publik.
Pada akhirnya, tambang yang katanya untuk rakyat, tetap menjadi tambang bagi penguasa, hanya dengan wajah yang lebih halus, dan narasi yang lebih indah saja.