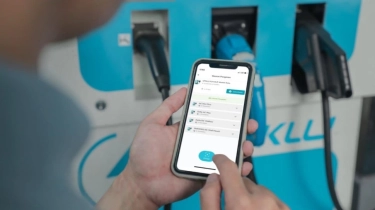Bersahabat dengan Ekonomi Serabutan (Bagian I)
KITA sering memuja angka pertumbuhan, merayakan gelombang digitalisasi, dan membanggakan deret startup yang melesat.
Namun, di balik semua itu, ada dunia yang tak masuk statistik — dunia yang bertahan dalam diam, menghidupi jutaan, tapi nyaris tak dianggap.
Dunia itu bernama ekonomi serabutan. Dan mungkin, di sanalah wajah paling jujur dari bangsa ini sedang menunggu untuk dilihat.
Ia tak punya seragam. Tak ada struktur organisasi. Tak ada gelar yang bisa dipamerkan. Namun, ia nyata — dan ada di mana-mana.
Di balik etalase kecil pinggir jalan, di notifikasi order yang datang tengah malam, di kaki lima yang terus berpindah karena tak punya tempat yang diakui.
Mereka bekerja bukan dari kantor, tapi dari keberanian. Mereka tak punya atasan, tapi setiap pagi dihadapkan pada satu bos yang tak pernah sabar: kebutuhan hidup.
Mereka ini bukan pengangguran, tapi juga bukan pegawai. Mereka hidup di tengah, di ruang abu-abu yang diciptakan oleh sistem yang terlalu kaku untuk melihat kenyataan.
Mereka yang berdagang di emperan, nyambi kerja proyek harian, menjual pulsa sambil mengasuh anak, menjadi kurir, guru les, juru rias, pembuat konten. Bukan karena mereka tak punya arah, tapi karena terlalu banyak pintu tertutup sebelum sempat diketuk.
Kita sering tergoda menertibkan. Memasukkan mereka ke dalam sistem formal, seolah hidup hanya sah bila terstruktur.
Namun, pernahkah kita berhenti sejenak — bukan untuk menata, melainkan untuk melihat?
Untuk mendengar cerita-cerita tentang bagaimana seorang ibu bisa menyekolahkan anaknya hanya dari hasil menjahit lepas dan jualan gorengan.
Atau bagaimana seorang pemuda bertahan hidup dari gabungan kerja ojol, jualan daring, dan jadi MC hajatan. Ini bukan kekacauan. Ini kreativitas. Ini strategi bertahan.
Di balik serabutan, ada keuletan. Di balik ketidakteraturan, ada kecerdikan. Namun juga ada luka: tidak ada perlindungan sosial, tidak ada akses pembiayaan, tidak ada asuransi saat sakit, tidak ada rasa aman.
Mereka bekerja dengan seluruh tubuh dan waktu — tapi negara sering kali hanya hadir saat ingin menertibkan, bukan saat mereka butuh digenggam.
Sekitar 60 persen dari total pekerja di Indonesia berada di sektor informal — setara sekitar 87 juta jiwa, menurut data Badan Pusat Statistik bulan Februari 2025.
Ini bukan segelintir orang. Ini mayoritas. Ini menunjukkan bahwa ekonomi serabutan bukan hanya fenomena sisa, tapi wajah masa kini dari daya hidup rakyat.
Negara-negara seperti Rwanda, Thailand, dan Kolombia sudah lebih dulu melihat apa yang sering kita abaikan.
Rwanda, dengan keberanian yang jujur, mengakui bahwa hampir 90 persen tenaga kerjanya berada di sektor informal. Alih-alih disingkirkan, mereka dimasukkan ke dalam sistem hukum dan perlindungan sosial yang setara.
Di Kigali, pedagang kaki lima diberi tempat, akses modal, dan pelatihan — bukan untuk diseragamkan, tapi agar bisa berdiri lebih tegak dengan martabat yang diakui.
Pemerintah Rwanda menonjolkan pendekatan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada rakyat dari bawah.
Bahkan Kepala Program Lingkungan PBB pernah menyebut Kigali sebagai “kota terbersih di planet ini” — hasil dari kebijakan pemerintah yang tegas dan budaya gotong royong Umuganda, kegiatan bersih-bersih wajib tiap bulan yang diikuti seluruh warga.
Negara yang dulu dikenal dunia karena luka genosida, kini bangkit sebagai salah satu yang terbersih, teraman, dan paling progresif di Afrika — bukan karena menyalin sistem luar, tapi karena memilih mendengarkan rakyatnya sendiri.
Thailand pun menunjukkan bahwa keberpihakan pada ekonomi rakyat bukan sekadar wacana, tapi kebijakan nyata.
Melalui skema Section 40, pemerintah membuka jalur perlindungan sosial bagi pekerja informal seperti pekerja lepas, wiraswasta, pedagang kecil, dan buruh mandiri yang tidak tercakup dalam sistem jaminan sosial formal.
Keanggotaannya bersifat sukarela, dengan iuran bulanan yang lebih rendah — namun manfaatnya mencakup perlindungan kesehatan, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan hari tua, serta bantuan sosial seperti santunan kematian dan bantuan bencana.
Skema ini menjadi andalan dalam menjangkau kelompok yang selama ini luput dari jaring pengaman formal.
Laporan berbagai lembaga internasional menyebutkan bahwa pekerja informal yang masuk melalui Section 40 kini menjadi kelompok peserta terbesar dalam sistem jaminan sosial Thailand — mencerminkan besarnya dukungan negara terhadap pilar ekonomi rakyat.
Lebih dari sekadar perlindungan, Thailand membangun strategi nasional untuk memperkuat ekonomi informal secara menyeluruh.
Pemerintah mendorong pelatihan keterampilan yang sesuai kebutuhan, memperluas akses pembiayaan, mempromosikan pendidikan berkelanjutan, serta memperkuat peran lembaga keuangan dalam integrasi ekonomi rakyat.
Asosiasi Perbankan Thailand, misalnya, aktif mendukung digitalisasi layanan keuangan agar lebih inklusif — memastikan para pelaku usaha mikro dan pekerja mandiri tak lagi berada di pinggir sistem.
Bagi Thailand, ekonomi informal bukan penghalang modernisasi — tapi justru “imunitas nasional” yang terbukti menjaga stabilitas sosial dan ekonomi saat krisis datang.
Sebuah pengakuan yang lahir bukan dari belas kasihan, tapi dari pemahaman mendalam bahwa di sanalah kekuatan negara sesungguhnya bertumbuh.
Kolombia juga memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap pekerja informal bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari upaya rekonstruksi keadilan sosial yang lebih luas.
Melalui kebijakan Formalización Laboral, pemerintah mengintegrasikan pekerja informal ke dalam sistem jaminan sosial secara bertahap, dengan memperhatikan aspek kemanusiaan.
Pendaftaran dipermudah, iuran jaminan sosial disubsidi, dan pelatihan kewirausahaan diberikan untuk memperkuat daya tahan ekonomi pelaku usaha kecil — terutama di sektor perdagangan dan jasa yang mendominasi ekonomi informal.
Yang membedakan Kolombia adalah pendekatan partisipatif yang berbasis komunitas. Kebijakan dirancang melalui dialog langsung dengan organisasi pekerja informal dan komunitas lokal, bukan sekadar dari balik meja birokrasi.
Negara hadir bukan hanya sebagai pengatur, tetapi sebagai mitra yang mendengarkan. Dari sini, lahirlah kebijakan yang lebih relevan, responsif, dan berakar — bukan hanya pada data, tapi pada kenyataan hidup sehari-hari.