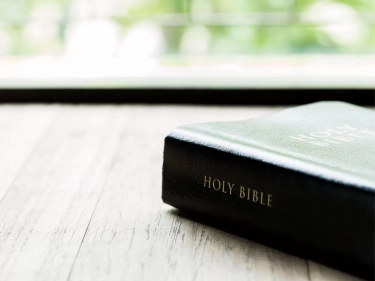Bencana sebagai Ujian Keberadaban
BANGSA ini sudah terlalu lama mengukur kemajuan dari apa yang terlihat: deretan gedung pencakar langit, jalan tol yang seakan tak berujung, kawasan industri yang bekerja siang dan malam, serta angka investasi yang dipromosikan bak prestasi nasional.
Namun, ada ukuran lain yang jauh lebih jujur: bagaimana negara melindungi warganya ketika bencana datang.
Pada momen itulah keberadaban diuji tanpa dekorasi. Tidak ada panggung, tidak ada pencitraan, tidak ada ruang untuk slogan.
Yang tersisa hanyalah pertanyaan paling mendasar: apakah negara menjalankan tugas pertamanya—melindungi manusia?
Kemajuan sejati bukan hanya ketika bangsa membangun, tetapi ketika bangsa memastikan bahwa membangun tidak mengorbankan nyawa rakyatnya.
Sejarah kita menghadapi bencana seperti kaset yang diputar ulang tanpa jeda. Ketika banjir tiba, ketika tanah melorot menghantam pemukiman, ketika asap menutup langit, kita kembali bersatu dalam empati.
Para pemimpin datang, bantuan mengalir, rumah sementara dibangun, dan janji penanganan permanen disampaikan dengan penuh keyakinan.
Namun, begitu air surut dan kamera televisi berhenti merekam duka, kehidupan perlahan kembali ke pola semula. Akar persoalan tidak disentuh, mitigasi tidak dibangun, tata ruang tidak dibenahi.
Bangsa ini menangani luka, tetapi tidak mengobati sebab. Bencana menjadi siklus, bukan kejutan. Dan siklus adalah tanda bahwa kesalahan bukan datang dari alam, tetapi dari manusia yang enggan belajar.
Bencana alam seringkali dibicarakan seolah-olah ia datang tanpa undangan, padahal banyak bencana sesungguhnya adalah buah dari tata kelola yang rapuh.
Sungai dikerangkeng beton dan bangunan, lereng perbukitan dijadikan komoditas, rawa dan resapan air ditebus menjadi klaster perumahan, hutan ditebang untuk industri yang tidak pernah mengenal kata cukup.
Pemerintah daerah berlomba mengeluarkan izin, sementara pemerintah pusat mengukur pembangunan dari seberapa besar pergerakan ekonomi, bukan seberapa aman manusia tinggal di dalamnya.
Sebuah negara boleh membangun apa saja, tetapi selama mitigasi tidak menjadi nafas pembangunan, maka setiap pembangunan sesungguhnya sedang menunda tragedi.
Negara yang hadir setelah bencana menyentuh hati; tetapi negara yang hadir sebelum bencana menyelamatkan nyawa — dan itu jauh lebih mulia.
Kekuasaan
 Foto udara permukiman terendam banjir di kawasan Dadok Tunggul Hitam, Padang, Sumatera Barat, Selasa (25/11/2025). Intensitas curah hujan tinggi membuat sejumlah sungai besar di kota itu meluap dan merendam ratusan rumah.Bencana adalah cermin yang tak pernah berbohong. Ketika air menggenang dan tanah bergeser, seluruh retorika kekuasaan runtuh.
Foto udara permukiman terendam banjir di kawasan Dadok Tunggul Hitam, Padang, Sumatera Barat, Selasa (25/11/2025). Intensitas curah hujan tinggi membuat sejumlah sungai besar di kota itu meluap dan merendam ratusan rumah.Bencana adalah cermin yang tak pernah berbohong. Ketika air menggenang dan tanah bergeser, seluruh retorika kekuasaan runtuh.
Pengungsi tidak menilai pejabat dari panjang pidato atau frekuensi konferensi pers, tetapi dari kecepatan mereka mendapatkan selimut, tempat tidur, air bersih, obat, dan kepastian hidup.
Yang dibutuhkan negeri ini bukan pemimpin yang mahir berdiri di tengah reruntuhan, tetapi pemimpin yang berani memastikan tidak ada reruntuhan.
Mitigasi bukan beban anggaran; ia adalah tabungan masa depan. Pembangunan embung jauh lebih penting daripada pembangunan panggung seremoni.
Keberanian seorang pemimpin tidak diukur dari bagaimana ia tampil dalam krisis, melainkan dari bagaimana ia mencegah krisis itu terjadi.
Sebelum jari kita menunjuk ke arah negara, cermin itu juga perlu diarahkan kepada masyarakat.
Kita membanggakan modernitas, tetapi kita sendiri menyumbat saluran air dengan sampah rumah tangga.
Kita geram ketika sungai meluap, tetapi diam ketika sungai dijadikan tempat pembuangan. Kita marah ketika longsor merenggut nyawa, tetapi acuh ketika pepohonan ditebang habis untuk memperluas permukiman.
Kita lupa bahwa alam bukan pelayan pembangunan, melainkan fondasi keberadaan kita. Selama manusia memperlakukan alam sebagai objek eksploitasi tanpa batas, maka manusia sejatinya sedang menyiapkan tragedi berikutnya dengan tangannya sendiri.
Keadilan
Di negeri ini, bencana tidak mengenai semua orang dengan skala yang sama. Mereka yang tinggal di bantaran sungai, lereng curam, daerah pesisir, bukan tinggal di sana karena tidak memahami bahaya, melainkan karena tidak punya pilihan.
Mereka yang miskin membeli risiko; mereka yang mampu membeli keamanan. Maka bencana bukan hanya soal alam, tetapi soal ketimpangan.
Ketika keselamatan menjadi hak istimewa dan risiko menjadi beban kaum kecil, maka tragedi kehilangan makna geografis dan mengambil wajah sosial.
Negara hanya bisa disebut beradab apabila ia menempatkan mereka yang paling rentan sebagai pihak yang paling dilindungi — bukan paling akhir.
Tidak benar jika kita disebut tidak punya pengetahuan. Peta kerawanan dibuat, kajian teknis disusun, peringatan dini diaktifkan, perangkat hukum tersedia.
BMKG, BNPB, perguruan tinggi, lembaga riset telah menjalankan tugasnya. Namun, ilmu hanya berguna jika ia masuk ke meja kebijakan.
Ketika riset hanya berhenti sebagai laporan, dan rekomendasi teknis hanya menjadi arsip rapat, maka bencana tinggal menunggu momentum untuk mempermalukan kita.
Alam tidak akan pernah mengoreksi dirinya demi menyesuaikan keputusan politik. Politiklah yang harus menyesuaikan keputusannya dengan hukum alam.
Negara yang ingin menutup babak duka harus lebih berani berpihak pada sains daripada pada kepentingan sesaat.
Ada kecenderungan berulang setiap kali tragedi datang: menyalahkan alam. Kita menyebut banjir sebagai air yang “mengamuk”, tanah longsor sebagai bumi yang “murka”, dan gempa sebagai “hukuman”.
Padahal alam tidak pernah marah tanpa sebab. Ia hanya menagih keseimbangan yang dirusak manusia.
Dalam kebudayaan populer kita, sudah ada peringatan moral jauh sebelum bencana datang. Dalam salah satu karya musik legendaris negeri ini, ada refleksi yang menusuk: bahwa "mungkin Tuhan pun letih melihat tingkah manusia yang bangga berbuat salah, dan mungkin alam pun mulai enggan bersahabat dengan kita".
Ajakan untuk “bertanya pada rumput yang bergoyang” adalah metafora bahwa jawaban sudah tersedia di sekitar kita, hanya saja kita terlalu sombong untuk mendengarnya.
Doa memang penting, tetapi doa tidak menggantikan mitigasi. Doa adalah permohonan, dan mitigasi adalah tanggung jawab. Ketika kita berdoa memohon keselamatan tetapi tetap mengulang perusakan, maka kita bukan memohon keselamatan — kita hanya memohon penundaan dari kehancuran yang kita ciptakan sendiri.
Peradaban
Jika bangsa ini ingin keluar dari lingkaran luka yang berulang, satu keputusan fundamental diperlukan: menjadikan keselamatan manusia sebagai indikator pembangunan.
Setiap izin pembangunan harus diuji dampaknya terhadap kehidupan, bukan hanya dampaknya terhadap perolehan modal.
Tata ruang harus dilihat sebagai peta keselamatan, bukan sebagai peta kekuasaan kewilayahan.
Pemerintah pusat dan daerah harus satu nalar dalam memandang ruang hidup. Bangsa ini sudah terlalu lama menjadikan bencana sebagai guru yang mengajar dengan air mata.
Kini saatnya kebijakan yang mengajar dengan keberanian. Mitigasi harus menjadi budaya. Keamanan ekologis harus menjadi prioritas.
Negara yang mencintai rakyat bukan negara yang cepat mengirim bantuan — tetapi negara yang membuat rakyat tak lagi menjadi korban.
Bencana bukan sekadar fenomena alam. Ia adalah cermin keberadaban. Kita memang tidak bisa menghentikan hujan turun, tetapi kita bisa memastikan hujan tidak berubah menjadi kabar duka.
Kita tidak bisa mengubah geografi, tetapi kita bisa mengubah tata kelola. Kita tidak bisa menghentikan air bah, tetapi kita bisa menghentikan kelalaian.
Peradaban tidak diukur dari seberapa cepat kita membangun kembali yang runtuh, tetapi dari seberapa sungguh-sungguh kita mencegah keruntuhan berikutnya.
Bangsa yang beradab bukan bangsa yang tidak pernah jatuh, melainkan bangsa yang belajar cukup dalam agar tidak jatuh di lubang yang sama dua kali.
Bencana adalah ujian keberadaban. Kita belum lulus — tetapi kita masih bisa memilih untuk lulus.