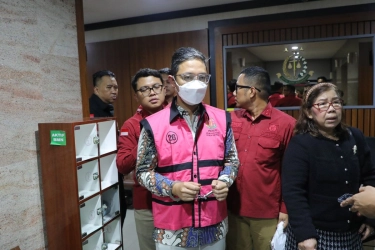Presiden Bukan Pahlawan!
ADA satu usulan yang belakangan ini kembali muncul ke permukaan: semua presiden Indonesia sebaiknya otomatis diberi gelar pahlawan.
Sekilas terdengar masuk akal. Bukankah mereka pernah memimpin bangsa ini? Bukankah jabatan tertinggi layak mendapat penghormatan tertinggi?
Namun, di balik logika yang tampak mulia itu tersembunyi kekeliruan yang tak bisa dibiarkan: kita mencampuradukkan otoritas dengan integritas.
Kita menganggap bahwa karena seseorang pernah menjadi presiden, maka ia pasti layak disebut pahlawan.
Padahal, Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menetapkan syarat yang jauh lebih dalam: integritas moral, keteladanan, perilaku baik, dan bebas dari hukuman pidana berat.
Mengabaikan syarat-syarat ini demi memudahkan proses bukanlah bentuk penghormatan, melainkan bentuk amnesia kolektif yang disengaja.
Kita ingin mengenang tanpa mengingat, memuliakan tanpa mengkaji. Kita ingin sejarah yang nyaman, bukan sejarah yang jujur.
Setiap presiden Indonesia adalah figur yang kompleks. Soekarno adalah proklamator, tapi juga membubarkan DPR dan menerima status presiden seumur hidup.
Soeharto dikenal sebagai “Bapak Pembangunan”, tapi warisannya dibayangi pelanggaran HAM dan praktik KKN yang diakui secara resmi.
Habibie membuka ruang demokrasi, tetapi masa jabatannya diwarnai krisis multidimensi. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dijuluki “Bapak Pluralisme”, tapi kepemimpinannya memicu ketegangan politik.
Susilo Bambang Yudhoyono mendamaikan Aceh, tetapi dikritik atas konflik antara KPK dan Polri. Jokowi membangun infrastruktur masif, tapi mendapat “Rapor Merah” dari mahasiswa atas regresi demokrasi.
Obsesi terhadap pemimpin sempurna adalah refleksi psikologis yang belum dewasa. Kita ingin pahlawan yang bersih dari cela, padahal sejarah tidak pernah sesederhana itu.
Kepahlawanan bukanlah hasil jabatan, melainkan hasil evaluasi kritis terhadap jasa dan kontroversi. Mengkultuskan presiden sebagai pahlawan tanpa syarat adalah bentuk pelarian dari kenyataan bahwa pemimpin adalah manusia yang penuh paradoks.
Jika kita ingin menjadi bangsa yang dewasa, kita harus berani berkata: jabatan bukan jaminan jasa. Presiden bukan otomatis pahlawan. Titik.
Jika elite politik menawarkan logika otoritas, ruang digital menyodorkan jebakan lain: bandwagon fallacy. Kita menganggap sesuatu benar karena populer.
Di era algoritma, kita menyaksikan runtuhnya figur “pahlawan monolitik” yang dulu dinarasikan negara.
Seperti diungkap Jean-François Lyotard, kita hidup di zaman “ketidakpercayaan terhadap metanarasi”. Narasi pahlawan sempurna adalah metanarasi yang telah runtuh.
Roland Barthes dalam “The Death of the Author” menekankan bahwa makna kini ditentukan oleh pembaca, bukan penulis. Dalam konteks digital, “pembaca” adalah publik yang dimediasi algoritma.
Namun, algoritma tidak netral. Ia dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan, bukan kebenaran.
Konten yang sederhana, emosional, dan nostalgik—seperti meme “Piye kabare? Isih penak jamanku, toh?”—lebih mudah viral daripada laporan pelanggaran HAM yang kompleks dan traumatis. Ini bukan ingatan otentik, melainkan produk amnesia historis yang dimediasi teknologi.
Ketika jumlah likes dan shares dianggap sebagai validasi sejarah, kita telah keliru menyamakan legitimasi algoritmik dengan legitimasi historis.
Akibatnya, memori kolektif terfragmentasi ke dalam perang narasi yang tak kunjung usai. Kita tidak lagi mendidik memori, melainkan memuja popularitas.
Fenomena ini bukan sekadar soal nostalgia. Ia adalah cerminan dari cara kita mengonsumsi sejarah: cepat, dangkal, dan emosional.
Kita lebih mudah tersentuh oleh meme daripada oleh arsip. Kita lebih percaya pada viralitas daripada pada verifikasi. Dan dalam proses itu, kita kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kenangan dan kenyataan.
Ironisnya, artikel ini pun berisiko menjadi bagian dari algoritma yang ia kritik. Namun, lebih baik menjadi virus reflektif daripada menjadi vaksin yang tak pernah disuntikkan.
Reformasi memori, bukan seremonial baru
Untuk keluar dari jebakan logika dan algoritma ini, kita membutuhkan reformasi sistemik yang membangun kedewasaan historis. Tiga langkah utama dapat ditempuh:
Pertama, Reformasi Institusional. Proses pemberian gelar pahlawan harus transparan dan deliberatif.
Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan perlu bertransformasi dari lembaga administratif-seremonial menjadi lembaga edukatif-deliberatif.
Setiap kandidat kontroversial harus disertai publikasi neraca sejarah yang utuh—kajian komprehensif atas jasa dan kontroversinya. Bukan hanya daftar pujian, tetapi juga daftar kritik. Bukan hanya glorifikasi, tetapi juga evaluasi.
Bayangkan jika setiap pengajuan gelar pahlawan disertai dengan dokumen sejarah yang jujur dan lengkap. Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi pendidikan publik.
Kita tidak hanya memberi gelar, tetapi juga memberi ruang bagi bangsa untuk belajar dari sejarahnya sendiri.
Kedua, Reformasi Edukasional. Kurikulum sejarah nasional harus mengadopsi pendekatan Critical Historical Thinking.
Sejarah tidak boleh lagi diajarkan sebagai hafalan nama dan tanggal. Ia harus menjadi metode investigasi yang mengajarkan analisis terhadap ambivalensi dan bukti yang saling bertentangan.
Sejarawan Hilmar Farid menekankan pentingnya menjadi bangsa yang “tidak takut pada sejarah”. Ini berarti berani menghadapi sisi gelap masa lalu, bukan menutupinya demi kenyamanan politik atau nostalgia.
Anak-anak kita harus diajak untuk bertanya, bukan hanya menghafal. Mereka harus diajak untuk membaca sumber primer, membandingkan narasi, dan memahami bahwa sejarah adalah arena interpretasi.
Ketiga, Reformasi Kognitif Publik. Kita memerlukan gerakan nasional Literasi Digital Kritis. Ini bukan sekadar cek fakta, tetapi edukasi tentang cara kerja algoritma, echo chamber, dan bias kognitif.
Publik harus memahami bagaimana algoritma mengeksploitasi emosi dan preferensi untuk membentuk persepsi sejarah.
Ketahanan kognitif kolektif adalah benteng terakhir melawan bandwagon fallacy. Tanpa itu, kita akan terus terjebak dalam narasi viral yang menyesatkan dan kehilangan kemampuan untuk mengevaluasi sejarah secara kritis.
Gerakan ini harus melibatkan sekolah, media, komunitas, dan platform digital. Kita perlu membangun budaya digital yang tidak hanya cepat dan interaktif, tetapi juga reflektif dan bertanggung jawab.
Kita perlu mengajarkan bahwa tidak semua yang viral itu benar, dan tidak semua yang populer itu pantas dikenang.
Kepahlawanan sejati tidak lahir dari jabatan atau viralitas. Ia lahir dari keberanian kolektif untuk mengingat secara jujur dan mengevaluasi secara kritis.
Tugas kita bukan mencari pahlawan sempurna, melainkan menjadi bangsa yang dewasa—yang mampu belajar dari pemimpin yang tidak sempurna.