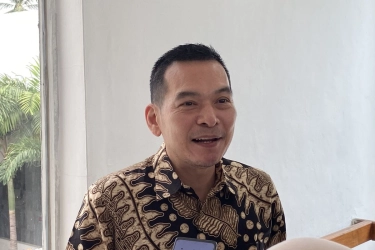Mewujudkan Ekonomi Konsitusi
PIDATO Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya kembali kepada amanat konstitusi ekonomi — khususnya Undang-undang Dasar NRI 1945 Pasal 33 — menandai sinyal strategis dalam orientasi pembangunan ekonomi nasional.
Presiden Prabowo menyampaikan arahan itu pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Oktober 2025.
Dalam arahan tersebut, ia menyatakan bahwa “perekonomian nasional harus dikembalikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan semata pertumbuhan atau keuntungan jangka pendek”.
Ia juga menyinggung bahwa Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia masih mengalami kelangkaan minyak goreng — sebagai indikasi bahwa mekanisme pasar belum mencerminkan keadilan sosial.
Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami substansi Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai landasan hukum ekonomi negara.
Pasal 33 ayat (1) menyatakan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”
Ayat (2): “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”
Ayat (3): “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Penjelasan lebih lanjut (termasuk setelah amandemen) menyebut bahwa ayat (4) menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi... dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
Dalam tinjauan sejarah hukumnya, Pasal 33 dimaknai sebagai “ideologi ekonomi Indonesia” — yaitu suatu rumusan yang menegaskan kedaulatan ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai salah satu tujuan dari Indonesia merdeka.
Penafsiran yuridis-normatif menunjukkan bahwa penguasaan negara atas cabang produksi penting ataupun kekayaan alam tidak dapat direduksi hanya sebagai hak regulasi, melainkan mencakup mandat moral untuk kemakmuran rakyat secara kolektif.
Dengan demikian, ketika Presiden Prabowo kembali menegaskan Pasal 33 sebagai landasan ekonomi konstitusi dan mendorong kedigdayaan ekonomi rakyat, maka pidato tersebut sesungguhnya menegaskan “ekonomi konstitusi” sebagai kembali ke amanat UUD dan nilai-nilai Pancasila: kedaulatan, kemandirian, pemerataan, dan keberpihakan pada seluruh rakyat.
Namun, penting dicatat bahwa meskipun landasan tersebut kuat secara konstitusional dan historis, implementasi nyata menghadapi tantangan struktural, yakni masih merajalelanya ideologi kapitalisme, seperti mekanisme pasar yang semakin terbuka hampir tanpa batas, globalisasi modal asing, liberalisasi investasi, termasuk isu persaingan modal besar oligarki versus kepentingan rakyat kecil.
Pidato Presiden dapat dibaca sebagai momentum korektif terhadap bias kapitalisme yang telah lama mendominasi orientasi pembangunan nasional.
Visi Ekonomi Pancasila
Pemikiran ekonomi bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya soal produksi dan konsumsi, tetapi juga soal kemerdekaan, kedaulatan dan keadilan sosial.
Bung Karno dalam Deklarasi Ekonomi tahun 1963 menegaskan bahwa pembangunan harus diarahkan untuk “menyusun perekonomian yang berdikari”, bebas dari ketergantungan modal asing, dan berorientasi kepada kepentingan rakyat.
Ekonomi Berdikari menjadi sikap ekonomi bagi perwujudan sosialisme Indonesia yang menjadi visi ekonomi dari Pancasila.
Sementara itu, Mohammad Hatta dalam "Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun" (1954) memandang koperasi sebagai bentuk organisasi ekonomi yang menempatkan manusia sebagai pusat, bukan modal.
Ia menulis bahwa “koperasi adalah alat pendidikan sosial yang mengajarkan rakyat untuk saling tolong-menolong dan membangun kekuatan bersama.”
Pemikiran tersebut mengusung jalan tengah antara kapitalisme yang menindas dan sosialisme yang mengabaikan kebebasan individu.
Beberapa dekade kemudian, Mubyarto secara konsisten mengembangkan pemikiran “Ekonomi Pancasila” sebagai kerangka sistem ekonomi alternatif.
Dalam bukunya "Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan" (1987), Mubyarto menyusun konsep sistem ekonomi Pancasila yang merujuk pada “usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan.”
Ia mengkritik arus dominan ekonomi neoklasik yang terlalu menekankan efisiensi pasar dan mengabaikan dimensi moral pembangunan.
Bagi Mubyarto, ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya pertumbuhan, tetapi sejauh mana kemiskinan berkurang, lapangan kerja terbuka, dan rakyat kecil memperoleh kemandirian ekonomi.
Ketiga tokoh ini, meskipun berbeda dalam konteks zamannya, menyepakati substansi bahwa ekonomi harus berpihak pada rakyat — bukan hanya tatanan pasar bebas yang tanpa kendali.
Soekarno dengan kedaulatan ekonomi, Hatta dengan prioritas koperasi dan manusia sebagai subjek ekonomi, serta Mubyarto dengan kerangka sistem ekonomi Pancasila yang menjembatani nilai moral dan struktur ekonomi.
Warisan pemikiran mereka dapat menjadi fondasi bagi interpretasi “ekonomi konstitusi” masa kini — yaitu, bagaimana melaksanakan ekonomi yang dirancang dalam UUD 1945 dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka globalisasi dan persaingan pasar yang semakin terbuka.
Realitas kapitalistik dan penguatan ekonomi konstitusi
Empat dekade terakhir menunjukkan pergeseran tajam dalam orientasi ekonomi nasional menuju liberalisasi dan dominasi mekanisme pasar.
Kebijakan deregulasi dan liberalisasi sejak 1980-an, undang-undang dilakukan seperti UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membuka investasi asing dan memperluas ruang swasta tanpa pengaturan kontrol sosial yang memadai.
Akibatnya, terjadi privatisasi BUMN, pelemahan proteksi sektor rakyat kecil, dan akumulasi modal besar yang semakin kuat.
Realitas ini membentuk struktur ekonomi yang oleh banyak kritikus sebut sebagai “kapitalistik” dalam arti orientasi kepada akumulasi modal besar yang dikuasai oleh segelintir oligarki yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan.
Dari segi angka, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rasio Gini pengeluaran penduduk Indonesia per September 2024 tercatat sebesar 0,381.
Ini menandakan bahwa meskipun terjadi sedikit penurunan dibanding Maret 2023 (0,388) ke Maret 2024 (0,379) , ketimpangan ekonomi masih relatif tinggi.
Distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah pada September 2024 tercatat hanya 18,41 persen dari total pengeluaran nasional.
Secara struktur, Bank Dunia mencatat 20 persen kelompok teratas menguasai hampir separuh total pendapatan nasional — yang mencerminkan pola akumulasi yang sangat timpang.
Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi pasar bebas dan akumulasi modal besar belum menciptakan pemerataan yang signifikan.
Dari aspek hukum, penafsiran Pasal 33 ayat (2) dan (3) menunjukkan bahwa penguasaan negara atas cabang produksi penting dan kekayaan alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Namun, realitas pengelolaan sumber daya alam kerap menunjukkan bahwa nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh korporasi besar atau investor asing, sementara manfaat lokal atau rakyat kecil masih terbatas.
Untuk menghidupkan kembali semangat “ekonomi konstitusi” sebagai yang ditekankan Presiden, setidak-tidaknya dapat ditempuh melalui empat langkah strategis.
Pertama, memperkuat kembali peran negara dan BUMN di sektor strategis, bukan sekadar sebagai pelaku bisnis, tetapi sebagai pelindung kepentingan publik.
Kedua, merevitalisasi koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat modern dan profesional yang tumbuh dari bawah berdasarkan kepentingan ekonomi rakyat banyak (sejalan dengan Hatta dan Mubyarto).
Ketiga, mengarahkan kebijakan investasi dan hilirisasi sumber daya alam agar tercipta nilai tambah di dalam negeri dan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.
Keempat, memperkuat regulasi sosial dan perlindungan rakyat agar pembangunan tidak hanya efisien tetapi juga adil dan manusiawi.
Langkah-langkah ini tidak menolak mekanisme pasar modern, melainkan menempatkannya dalam bingkai moral pembangunan: bahwa keterbukaan ekonomi dan persaingan global harus tunduk pada nilai nasional dan kepentingan rakyat.