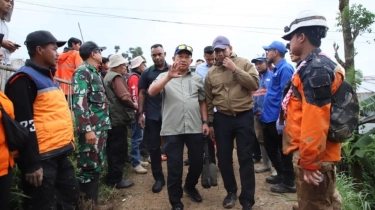Polisi, Pedagang Kopi Keliling, dan Batas Keamanan Publik
KEBIJAKAN Kepolisian Daerah Metro Jaya yang menjadikan pedagang kopi keliling sebagai mata dan telinga aparat mungkin tampak sebagai langkah sederhana untuk memperkuat keamanan kota.
Di hadapan publik, gagasan ini dikemas dalam narasi humanis: polisi ingin lebih dekat dengan rakyat, mendengar denyut kehidupan masyarakat kecil, dan membangun kebersamaan dalam menjaga ketertiban.
Namun, di balik citra yang hangat itu, tersimpan arah baru dalam cara negara memandang rakyatnya. Bukan lagi sebagai pemilik kedaulatan, melainkan sebagai pelengkap kekuasaan.
Dalam kebijakan ini, rakyat diminta menjadi perpanjangan tangan negara dalam fungsi pengawasan, bukan subjek yang berdaulat atas ruang sosialnya sendiri.
Dalam demokrasi yang sehat, rakyat menugaskan aparat untuk menjaga keamanan, bukan sebaliknya. Hubungan yang ideal bersifat vertikal, dengan kejelasan mandat dan akuntabilitas.
Ketika aparat justru meminta rakyat menjadi pengawas bagi sesamanya, relasi ini berubah secara fundamental.
Kedaulatan yang semula berada di tangan warga bergeser ke dalam struktur kekuasaan yang memobilisasi mereka sebagai alatnya.
Proses ini berlangsung tanpa paksaan, tanpa kekerasan, bahkan tanpa rasa curiga, karena semuanya dikemas dalam bahasa empati dan gotong royong. Inilah bentuk baru dari kekuasaan yang bekerja melalui persuasi moral, bukan perintah eksplisit.
Michel Foucault, dalam Discipline and Punish, menunjukkan bahwa kekuasaan modern tidak lagi menindas tubuh, melainkan mengatur perilaku dan kesadaran.
Kekuasaan bekerja bukan dari atas, tetapi dari dalam diri individu, yang tanpa sadar mengatur perilakunya sesuai norma yang ditanamkan negara.
Bentuk ideal dari sistem ini disebutnya sebagai panoptikon, di mana seseorang merasa selalu diawasi meski tidak tahu kapan pengawasan itu terjadi.
Dalam masyarakat modern, menara pengawasan itu tak lagi berupa bangunan, melainkan sistem sosial yang membuat setiap orang menjadi penjaga bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain.
Kebijakan yang mengajak pedagang kopi keliling menjadi mata dan telinga polisi adalah manifestasi kontemporer dari panoptikon yang digambarkan Foucault.
Negara tidak lagi perlu mengawasi secara langsung karena pengawasan kini dijalankan oleh warga yang percaya sedang berbuat baik.
Dengan menggabungkan peran sosial, moral, dan keamanan, kebijakan ini menciptakan warga yang secara sukarela menjadi bagian dari sistem kontrol.
Ia menghapus jarak antara negara dan masyarakat bukan dengan kepercayaan, tetapi dengan integrasi fungsional yang menempatkan warga sebagai operator dari mesin pengawasan sosial.
Kebijakan ini memang tampak berbeda dari model pengawasan keras yang dijalankan rezim otoriter. Tidak ada ancaman, tidak ada tekanan, tidak ada larangan eksplisit. Namun, efektivitasnya justru terletak pada kelembutannya.
Ketika pengawasan dibungkus dalam narasi kebersamaan, warga menerima peran itu tanpa merasa sedang kehilangan kebebasan.
Mereka percaya sedang membantu negara menjaga ketertiban, padahal perlahan kehilangan posisi sebagai pemilik kedaulatan. Proses ini bukan lagi kontrol koersif, melainkan kontrol persuasif yang bekerja melalui nilai moral dan rasa tanggung jawab sosial.
Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Dalam banyak negara, pengawasan berbasis warga telah menjadi bagian dari politik keamanan modern.
Di Amerika Serikat, program neighborhood watch yang dimaksudkan untuk memperkuat rasa aman di lingkungan sering kali memperluas stereotip dan kecurigaan terhadap kelompok minoritas.
Di China, sistem grid management memungkinkan negara mengendalikan kehidupan warga hingga tingkat blok perumahan melalui relawan sosial.
Dalam sejarah abad ke-20, Uni Soviet menjadi contoh ekstrem tentang bagaimana pengawasan sosial dilembagakan secara sistemik. Di bawah rezim Stalin, jaringan informan sipil menjadi instrumen utama kekuasaan.
Setiap warga bisa menjadi pelapor, setiap percakapan pribadi bisa berubah menjadi catatan ideologis. Pengawasan dilakukan bukan semata oleh aparat, tetapi oleh sesama warga yang berlomba menunjukkan loyalitas.
Model Soviet ini bekerja dengan logika ketakutan dan ideologi. Namun dalam masyarakat modern, mekanisme serupa dapat hadir tanpa tekanan politik yang kasat mata.
Jika di masa lalu warga mengawasi karena takut, kini mereka diajak mengawasi karena merasa peduli.
Kesamaan dari semua kasus ini terletak pada logika kekuasaan yang sama. Negara menciptakan masyarakat yang berpartisipasi bukan untuk memperkuat suara publik, tetapi untuk memperluas jangkauan kendali.
Partisipasi menjadi bentuk baru dari disiplin sosial. Semakin banyak warga yang merasa terlibat, semakin efektif sistem itu bekerja, sebab pengawasan sukarela tidak membutuhkan sumber daya besar, hanya legitimasi moral.
Dalam kerangka inilah kebijakan “mata dan telinga polisi” harus dibaca bukan sebagai inovasi keamanan, melainkan sebagai transformasi sosial yang berpotensi menumbuhkan masyarakat pengawas.
Implikasinya jauh lebih luas daripada sekadar urusan keamanan. Ketika warga diajak melaporkan hal-hal yang mencurigakan, masyarakat mulai beroperasi dalam logika kecurigaan.
Hubungan sosial yang sebelumnya dibangun di atas rasa percaya perlahan digantikan oleh kewaspadaan. Warga tidak lagi melihat sesamanya sebagai mitra sosial, melainkan sebagai potensi ancaman.
Aparat tak perlu memecah masyarakat secara terbuka, karena masyarakat telah diajari untuk saling menjaga yang dalam praktiknya sering berarti saling mengawasi.
Di sinilah bahaya kebijakan ini menjadi nyata. Ia menanamkan polarisasi mikro di tengah warga tanpa perlu konflik terbuka.
Bahaya itu bukanlah adu domba dalam pengertian klasik, tetapi jauh lebih subtil. Negara menciptakan harmoni semu, di mana warga merasa bersatu dalam tugas menjaga keamanan, padahal mereka diarahkan untuk mengawasi satu sama lain.
Kebersamaan berubah menjadi strategi kontrol. Rakyat kehilangan posisi sebagai pengendali kekuasaan dan berubah menjadi bagian dari sistem pengawasan yang mereka percayai.
Demokrasi kehilangan energi moralnya ketika warga berhenti menjadi pengawas terhadap negara dan mulai menjadi pengawas terhadap sesamanya.
Kritik terhadap kebijakan ini tidak berarti menolak gagasan keamanan. Keamanan adalah kebutuhan dasar setiap masyarakat, tetapi keamanan yang sehat harus lahir dari kepercayaan, bukan dari rasa curiga.
Negara yang sungguh kuat tidak mengandalkan pengawasan, melainkan legitimasi. Ia tidak membangun rasa aman dengan menanamkan ketakutan, tetapi dengan menegakkan keadilan.
Ketika aparat melibatkan warga, keterlibatan itu seharusnya dalam kerangka deliberasi, bukan subordinasi.
Polisi bisa mendengar cerita rakyat tanpa meminta mereka menjadi alat negara. Kedekatan tidak harus berarti keterikatan fungsional, apalagi subordinasi sosial.
Jika kita lihat secara lebih luas, kebijakan ini menunjukkan bagaimana negara mengaburkan batas antara perlindungan dan kontrol.
Dengan dalih partisipasi, negara menggeser tanggung jawab keamanan kepada warga tanpa memberikan ruang bagi mereka untuk menentukan arah kebijakan.
Padahal dalam demokrasi, partisipasi selalu bersifat dua arah. Warga memiliki hak untuk terlibat dalam perumusan kebijakan, bukan hanya menjadi pelaksana moral dari kebijakan yang telah ditetapkan dari atas.
Partisipasi sejati bukanlah kesediaan membantu negara, melainkan kemampuan mengoreksi negara.
Kecenderungan semacam ini memperlihatkan bagaimana demokrasi bisa meluncur perlahan ke arah disiplin sosial tanpa melalui represi.
Bentuknya bukan pelarangan, melainkan normalisasi. Tidak ada yang dilarang, tetapi semua diarahkan. Orang tidak merasa ditindas, tetapi terbiasa mengawasi dan diawasi.
Itulah kekuasaan modern dalam bentuknya yang paling efisien, seperti yang digambarkan Foucault, ketika kekuasaan tidak lagi membutuhkan kekerasan karena telah tertanam dalam kesadaran warga.
Sejarah Uni Soviet memberi pelajaran penting tentang bagaimana masyarakat kehilangan solidaritas ketika rasa curiga dilembagakan.
Negara yang menuntut kesetiaan mutlak atas nama keamanan akhirnya menumbuhkan warga yang hidup dalam ketakutan.
Kini, bentuk pengawasan serupa bisa muncul tanpa represi ideologis, tetapi dengan efek sosial yang tak kalah destruktif.
Rasa curiga yang dibungkus kepedulian tetaplah racun bagi demokrasi, karena ia menggantikan solidaritas dengan ketaatan, dan kepercayaan dengan kepatuhan.
Dalam konteks Indonesia, transformasi semacam ini memiliki dampak yang lebih kompleks karena masyarakat kita masih membawa warisan relasi paternalistik antara negara dan rakyat.
Negara masih dipandang sebagai pelindung, bukan pelayan publik. Ketika aparat berbicara dengan nada empati dan mengajak rakyat bekerja sama, ajakan itu dengan mudah diterima tanpa kecurigaan.
Padahal di sanalah awal dari pergeseran kedaulatan itu terjadi. Rakyat yang seharusnya menjadi sumber kekuasaan berubah menjadi alat yang menopangnya.
Pada akhirnya, demokrasi tidak runtuh karena kekerasan, tetapi karena rasa percaya yang salah arah.
Ketika rakyat percaya bahwa tugas mereka adalah membantu negara menjaga ketertiban, bukan menuntut negara menjaga keadilan, maka demokrasi telah kehilangan jiwanya.
Keamanan yang dibangun di atas kecurigaan hanya akan menciptakan keteraturan yang hampa.
Kota yang aman bukanlah kota yang dijaga oleh seribu mata yang mengintai, melainkan kota di mana setiap orang merasa dilihat tanpa diawasi, dihargai tanpa dimanfaatkan, dan dilindungi tanpa harus menjadi alat bagi kekuasaan.
Kebijakan “mata dan telinga polisi” bukan sekadar eksperimen sosial, melainkan cermin dari cara negara memandang rakyatnya.
Jika rakyat terus diposisikan sebagai perpanjangan tangan aparat, maka negara sedang membangun demokrasi tanpa warga. Dan demokrasi tanpa warga pada akhirnya hanyalah administrasi dengan nama lain.
Rakyat seharusnya tetap menjadi subjek yang berdaulat, bukan instrumen yang dimobilisasi untuk menopang stabilitas kekuasaan.
Negara yang benar-benar kuat adalah negara yang percaya kepada rakyatnya tanpa harus menjadikan mereka pengawas bagi sesamanya.
Tag: #polisi #pedagang #kopi #keliling #batas #keamanan #publik