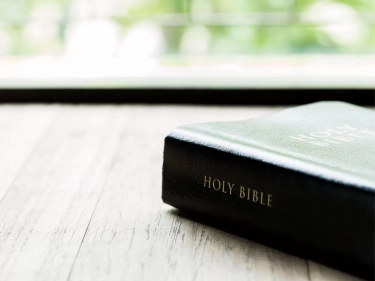Negara dan Perempuan
SETIAP 21 April, kita merayakan nama Kartini. Sekolah-sekolah penuh kebaya. Kantor-kantor menggelar lomba menghias tumpeng. Pidato-pidato menyebut perempuan sebagai tiang bangsa, penyangga keluarga, pejuang ganda yang tabah.
Namun Kartini, jika bisa hadir sejenak hari ini, mungkin tak akan tersenyum. Ia akan bertanya: “Sudahkah negara benar-benar berpihak kepada perempuan?”
Karena peringatan bukan soal bunga dan busana. Ia soal warisan pemikiran. Kartini bukan selebrasi, tapi protes yang ditulis dalam surat. Bukan simbol, tapi suara dari yang dibungkam.
Dan jika kita ingin sungguh-sungguh menghormatinya, maka kita harus melihat hubungan perempuan dan negara dengan mata yang jujur.
Setiap kali negara berbicara tentang perempuan, yang terdengar bukan suara, tapi gema. Gema dari ruang-ruang sidang yang disterilkan dari pengalaman perempuan.
Gema dari podium seremonial yang gemar memuji perempuan sebagai “pilar bangsa”, tetapi tak pernah menanyakan bagaimana rasanya menjadi pilar yang terus retak karena beban struktural.
Dalam pidato-pidato resmi, perempuan dipanggil dengan kata hormat: ibu, bunda, kartini, srikandi. Namun dalam kebijakan dan hukum, suara mereka tereduksi menjadi angka, program, dan indikator.
Negara mencintai perempuan dalam bentuk simbolik, tetapi gagal mencintai mereka sebagai subjek yang hidup dalam tubuh dan luka.
Perempuan di republik ini telah lama tahu: negara bisa hadir, tapi tak selalu berpihak.
Negara yang bicara, perempuan yang dibungkam
Kita hidup di negara yang rajin menyusun strategi kesetaraan gender—mulai dari RPJMN, Renstra Kementerian PPPA, hingga SDG’s Goal 5. Namun, perempuan tetap saja menjadi kelompok yang paling sering dilupakan dalam pengambilan keputusan.
Lihat bagaimana penyusunan UU penting seperti Omnibus Law Cipta Kerja dilakukan tanpa melibatkan buruh perempuan yang terdampak langsung oleh deregulasi.
Lihat bagaimana revisi KUHP diloloskan dengan pasal-pasal kesusilaan yang bisa menghukum korban, bukannya pelaku. Lihat bagaimana RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dibiarkan menggantung selama dua dekade.
Negara bicara dalam bahasa birokrasi. Perempuan bicara dari perut yang lapar, rahim yang dilecehkan, tubuh yang dijadikan instrumen politik moral. Dan dua bahasa ini tak pernah sungguh-sungguh disambungkan.
Setiap tahun Komnas Perempuan merilis Catatan Tahunan. Angka kekerasan seksual naik. Kekerasan dalam rumah tangga tetap tinggi.
Kasus perkawinan anak merayap di bawah karpet adat. Namun, negara tak bergerak secepat data. Ia sibuk menyusun rencana aksi, menyusun forum lintas kementerian, menyusun draft, draft, dan draft.
Kita tahu negara tak buta. Ia punya semua alat—BPS, KemenPPPA, LSM, bahkan teknologi big data. Namun, masalahnya bukan pada ketidaktahuan. Masalahnya pada ketidakpedulian.
Karena bagi negara, perempuan sering hanya dihitung saat dibutuhkan. Dalam pemilu sebagai pemilih. Dalam statistik sebagai penerima bansos. Dalam pembangunan sebagai target, bukan subjek.
Dari total 48 menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini, hanya 5 yang perempuan. Dari 481 kepala daerah hasil Pilkada terakhir, hanya 43 yang perempuan.
Dan di DPR RI, dari 580 anggota, hanya 127 yang perempuan—itu pun sebagian besar berasal dari lingkaran politik dinasti atau keluarga elite partai.
Di negeri dengan lebih dari separuh penduduknya adalah perempuan, keterwakilan dalam pengambilan keputusan masih tersandera sistem patriarkis dan pragmatisme politik elektoral.
Dalam sistem politik yang maskulin, kebijakan menjadi bias maskulin. Perempuan masuk dalam kategori “penerima manfaat”, tapi jarang dilibatkan dalam proses perumusan. Mereka dicatat, tapi tak pernah diajak bicara.
Negara senang mengatur tubuh perempuan—dari cara berpakaian hingga urusan moral—tapi enggan melindungi tubuh yang disakiti.
Perempuan, negara, dan kekerasan yang tak diakui
Kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar tindakan individual. Ia adalah bentuk kegagalan negara melindungi warganya. Ia adalah cermin sistemik dari relasi kuasa yang timpang.
Ketika seorang perempuan diperkosa di rumah, dan aparat menyuruhnya “memaafkan demi keluarga”—itu adalah kekerasan negara.
Ketika seorang PRT dianiaya majikan, dan negara tidak memiliki payung hukum untuk membelanya—itu adalah kekerasan negara.
Ketika seorang mahasiswi dilecehkan dosen, dan kampus bungkam karena pelaku adalah guru besar—itu adalah kekerasan negara.
Karena negara yang membiarkan, sama saja dengan negara yang melakukan.
UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah langkah penting. Namun, satu undang-undang tak cukup jika sistem hukum dan budaya aparatnya masih misoginis. UU TPKS adalah jendela, tapi dinding ruang keadilan masih gelap.
Kita menyaksikan, bahkan setelah UU TPKS disahkan, proses hukum terhadap pelaku kekerasan seksual masih lambat, berbelit, dan sering menjatuhkan korban dalam reviktimisasi.
Seolah korban harus membuktikan bukan hanya ia disakiti, tetapi bahwa ia layak untuk diselamatkan.
Negara hadir lewat undang-undang. Perempuan butuh negara yang hadir lewat pendampingan, perlindungan, dan keberpihakan di ruang sidang.
Di banyak tempat, negara justru hadir untuk mengatur tubuh perempuan—bukan melindunginya. Kita lihat itu dalam regulasi berpakaian, pengawasan moral terhadap konten perempuan, bahkan dalam pembatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi.
Tubuh perempuan dianggap “milik bersama”. Negara merasa berhak ikut mengatur, mengawasi, bahkan menghakimi. Namun, saat tubuh itu dilukai, negara sering lambat, kaku, dan diam.
Perempuan yang ingin aborsi karena pemerkosaan, harus menghadapi prosedur medis dan hukum yang panjang. Sementara pelaku pemerkosaan bisa bebas karena “tidak cukup alat bukti”. Negara seolah lebih khawatir pada moral publik daripada pada penderitaan warganya.
Kita tak sedang menuntut negara menjadi feminis. Tapi kita menuntut negara belajar mendengar. Bukan dengan menyusun program dari balik meja, tetapi dengan turun, menyelami, dan mengakui bahwa luka perempuan adalah luka bangsa.
Negara yang setara gender bukan negara yang menambah kuota perempuan, lalu merasa selesai. Namun, negara yang mengubah cara kerja: dari vertikal menjadi partisipatif, dari prosedural menjadi empatik.
Negara yang adil gender bukan negara yang memuji perempuan sebagai ibu, tetapi memperlakukan mereka sebagai warga negara seutuhnya: dengan hak, suara, dan agensi.
Kartini bukan upacara
Kartini, jika hidup hari ini, mungkin tidak bangga. Karena namanya dijadikan simbol, tapi pemikirannya tidak dijalankan.
Ia menulis tentang kesetaraan, tapi negara masih bicara soal kodrat. Ia menulis tentang pendidikan dan kebebasan, tapi negara masih mengatur pakaian dan perilaku perempuan.
Kartini tidak meminta perempuan disayangi. Ia meminta mereka dihormati. Dan penghormatan itu tidak lahir dari bunga di pundak, tapi dari perlindungan yang nyata.
Kesetaraan gender bukan soal pilihan politik. Ia adalah mandat konstitusi. Negara yang abai pada perempuan adalah negara yang melanggar keadilan sosial.
Karena itu, negara tak boleh netral. Dalam dunia yang timpang, netralitas adalah keberpihakan pada yang kuat.
Perempuan telah berjalan jauh tanpa negara. Kini saatnya negara berjalan bersama mereka. Bukan di depan, bukan di belakang—tapi di samping. Dengan telinga terbuka dan hati yang bersedia berubah.
Karena perempuan tidak butuh pujian. Mereka butuh negara yang hadir dan berpihak.
Tag: #negara #perempuan