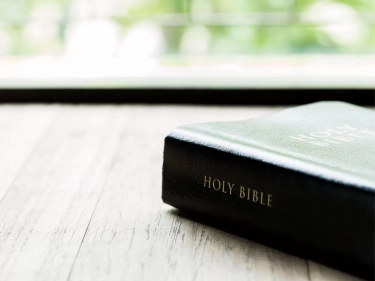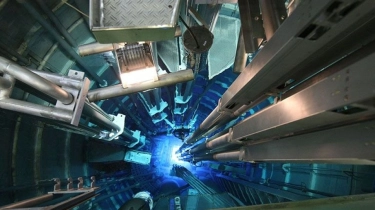Rp 17.000, Dollar AS, dan Harga Kepercayaan
KAMIS, 22 Januari 2026, rupiah menyeberang satu garis yang oleh para ekonom disebut “psikologis”: Rp 17.000 per dollar Amerika. Seolah ada palang pintu di situ.
Ketika palang itu terangkat, orang mendengar bunyi yang tak tercatat dalam statistik: bunyi kecemasan.
Di situs Bank Indonesia, angka itu ditulis rapi dan tak sentimental: kurs jual Rp 17.047,81 dan kurs beli Rp 16.878,19 untuk 1 dollar AS. Di JISDOR.
Ini memberi kita semacam “titik tengah” yang lebih resmi: angka 22 Januari 2026 dicatat Rp 16.902 per dollar AS (Bank Indonesia, 2026).
Kurs, seperti kalender, tampak netral. Padahal, ia menyimpan cuaca: panas dan dingin yang dialami orang-orang yang tak pernah membuka laman BI.
Karena uang, kita tahu dari sejarah panjangnya, tak pernah sepenuhnya benda. Ia, lebih sering, adalah janji. Selembar kertas yang kita tukar dengan keyakinan bahwa esok ia masih punya arti.
Apa yang membuat rupiah melemah? Selalu ada jawaban teknis: arus modal yang keluar-masuk, imbal hasil obligasi, neraca perdagangan, defisit fiskal, suku bunga global yang keras kepala.
Ada pula jawaban yang lebih sulit diukur: sentimen. Dan sentimen, dalam pasar, adalah seperti bau asap. Bahkan ketika api belum terlihat, orang mulai berlari.
Reuters menyebut rupiah melemah hampir 2 persen sepanjang Januari 2026 dan sebelumnya turun sekitar 3,5 persen pada 2025.
Angka-angka ini seperti garis tipis pada peta gempa: bukan letusan tunggal, melainkan rangkaian getar yang membuat dinding rumah pelan-pelan retak.
Pada saat yang sama, kekhawatiran investor tentang kesehatan fiskal dan independensi bank sentral ikut disebut sebagai latar yang menekan. Bahkan defisit 2025 yang dicatat sekitar 2,92 persen PDB, mendekati batas disiplin 3 persen (Reuters, 2026; Kementerian Keuangan, 2025).
Namun, di luar istilah-istilah itu ada sesuatu yang lebih sederhana: ketika rupiah melemah, hidup menjadi lebih mahal. Dan mahal itu tidak selalu datang dalam bentuk barang mewah. Ia kadang masuk lewat pintu belakang.
Bhima Yudhistira menyebut satu kata yang terdengar teknis, tapi berdampak sangat domestik: imported inflation.
“Jika rupiah tembus Rp 17.000 per dollar, inflasi impor tidak terhindarkan. Harga barang impor naik dan itu akan langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya (Bhima Yudhistira/CELIOS, 2026). Kalimatnya pendek, nyaris seperti peringatan di tikungan tajam.
Imported inflation adalah jenis inflasi yang datang bukan karena kita belanja berlebihan, melainkan karena mata uang kita mengecil terhadap mata uang yang kita butuhkan.
Ia bekerja seperti ini: sesuatu yang berharga 100 dollar AS, entah itu bahan baku industri, obat, alat kesehatan, atau pangan impor, ketika kurs Rp 16.000, nilainya Rp 1,6 juta. Ketika kurs Rp17.000, ia menjadi Rp 1,7 juta. Selisih Rp 100.000 itu bukan keputusan pedagang; itu keputusan kurs. Dan kurs, kita tahu, tidak pernah meminta izin.
Maka perubahan di layar itu segera merembes ke meja makan. Mungkin dalam bentuk harga yang naik pelan-pelan, lalu tiba-tiba terasa: “kok sekarang harganya segini?” Seperti matahari sore yang meredup perlahan, hingga kita tersadar senja telah berubah menjadi malam.
Namun, inflasi impor tidak berhenti di rak toko. Ia bergerak lebih jauh: ke pabrik.
Industri kita banyak yang bergantung pada bahan baku impor. Ketika kurs melemah, biaya input naik. Lalu manajemen menghadapi tiga pilihan yang sama getirnya: menaikkan harga jual (dan risiko pasar lari), menelan margin (dan risiko rugi), atau melakukan efisiensi.
Di sini, “efisiensi” sering menjadi kata yang sopan untuk sesuatu yang brutal: pengurangan jam kerja, penutupan lini produksi, atau PHK.
Kurs yang melemah bisa menyusup menjadi keputusan personal: seseorang pulang lebih cepat dari kantor dengan surat di tangan.
Tak ada yang romantis pada PHK. Namun, sering kali ia lahir dari kalkulasi yang dingin. Dalam kalkulasi itu, Rp 17.000 menjadi batas yang terasa sebagai pembenaran: perusahaan terpaksa.
Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah penyesuaian besar: ekonomi menegosiasikan ulang dirinya.
Di sisi lain, kurs juga menghantam tempat yang lebih tinggi dan lebih sunyi: neraca utang negara.
Utang luar negeri pemerintah, menurut Bank Indonesia, pada November 2025 tercatat 209,8 miliar dollar AS. Angka ini seperti gunung es: besar, tapi sering dilihat hanya ujungnya.
Sebab yang menjadi persoalan bukan semata jumlah dolar, melainkan bagaimana dolar itu dibayar dalam rupiah.
Kita bisa membayangkan dampaknya dengan cara yang vulgar, tapi jelas: jika 209,8 miliar dollar AS dikonversi dengan kurs Rp 16.000, nilainya sekitar Rp 3.356 triliun; jika kurs Rp 17.000, nilainya menjadi sekitar Rp 3.567 triliun.
Tanpa menambah utang satu dolar pun, beban dalam rupiah “mengembang” hanya karena kurs berubah. Seakan ada makhluk hidup di sana, utang yang tumbuh hanya karena nilai tukar melemah.
Dan pada 2026, pemerintah menargetkan penarikan utang baru Rp 832,20 triliun untuk membiayai defisit APBN.
Setiap pelemahan rupiah membuat ruang fiskal makin sempit. Seperti kain yang ditarik dari dua sisi: belanja publik di satu ujung, kewajiban pembayaran di ujung lain.
Ketika kurs bergerak, tarikan itu makin keras. Lalu, kita mulai mendengar pertanyaan lama yang tak pernah sepenuhnya hilang: sampai kapan?
Di titik inilah, pelemahan mata uang tidak lagi soal domestik. Ia menjadi bagian dari kisah yang lebih luas.
Jepang pernah membiarkan yen melemah lama, karena struktur industrinya kuat ekspor dan ia butuh inflasi yang dulu sulit tumbuh.
Di Turkiye, depresiasi menjadi petaka karena krisis kepercayaan pada kebijakan moneter; inflasi melonjak dan mata uang seperti kehilangan jangkar. Argentina mengulang cerita tragis berulang kali: inflasi, pelemahan mata uang, kontrol harga, dan putaran baru.
Indonesia bukan Jepang, bukan pula Turkiye atau Argentina. Kita berdiri di wilayah abu-abu: disiplin defisit dijaga, tetapi sentimen pasar mudah terganggu.
Fundamental kadang tampak cukup, tetapi kepercayaan tidak pernah permanen. Dan seperti kata-kata lama yang selalu terbukti, dalam pasar uang, orang tak sekadar membaca data. Orang juga membaca arah angin.
Itulah yang membuat Rp 17.000 terasa bukan sekadar angka. Ia seperti tanda pada tembok yang menunjukkan permukaan air banjir: barangkali tahun lalu belum setinggi itu, barangkali ini baru.
Namun, ketika tanda itu terlampaui, orang mulai mengangkat barang ke tempat lebih tinggi. Mulai menutup pintu, mulai menyiapkan hal-hal yang tak ingin disiapkan.
Kurs rupiah adalah berita yang tak menunggu redaktur. Ia muncul setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit.
Dan setiap menit itu bisa merembes ke dalam kehidupan orang yang tak pernah memikirkan “indikator”. Barangkali itulah ironi terbesar ekonomi modern: angka yang terlihat kecil pada layar bisa menjadi besar dalam nasib.
Namun, setiap pelemahan selalu membawa godaan lama: panik, menyalahkan, lalu berharap pasar segera “kembali normal”. Padahal pasar jarang kembali; ia hanya berpindah ke kebiasaan baru.
Maka pertanyaannya bukan semata bagaimana menguatkan rupiah besok pagi, melainkan bagaimana membuat ekonomi cukup tahan ketika rupiah tak lagi setangguh dulu.
Para ekonom makro sering mengingatkan bahwa nilai tukar bukan tujuan akhir. Ia lebih mirip termometer: menandai panas, bukan menyembuhkan demam.
Joseph Stiglitz pernah menulis bahwa stabilitas makroekonomi tidak lahir dari satu instrumen, melainkan dari orkestrasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil (Stiglitz, 2010).
Kurs yang stabil, dalam pandangannya, adalah hasil, bukan sasaran tunggal. Terlalu memuja nilai tukar justru membuat kebijakan kehilangan arah.
Di Indonesia, arah itu kerap kembali ke dua kata yang terdengar membosankan, tapi menentukan: kepercayaan dan konsistensi.
Bank Indonesia, misalnya, masih memegang mandat menjaga stabilitas nilai tukar melalui bauran kebijakan—intervensi valas, pengelolaan likuiditas, hingga suku bunga (Bank Indonesia, 2025).
Namun seperti diingatkan ekonom makro Paul Krugman, suku bunga tinggi memang bisa menahan depresiasi, tetapi terlalu lama dipertahankan justru menekan pertumbuhan dan memperbesar risiko sosial (Krugman, 1999). Menjaga rupiah dengan mengorbankan lapangan kerja adalah kemenangan yang mahal.
Karena itu, Bhima Yudhistira kembali menekankan bahwa pelemahan rupiah tidak bisa dijawab hanya dengan instrumen moneter.
Penguatan sektor riil dan pengurangan ketergantungan impor menjadi kunci jangka menengah (Bhima Yudhistira/CELIOS, 2026).
Selama bahan baku, pangan, dan energi masih banyak bergantung pada luar negeri, setiap depresiasi akan selalu berubah menjadi inflasi impor.
Di tingkat fiskal, disiplin tetap menjadi kata kunci. Carmen Reinhart dan Kenneth Rogoff menunjukkan bahwa utang yang membengkak, terutama dalam mata uang asing, mempersempit ruang kebijakan saat krisis datang (Reinhart & Rogoff, 2009).
Dalam konteks Indonesia, menjaga defisit dan komposisi utang bukan sekadar kepatuhan angka, melainkan perlindungan terhadap generasi berikutnya.
Namun kebijakan, seketat apa pun, akan pincang tanpa komunikasi. Pasar, seperti publik, membaca isyarat.
Olivier Blanchard mengingatkan bahwa ekspektasi adalah variabel makro yang paling mudah rusak dan paling sulit dipulihkan (Blanchard, 2018).
Ketika pemerintah dan bank sentral berbicara dengan nada berbeda, pasar akan memilih untuk percaya pada ketidakpastian.
Maka jalan keluar bukan satu pintu. Ia adalah lorong panjang: konsistensi kebijakan moneter yang tidak reaktif, fiskal yang disiplin tapi tidak kering dari empati sosial, industrialisasi yang mengurangi impor strategis, dan komunikasi kebijakan yang jujur, bahkan ketika kabarnya tidak menyenangkan.
Barangkali di titik ini, kita bisa mendengarkan David Hume, filsuf ternama asal Skotlandia. Kepercayaan, katanya, bukan produk argumen sempurna, melainkan kebiasaan yang terus dipelihara.
Rupiah pun demikian. Ia menguat bukan hanya karena intervensi hari ini, melainkan karena kepercayaan bahwa besok kebijakan masih masuk akal.
Rp 17.000, dengan demikian, bukan vonis. Ia lebih mirip peringatan yang ditulis kecil di pinggir halaman: bahwa ekonomi tak bisa hidup dari harapan saja.
Ia butuh kerja yang berulang, keputusan yang konsisten, dan keberanian untuk menunda kesenangan jangka pendek.
Jika tidak, maka kita akan tetap menyebutnya gerimis, dan baru mengerti ketika hujan itu ternyata sudah lama hadir.
Kamis itu, rupiah melemah, dolar menguat, dan kita kembali diingatkan bahwa negara pun bisa diuji bukan hanya oleh perang. Bukan hanya oleh bencana, melainkan oleh sesuatu yang tampak sederhana: nilai tukar.
Selebihnya adalah cerita yang selalu sama: kurs bergerak, harga mengikuti, daya beli mengempis, lalu politik mulai berbicara dengan suara yang lebih keras.
Namun, seperti yang kita pelajari dari sejarah uang, suara keras pun tak selalu mampu mengubah sesuatu yang paling menentukan: kepercayaan.
Dan kepercayaan, seperti rupiah di hadapan dollar, kadang melemah tanpa terdengar.
Tag: #17000 #dollar #harga #kepercayaan