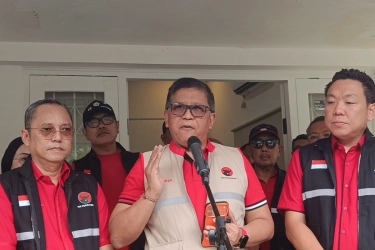Tinta Merah Megawati dan Kenegarawan Hakim Konstitusi
PADA 8 April 2024 lalu, Megawati Soekarnoputri menulis pesan dalam artikel opininya di Harian Kompas berjudul “Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi”.
Proses kreatif penulisan artikel opini itu berawal dari guratan tulisan tangan Megawati menggunakan tinta merah pada berlembar-lembar kertas sebelum diserahkan ke Redaksi Harian Kompas dan kemudian diterbitkan.
Ada pun kapasitas Megawati dalam artikel opini tersebut bukan Presiden ke-5 Republik Indonesia atau Ketua Umum PDI Perjuangan, tapi disampaikan sebagai seorang warga negara Indonesia.
Hal ini jelas bukan sekadar penanda kerendahan hati dari seorang Megawati, namun secara filosofi 9 (sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan representasi kurang lebih 280 juta warga Indonesia yang bertanggungjawab pada terciptanya keadilan substantif dan menempatkan kepentingan bangsa menjadi yang utama.
Pemaknaan dari tinta merah yang digunakan Megawati adalah ekspresi suara hati, kerisauan, pengalaman panjang dan keprihatinan melihat kondisi demokrasi di Indonesia dewasa ini.
Selain itu, tinta merah Megawati tersebut secara semiotik menegaskan dirinya selalu merasa terpanggil dalam setiap kegentingan dalam menyelamatkan konstitusi dan demokrasi agar tidak semakin parah.
Tulisan Megawati itu juga bukanlah bagian dari langkahnya untuk memengaruhi putusan hakim MK jelang pengumuman hasil sengketa Pilpres 2024, tapi seruan moral dalam memastikan tegaknya keadilan.
Baca juga: Menyerahkan Hakim Konstitusi ke DPR
Pasalnya, jika merunut seluruh isi dalam artikel opini yang ditulis oleh Megawati, dua kata yang paling dominan adalah etika dan moral.
Etika maupun moral selalu diukur dari baik atau buruk serta keduanya membutuhkan konsistensi.
Pedomannya berakar dari Pancasila dan UUD 1945 yang seutuh-utuhnya harus bisa diterapkan dalam peradilan MK.
Pada kalimat dalam paragraf akhir artikel opini tersebut, Megawati menutup tulisan dengan menawarkan diri sebagai Amicus Curiae atau sahabat peradilan.
Kenegarawan hakim Mahkamah Konstitusi
Pembentukan MK dilandaskan pada amandemen ke-3 UUD 1945 tahun 2001 yang secara implisit mengamanatkan pembentukan lembaga baru dalam memperkuat prinsip checks and balances pemerintahan dan tegaknya konstitusi.
Perintah itu kemudian aplikasikan oleh Presiden Megawati melalui pelembagaan hukum dan demokrasi dengan keterlibatan secara utuh tidak hanya dalam mendirikan MK di tahun 2003, tapi juga mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2002, Komisi Yudisial (KY) di tahun 2004 dan pelaksanaan Pilpres langsung pertama di Indonesia tahun 2004.
Berangkat dari kedudukan Pancasila sebagai norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm) serta sumber dari segala sumber hukum, keadilan itu ditempatkan secara ideologis.
Ada pun keadilan dalam perspektif ideologis itu dijabarkan dalam supremasi hukum. Pada konteks ini, sumpah seorang presiden dan hakim konstitusi merupakan bagian dari supremasi hukum.
Namun bagi hakim MK, sumpah dan tanggungjawabnya lebih dalam daripada sumpah seorang presiden.
Dasarnya sumpah hakim MK tidak hanya mengharuskan mereka menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya sesuai dengan UUD 1945, tapi ditambahkan syarat lainnya, yaitu memiliki sikap kenegarawan.
Sikap kenegarawan ini dimaknai tidak sekadar seorang hakim MK harus mampu menghapal serta memaknai pasal per pasal teks dalam konstitusi serta mampu menerjemahkan pengaplikasiannya dalam tata kelola pemerintahan di eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Lebih jauh, kenegarawan hakim MK ini merupakan perpaduan ideal antara kecerdasaan intelektual, kematangan emosi serta keteguhan sikap dalam mengambil keputusan secara adil dan bijaksana.
Baca juga: Senjakala Independensi Yudisial: Menggugat Politik Suka-suka DPR
Juga sikap kenegarawan hakim MK selalu menuntut agar setiap putusan dilandaskan pada etika dan moral yang didedikasikan sepenuhnya untuk tanah air.
Itu sebabnya, setiap putusan yang lahir dari palu hakim MK menjadi indikator dalam melihat kualitas demokrasi di Indonesia.
Apakah putusannya itu dilandaskan pada prinsip meneguhkan kedaulatan rakyat atau sekadar perpanjangan tangan dari kepentingan elit kekuasaan.
Indepedensi Hakim MK
Terpilihnya seorang politisi menjadi hakim MK mungkin tidak melanggar aturan karena belum ada pasal perundang-undangan yang membatasinya. Namun, hal ini menjadi anomali ketika syarat menjadi seorang hakim MK harus memiliki sikap kenegarawan.
Konsekuensi dari segi dimensi tanggungjawab etika dan moral juga tidak mudah karena posisi MK sebagai benteng konstitusi tidak boleh tercederai oleh konflik kepentingan apa pun.
Alasannya secara teknis, MK memiliki kewenangan dalam mengkoreksi produk undang-undang yang disahkan presiden dan DPR dengan mengujinya dengan UUD 1945.
Kewenangan lain dari MK adalah sebagai lembaga terakhir dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), baik Pilpres, Pileg hingga Pilkada yang sifatnya final dan mengikat yang memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan partai politik sebagai pihak terkait berperkara.
Terlepas dari ke depan hakim MK yang berlatar berlakang politisi tersebut memang bisa memutus perkara secara adil dan bijaksana.
Namun, potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan politiknya dan kelompoknya patut mendapatkan rasa curiga dan skeptis dari masyarakat sejak dini.
Hal ini sangat wajar mengingat politisi yang baru ditetapkan oleh DPR tersebut sudah puluhan tahun mengabdi di partai.
Ia juga telah mendapatkan kenyamanan, fasilitas dan kedudukan terhormat di DPR yang berasal dari rekomendasi partai.
Baca juga: Independensi MK dalam Bayang-bayang Konsolidasi Elite Politik
Kondisi semacam ini jelas punya tingkat sensitifitas tinggi terhadap hadirnya konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan MK di kemudian hari.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sangat kontoversial mungkin menjadi contoh paling aktual sekaligus pembelajaran berharga terkait pentingnya independensi pada setiap Hakim MK.
Pun setelah putusan tersebut keluar, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 menyebutkan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik dengan keterlibatannya dalam memutus Perkara 90 serta membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengambilan keputusan.
Tentu pada titik ini, kita tidak ingin persoalan sama yang menyangkut pelanggaran etik oleh hakim konstitusi hadir kembali mewarnai pengambilan putusan di MK.
Pun secara abstrak dalam setiap pengambilan putusan di MK tidak sekadar pertimbangan kuantitatif berdasarkan angka statistik yang tertulis di atas kertas.
Jauh daripada itu, konstruksi pengambilan putusan hakim MK ke depan harus pula dilakukan secara jernih, imparsial dan berpihak pada alam pikiran kebenaran.
Tag: #tinta #merah #megawati #kenegarawan #hakim #konstitusi