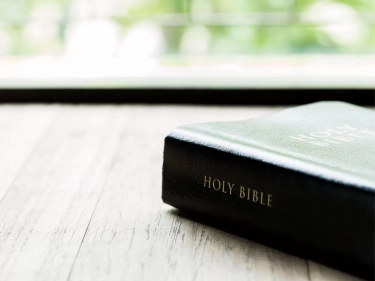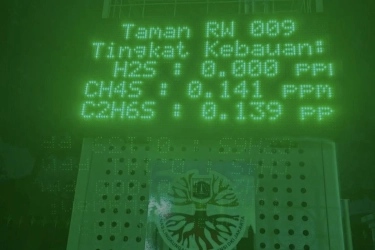OTT KPK dan Kegagalan Pendidikan Politik Parpol
TIDAK ada yang keliru dari Operasi Tangkap Tangan. Yang patut dipertanyakan justru mengapa demokrasi kita seolah terus-menerus membutuhkannya.
Ketika OTT menjadi rutin, ada mandat yang gagal dijalankan—yakni pendidikan politik oleh partai politik.
Operasi Tangkap Tangan sejatinya bukanlah instrumen pendidikan politik, melainkan mekanisme korektif terakhir yang bekerja setelah penyalahgunaan kekuasaan terjadi.
Dalam demokrasi yang sehat, fungsi pencegahan semestinya dijalankan jauh sebelum hukum bekerja—melalui proses kaderisasi, internalisasi nilai, dan pembentukan etika kekuasaan oleh partai politik.
Ketika fungsi ini absen atau gagal dijalankan, hukum dipaksa mengambil peran yang tidak pernah dimaksudkan untuknya.
Di sinilah persoalan mendasar itu mengemuka. Partai politik, sebagai institusi utama demokrasi perwakilan, memikul mandat strategis yang jauh melampaui sekadar memenangkan pemilu.
Ia seharusnya menjadi ruang pembelajaran politik warga, tempat nilai-nilai etika kekuasaan ditanamkan, dan arena pembentukan kepemimpinan publik yang bertanggung jawab. Namun dalam praktik politik kontemporer, mandat tersebut kian terpinggirkan.
Pendidikan politik yang dikosongkan maknanya
Secara normatif, pendidikan politik merupakan jantung dari fungsi partai politik dan fondasi etis dari demokrasi perwakilan.
Melalui pendidikan politik, partai diharapkan membentuk kesadaran warga dan kader tentang makna kekuasaan sebagai amanat publik, batas-batas kewenangan yang sah, serta tanggung jawab moral yang melekat pada setiap jabatan politik.
Pendidikan politik, dengan demikian, tidak berhenti pada transfer pengetahuan prosedural tentang pemilu atau sistem pemerintahan, melainkan merupakan proses pembentukan orientasi nilai, sikap, dan etika kekuasaan yang berlangsung secara berkelanjutan.
Dalam kerangka tersebut, pendidikan politik seharusnya menjadi ruang internalisasi prinsip-prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan pengabdian kepada kepentingan umum.
Ia menuntut konsistensi dalam kaderisasi, keteladanan elite partai, serta mekanisme disiplin internal yang menempatkan etika sebagai prasyarat utama kepemimpinan.
Tanpa proses ini, partai kehilangan fungsi pedagogisnya dan hanya menyisakan peran elektoral semata.
Namun, dalam praktik politik kontemporer, pendidikan politik kerap direduksi menjadi aktivitas mobilisasi elektoral yang pragmatis.
Kegiatan sosialisasi partai lebih banyak diarahkan untuk memenangkan suara, membangun loyalitas jangka pendek, dan memperkuat identitas simbolik menjelang kontestasi.
Kaderisasi pun sering dipahami sebagai proses teknis untuk menyiapkan operator politik yang efektif, bukan pembentukan pemimpin publik yang memiliki integritas dan kesadaran etis.
Reduksi ini membawa konsekuensi yang tidak sederhana. Ketika pendidikan politik berhenti pada logika kemenangan elektoral, kekuasaan kehilangan dimensi etiknya dan tereduksi menjadi sekadar instrumen.
Jabatan publik kemudian dipersepsikan sebagai hasil investasi politik yang harus dikembalikan, bukan amanat yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan.
Dalam kerangka berpikir seperti ini, penyalahgunaan kekuasaan tidak lagi dipahami sebagai penyimpangan moral yang serius, melainkan sebagai risiko yang dianggap inheren dan nyaris wajar dalam praktik politik.
OTT cermin kegagalan institusional
Maraknya OTT terhadap politisi seharusnya dibaca sebagai indikator kegagalan institusional, bukan semata-mata deviasi individu.
Politisi yang tertangkap bukanlah aktor yang muncul dari ruang hampa; mereka merupakan produk dari sistem rekrutmen, kaderisasi, dan pendidikan politik yang dirancang serta dijalankan oleh partai politik.
Ketika pola penangkapan berulang terjadi pada kader dari berbagai partai dan dalam lintas jabatan publik, persoalan yang mengemuka tidak lagi dapat direduksi pada soal integritas personal semata.
Yang patut dipertanyakan adalah kualitas sistem politik yang secara berulang melahirkan aktor dengan pola penyimpangan serupa.
Pada titik inilah keberhasilan penegakan hukum justru menyingkap kegagalan politik dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pembinaan etika kekuasaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja pada tahap akhir dari rantai penyimpangan, ketika pelanggaran telah terjadi dan kerusakan telah nyata, sementara akar persoalan sesungguhnya terletak jauh di hulu proses politik.
Ironisnya, temuan berulang ini jarang dijadikan momentum refleksi kelembagaan oleh partai politik. Alih-alih meninjau ulang pola kaderisasi, mekanisme seleksi, dan disiplin internal, respons yang muncul kerap berhenti pada pernyataan normatif tentang penghormatan terhadap proses hukum.
Pelaku kemudian dilabeli sebagai “oknum”, seolah tindakannya sepenuhnya terpisah dari ekosistem internal partai.
Bahasa semacam ini tidak hanya menyederhanakan persoalan, tetapi juga secara efektif menghapus tanggung jawab kolektif dan menutup ruang evaluasi struktural yang semestinya menjadi konsekuensi politik dari setiap kasus korupsi.
Penggunaan istilah “oknum” dalam merespons kasus korupsi sesungguhnya memiliki implikasi politik yang serius. Ia bukan sekadar pilihan kata, melainkan strategi simbolik untuk membatasi tanggung jawab.
Dengan menyederhanakan persoalan menjadi kesalahan individu, partai politik dapat menghindari tuntutan reformasi internal yang lebih mendasar.
Padahal, dalam demokrasi perwakilan, tanggung jawab politik bersifat institusional. Partai tidak hanya bertanggung jawab mengusung calon, tetapi juga memastikan bahwa calon tersebut dibekali orientasi etika dan kesadaran tanggung jawab publik.
Tanpa mekanisme akuntabilitas internal yang kuat, partai akan terus memproduksi kader dengan pola yang sama.
Selama pendidikan politik tidak dikembalikan sebagai mandat utama partai politik, Operasi Tangkap Tangan akan terus hadir sebagai mekanisme korektif yang bekerja di hilir.
Ia mungkin membersihkan satu kasus, tetapi tidak pernah menyentuh sumber persoalan.
Demokrasi pun berisiko terjebak dalam siklus penindakan tanpa pembelajaran, di mana hukum terus bekerja keras menutup lubang yang seharusnya tidak pernah ada sejak awal.