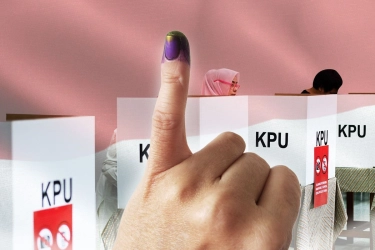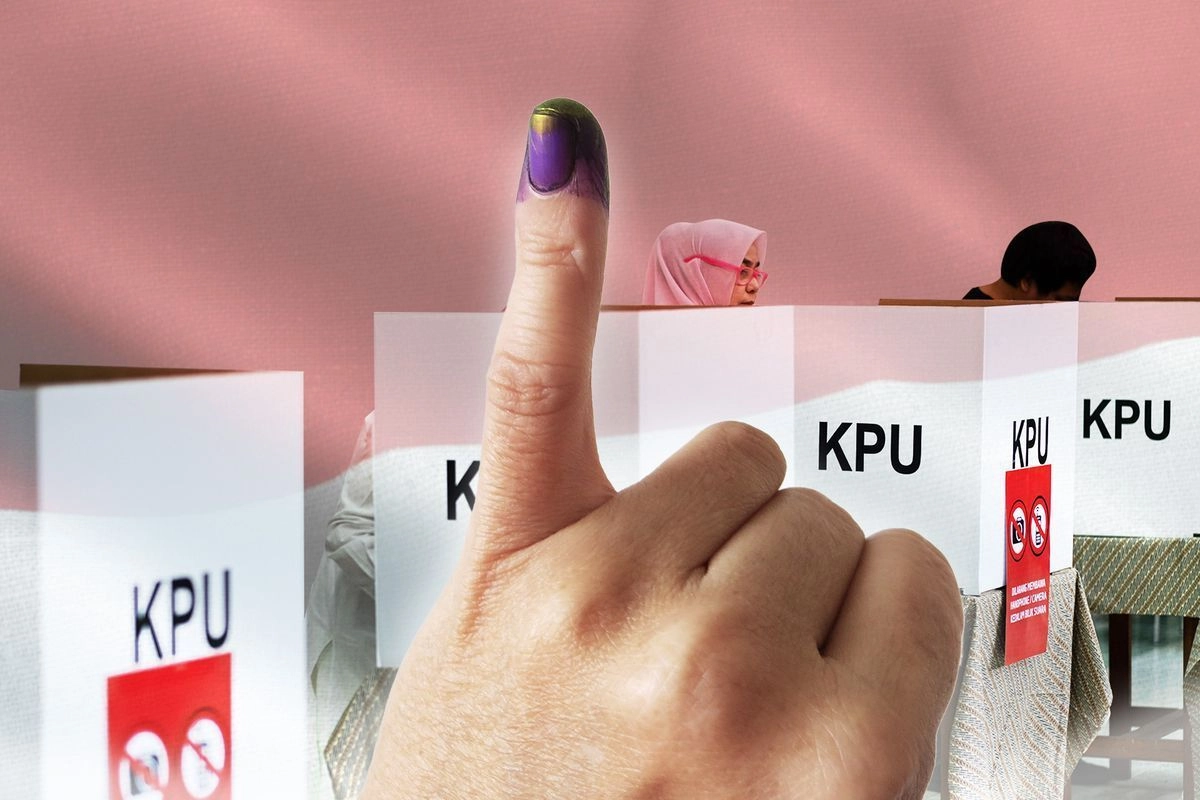
Mayoritas Responden Lembaga Survei Tolak Pilkada Lewat DPRD, Apa Penyebabnya?
- Wacana kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD mendapat penolakan oleh mayoritas responden lembaga survei.
Hasil ini pertama datang dari Survei Litbang Kompas pada Januari 2025 yang diterbitkan pada Kompas.id, 3 Februari 2025.
Survei ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 4-10 Januari 2025.
Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.
Metode ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian lebih kurang 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana, dan dibiayai penuh oleh harian Kompas.
Hasil surveinya penolakan wacana ini cukup kuat, bahkan setahun lalu.
Namun, wacana ini justru menguat di tataran elite, termasuk dukungan partai politik yang datang satu per satu.
Pada survei Januari 2025 ini, Litbang Kompas menyebut masyarakat memiliki kecenderungan tidak sepakat atas wacana yang digulirkan pemerintah dan DPR ini.
Pada tingkat pemerintahan kabupaten dan kota misalnya, ada 85,1 persen responden meminta agar kepala daerah tingkat II ini tetap dipilih langsung.
"Hanya 11,6 persen responden yang mengaku lebih setuju dipilih melalui mekanisme yang ada di DPRD kabupaten atau kota," tulis Litbang Kompas.
Penolakan wacana ini juga terjadi pada tingkat pemilihan gubernur.
Ada 83,5 persen responden masih menginginkan pemilihan langsung.
Kadar ketidaksetujuan masyarakat terhadap wacana ini paling tinggi terlihat pada tingkat pemerintah pusat.
Ada 91,6 persen responden mengaku lebih setuju dengan skema pemilihan langsung, 6 persen ingin presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh MPR.
Survei LSI Denny JA
Lembaga survei lainnya, LSI Denny JA juga turut memberikan hasil surveinya ke publik terkait wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan, survei ini dilakukan pada 10-19 Oktober 2025 melalui metodologi multi-stage random sampling.
Jumlah responden yang digunakan yakni 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data wawancara tatap muka menggunakan kuisioner.
Ia mengeklaim margin of error dalam penelitian ini lebih kurang 2,9 persen.
"Hasilnya 66,1 persen kurang setuju atau tidak setuju sama sekali (atau menolak pilkada dipilih DPRD)," kata dia.
Sedangkan 28,6 persen respondennya mengatakan setuju, dan 5,3 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu.
Dia mengatakan, angka penolakan ini tak bisa dianggap enteng, karena bisa berdampak secara sistemik.
Lembaga survei ini juga mengungkapkan, penolakan paling banyak berasal pada usia di bawah 27 tahun atau dikenal dengan Generasi Z (Gen-Z).
Ada 84 persen responden kategori Gen-Z yang menolak wacana ini, disusul Milenial 71,4 persen, Generasi X 60 persen, dan Baby Boomer 63 persen.
Mengapa mereka menolak?
Gelombang penolakan dari responden lembaga survei ini memiliki beragam alasan.
Dalam Litbang Kompas misalnya, di tingkat kabupaten/kota 59 persen responden berasalan pemilihan langsung adalah cara terbaik memilih pemimpin yang diinginkan masyarakat.
Alasan lain yang tinggi yakni sekitar 37 persen responden mendasari sikap mereka mendukung pemilihan langsung karena asas demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Alasan lainnya, semangat menjaga transparansi dan integritas.
Survei ini menyebut ada seperlima dari responden memilih pemilihan langsung karena dinilai lebih transparan.
Sedangkan temuan dari LSI Denny JA menyebut adanya memori kolektif yang dirasakan dalam 20 tahun terakhir sejak pilkada dipilih secara langsung.
Sebagian pemilih bahkan belum pernah mengetahui adanya pilkada dipilih secara perwakilan.
"Rakyat sudah terbiasa memilih langsung, ini adalah alasan pertama mengapa penolakan pilkada DPRD kuat," kata Ardian.
Kedua, penolakan pilkada terhadap DPRD didasari oleh ketidakpercayaan terhadap lembaga legislatif.
DPR dan DPRD konsisten masuk dalam kelompok institusi yang mendapat kepercayaan publik rendah dan sering diasosiasikan pada politik transaksional.
Selain itu ada juga persepsi korupsi lembaga legislatif yang masih tinggi.
Jejak politik uang
Politik transaksional dalam pilkada yang dipilih DPRD pernah terekam dalam laporan Harian Kompas.
Merujuk dua artikel Kompas berjudul "Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah: Anggota Dewan, Kiri-Kanan Oke" (14 Maret 2000) dan "Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah: Kejarlah Calon Gubernur, Uang Kutangkap" (15 Maret 2000), yang diulas kembali dalam liputan bertajuk "Jejak Politik Uang Saat Kepala Daerah Masih Dipilih oleh DPRD" politik uang terjadi saat pilkada melalui DPRD.
Praktik "biaya lain-lain yang merusak moral bangsa" itu digambarkan secara gamblang dalam pemilihan bupati Sukoharjo pada Januari 2000.
Saat itu, hampir semua bakal calon dilaporkan mengeluarkan dana besar untuk mengamankan dukungan fraksi.
Sejumlah kandidat disebut menghabiskan hingga Rp 500 juta hanya untuk tahap pencalonan.
Fenomena serupa muncul di Boyolali pada Februari 2000 ketika suara fraksi mayoritas DPRD justru berpindah dalam pemungutan suara.
Rumor yang beredar saat itu menyebutkan harga satu suara anggota DPRD berkisar Rp 50 juta hingga Rp 75 juta, disertai praktik "karantina" anggota dewan di rumah calon menjelang pemilihan.
Praktik transaksi politik lebih vulgar di Lampung Selatan, dalam proses pemilihan bupati periode 2000–2005, tim sukses calon bupati mendatangi rumah anggota DPRD, menginapkan mereka di hotel, dan memberikan uang tunai dengan nilai bervariasi.
Sejumlah anggota DPRD mengaku menerima uang antara Rp 10 juta hingga Rp 25 juta, bergantung pada posisi mereka sebagai anggota atau pimpinan fraksi.
Praktik politik uang tersebut merebak di berbagai daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Tag: #mayoritas #responden #lembaga #survei #tolak #pilkada #lewat #dprd #penyebabnya