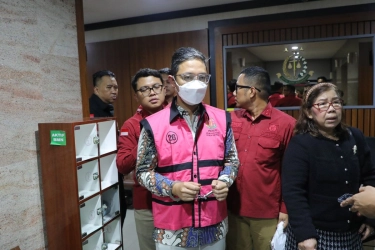Timpangnya Keadilan Hidrologi
SIAPA yang tidak terkejut ketika mengetahui bahwa klaim tentang air pegunungan yang murni ternyata bersumber dari air sumur bor. Itulah yang sempat menjadi inti polemik panas antara masyarakat Subang, Jawa Barat, dan salah satu perusahaan air minum kemasan.
Di balik label industri air minum dalam kemasan yang selama ini diasosiasikan dengan kemurnian dan kesehatan, tersimpan konflik laten antara korporasi, negara, dan masyarakat lokal dalam memaknai siapa yang sesungguhnya berhak atas air.
Dalam kerangka keadilan hidrologi, kasus itu menjadi contoh konkret dari komodifikasi air yang dikemas dalam bumbu-bumbu modernisasi, legalitas administratif, dan retorika pembangunan.
Secara historis dan filosofis, air merupakan commons atau sumber daya bersama yang keberadaannya melampaui hak kepemilikan privat.
Dalam hukum dasar Indonesia, Pasal 33 UUD 1945 ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Namun, dalam praktik, pasal tersebut justru mengalami distorsi kelembagaan yang cukup beralasan kita pertanyakan.
Negara tidak lagi menjadi pengelola langsung, melainkan bertindak sebagai regulator yang memberikan izin eksploitasi kepada pihak ketiga, termasuk korporasi multinasional.
Dalam konteks perusahaan tersebut, izin pengambilan air tanah dalam di Subang berdasar pada PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2021.
Legalitas ini sering dijadikan tameng administratif yang tidak selalu identik dengan keadilan ekologis.
Studi LaMoreaux dan Tanner (2001) dalam Springs and Bottled Waters of the World menunjukkan bahwa eksploitasi akuifer dalam oleh industri air kemasan didasarkan pada asumsi teknokratis bahwa akuifer dalam bersifat terisolasi dari kebutuhan masyarakat lokal sehingga sah untuk dikomersialisasi.
Asumsi ini bermasalah karena mengabaikan kompleksitas geohidrologi kawasan tropis seperti Indonesia, di mana hubungan antara akuifer dangkal dan dalam tidak bersifat linier.
Di Subang, masyarakat telah melaporkan sumur-sumur dangkal yang mengering dan debit mata air menurun.
Gejala ini menandakan bahwa pengambilan air dalam volume besar berpotensi mengganggu keseimbangan sistem air lokal.
Pendekatan berbasis izin administratif juga gagal menempatkan masyarakat sebagai subjek hak atas air.
Rutgerd Boelens dan koleganya (2018) dalam Water Justice menjelaskan bahwa konflik air bukan hanya tentang volume atau kuantitas, melainkan tentang siapa yang memiliki kuasa untuk mendefinisikan penggunaan yang sah.
Dalam kasus di Subang, klaim korporasi bahwa mereka mengambil air dari akuifer dalam dan bukan dari sumber masyarakat lokal menjadi justifikasi moral sekaligus teknis.
Dalam perspektif keadilan hidrologi, setiap bentuk ekstraksi yang dilakukan tanpa partisipasi komunitas terdampak serta tanpa mekanisme redistribusi manfaat yang adil tetaplah problematik.
Model tata kelola multilevel sebagaimana dijelaskan Finger, Tamiotti, dan Allouche (2006) dalam The Multi-Governance of Water semakin memperumit persoalan ini.
Pengaturan air kini berlangsung dalam arena yang bertumpuk antara nasional, regional, dan global.
Negara pusat menetapkan regulasi teknis sekaligus membuka ruang investasi.
Pemerintah daerah menjadi pelaksana kebijakan sekaligus mitra korporasi, sementara masyarakat lokal tersingkir dari arena pengambilan keputusan.
Di Subang, warga tidak pernah dilibatkan secara bermakna dalam evaluasi izin maupun dalam perumusan skema pembagian manfaat. Situasi ini menciptakan jurang ketidakpercayaan yang terus melebar.
Dalam ranah ekonomi politik, pendekatan neoliberal terhadap sumber daya air telah mengubah air dari hak publik menjadi komoditas.
Robert Brears (2021) dalam Water Resources Management: Innovative and Green Solutions menunjukkan bahwa model pengelolaan berbasis investasi swasta menciptakan akses eksklusif bagi mereka yang memiliki modal, sementara publik harus membeli kembali hak dasarnya dalam bentuk air kemasan.
Di Indonesia, pola ini terlihat dalam ekspansi industri air minum dalam kemasan yang agresif menyasar akuifer strategis di berbagai wilayah.
Perusahaan tersebut mendominasi dengan memiliki puluhan titik ekstraksi di seluruh nusantara, tetapi kontribusi fiskalnya terhadap daerah penghasil sering kali tidak sebanding dengan nilai ekonomi air yang diambil maupun biaya ekologis yang ditanggung masyarakat lokal.
Realitas itu juga menjadi isu terhadap produsen air kemasan lainnya yang marak di tanah air.
Masalah ini bukan hanya terletak pada model bisnis, tetapi juga pada kerangka kebijakan yang memungkinkan sistem ekstraksi semacam itu berjalan tanpa koreksi struktural.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air memang mengakui hak masyarakat untuk mendapatkan air dalam jumlah dan mutu yang memadai. Namun, implementasinya jelas sangat bergantung pada kemauan politik dan kapasitas institusi daerah.
Sebagian besar pemerintah daerah tidak memiliki instrumen pemantauan dan mekanisme transparansi dalam pelaporan volume ekstraksi maupun dampaknya terhadap cadangan air tanah.
Ketika perusahaan menyatakan telah mematuhi seluruh regulasi, hal itu benar secara administratif, tetapi tidak selalu adil secara substantif.
Lebih jauh, legalitas eksploitasi besar-besaran sering dibungkus dengan narasi tanggung jawab sosial perusahaan. Pembangunan sarana air bersih, kegiatan penghijauan, dan dukungan pendidikan menjadi instrumen legitimasi yang efektif.
Namun, sebagaimana dikemukakan Boelens (2018), pendekatan filantropik semacam ini tidak mengubah struktur relasi kuasa. CSR hanya berfungsi sebagai penutup luka, bukan benar-benar menyasar akar ketimpangan.
Ketimpangan itu bersumber dari penyingkiran masyarakat sebagai pemilik sah pengetahuan dan pengalaman atas sumber air. Dalam pandangan masyarakat adat dan pedesaan, air bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan bagian dari tatanan ekologi, identitas dan spiritual.
Kebijakan air yang dilandasi logika teknokratis menyingkirkan dimensi ini. Perizinan lebih mengutamakan kepatuhan administratif ketimbang keadilan intergenerasional.
Akibatnya, masyarakat kehilangan hak dan suara atas sumber daya yang menopang kehidupan mereka.
Secara global, kasus di Subang merefleksikan pola umum dari praktik water grabbing, yaitu pengambilalihan sumber air oleh entitas kuat, baik negara maupun korporasi dengan mengabaikan hak masyarakat lokal.
Seemann (2014) menyebut praktik ini sebagai bentuk kolonialisme sumber daya. Dalam situasi seperti ini, masyarakat hanya dapat mengandalkan aksi kolektif dan gerakan sosial sebagai upaya memperjuangkan keadilan.
Ujungnya, gelombang protes menjadi manifestasi dari kesadaran baru atas ketimpangan struktural tersebut. Namun, gerakan rakyat menuntut keadilan sering kali lemah secara politik dan hukum.
Pemerintah daerah terjebak dalam dilema antara kebutuhan pendapatan dan perlindungan hak publik, sementara pemerintah pusat lebih fokus menciptakan iklim investasi yang menguntungkan bagi pelaku industri.
Untuk merestorasi keadilan hidrologi, diperlukan rekonstruksi tata kelola air berbasis hak asasi, keberlanjutan ekologis, dan demokrasi partisipatif.
Izin pengambilan air harus dikaji ulang dengan melibatkan masyarakat terdampak secara substantif.
Skema redistribusi manfaat harus diperjelas dan dijalankan secara transparan, termasuk pungutan daerah berbasis volume ekstraksi dan audit independen atas dampak lingkungan.
Perlu disadari oleh pemerintah bahwa air bukanlah komoditas yang dapat dibotolkan tanpa konsekuensi sosial. Ia adalah jantung kehidupan dan simbol keterhubungan manusia dengan alam.
Jika negara membiarkan komodifikasi air terus berjalan atas nama pertumbuhan ekonomi, maka negara tidak lagi menjadi pelindung rakyat, melainkan fasilitator ekstraksi.
Kasus di Subang menjadi cermin untuk menilai ulang arah kebijakan air nasional. Sebab di balik setiap botol air terdapat kisah tentang siapa yang kehilangan haknya agar orang lain dapat membeli kemurnian dalam kemasan.
Konflik antara masyarakat dan perusahaan air minum dalam kemasan mencerminkan ketegangan antara tata kelola berbasis ekstraksi dan gagasan keadilan ekologis.
Ketika perusahaan menyatakan bahwa air diambil dari akuifer dalam dan tidak bersaing dengan kebutuhan warga, pernyataan itu tidak sepenuhnya menjawab keresahan.
Dalam pandangan masyarakat, sistem hidrologi bersifat saling terhubung. Tekanan di satu titik menciptakan defisit di titik lain.
Finger, Allouche, dan Tamiotti (2006) menjelaskan bahwa dalam sistem multi-level governance, korporasi sering memanfaatkan celah kelembagaan ketika pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh dan pemerintah pusat menyerahkan regulasi kepada swasta atas nama efisiensi.
Dalam kondisi itu, tanggung jawab menjadi kabur. Masyarakat hanya melihat sumur mereka mengering, sementara produksi air kemasan terus berjalan.
Hukum formal pun tidak selalu menjamin keadilan substantif. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan air sebagai cabang produksi yang harus dikuasai negara demi kemakmuran rakyat, tetapi regulasi turunannya justru membuka ruang konsesi bagi swasta. Negara berubah dari pengelola menjadi fasilitator bagi kepentingan ekonomi.
Zwarteveen (2011) melalui konsep hydrosocial territories menunjukkan bahwa air bukanlah entitas netral, melainkan ruang kontestasi sosial.
Ketika satu kelompok memperoleh keuntungan sementara kelompok lain kehilangan akses, yang terjadi bukan hanya ketimpangan ekologis, tetapi juga eksklusi politik.
Air dengan demikian menjadi arena perebutan kekuasaan, di mana relasi antara manusia, teknologi, dan alam membentuk ulang siapa yang berhak atas sumber daya tersebut.
Dalam konteks ini, muncul pertanyaan, bagaimana mungkin kita berbicara tentang kemajuan jika teknologi yang lebih adil dan berkelanjutan belum menjadi bagian dari sistem kita?
Dhara et al. (2023) menjelaskan bahwa pengolahan air limbah berbasis proses biologis anaerobic digestion mampu mengubah limbah cair menjadi sumber energi baru.
Melalui mekanisme ini, air limbah tidak hanya dibersihkan, tetapi juga dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas sebagai sumber listrik, sekaligus memulihkan unsur fosfor, nitrogen, dan logam berat.
Pendekatan semacam ini mencerminkan prinsip ekonomi regeneratif, di mana sirkularitas dan efisiensi sumber daya menjadi fondasi pengelolaan lingkungan.
Beberapa kota seperti Aarhus di Denmark, Yokohama di Jepang, dan Amsterdam di Belanda telah menunjukkan keberhasilan transformasi ini.
Instalasi pengolahan air limbah di sana tidak lagi sekadar mengurangi polusi, tetapi berfungsi sebagai pusat energi lokal yang memperkuat ketahanan kota.
Paradigma mereka telah bergeser dari eksploitasi menuju restorasi. Air tidak lagi dipandang sebagai input industri yang bisa diambil dan dihabiskan, melainkan sebagai bagian dari siklus ekologis yang harus dijaga dan terus diperbarui.
Sayangnya, integrasi semacam ini belum menjadi kenyataan di Indonesia. Instalasi pengolahan air limbah di berbagai kota masih beroperasi secara konvensional—hanya menurunkan kadar pencemaran tanpa mengubahnya menjadi sumber energi.
Padahal, integrasi antara sektor air, energi, dan pertanian berpotensi besar mengurangi tekanan terhadap air tanah sekaligus menekan ketergantungan pada energi fosil.
Sistem ini tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga relevan secara sosial karena menciptakan model tata kelola sumber daya yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Konflik air yang berulang di berbagai daerah—seperti di Klaten, Sukabumi, dan Pandaan—seharusnya menjadi cermin bagi negara untuk meninjau ulang kebijakan pengelolaan air.
Keadilan hidrologi tidak dapat dicapai hanya dengan menegakkan kepatuhan administratif. Ia menuntut keberanian politik untuk membangun visi keberlanjutan yang berpihak pada hak masyarakat atas air.
Negara seharusnya kembali berperan sebagai penjaga ekosistem, bukan semata regulator bagi kepentingan bisnis.
Jika paradigma ini diperluas, isu eksploitasi air tidak lagi menjadi pertarungan antara industri dan masyarakat, tetapi menjadi bagian dari transformasi menuju sistem air regeneratif.
Inovasi teknologi, reformasi kebijakan, dan partisipasi publik harus berjalan beriringan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem air.
Masa depan air Indonesia bergantung pada keberanian untuk memilih, apakah tetap bertahan dengan paradigma ekstraktif yang memperlakukan air seperti tambang, atau membangun tata kelola baru yang adil, regeneratif, dan berpihak pada seluruh kehidupan.