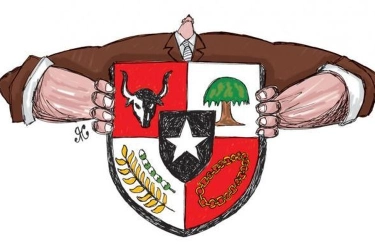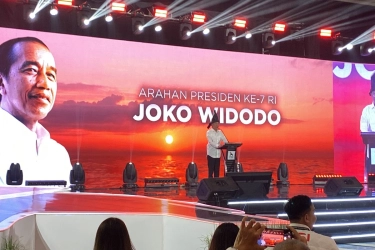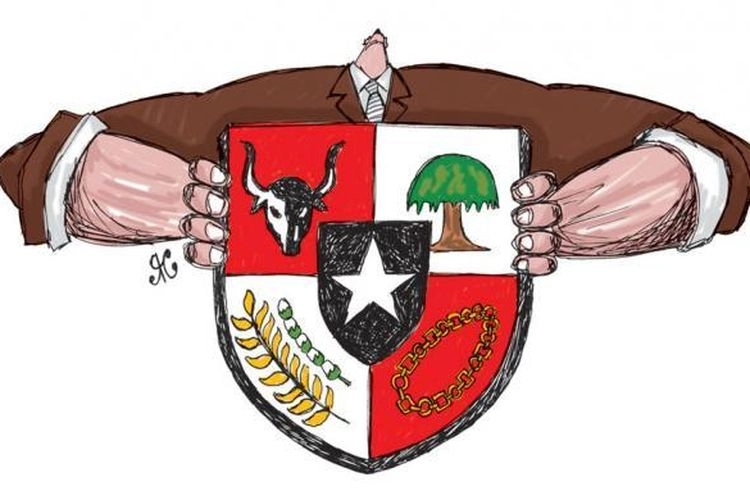
Mem-Pancasila-kan Diplomasi, Mendiplomasikan Pancasila
DALAM acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) pada 10 Januari lalu, Menlu Sugiono menegaskan, diplomasi Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, dengan Asta Cita sebagai panduan strategis.
Sepertinya baru kali ini seorang Menlu secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa Pancasila dijadikan dasar dan pedoman pelaksanaan diplomasi. Sikap politik yang layak diapresiasi.
Bahwa Asta Cita - visi capres Prabowo dalam kampanye Pilpres 2024 - dijadikan panduan strategis, itu adalah keniscayaan. Sebab di dalam Asta Cita “memperkokoh ideologi Pancasila” menjadi prioritas pertama.
Alur logikanya jelas: karena prioritas pertama Asta Cita adalah memperkokoh Pancasila, maka kebijakan luar negeri dan diplomasi harus mempedomani nilai-nilai Pancasila.
Justru yang kemudian menjadi pertanyaan: bagaimana memahami Pancasila sebagai dasar dan pedoman diplomasi, baik dalam tataran nilai dan kebijakan maupun dalam praksisnya?
Di dalam Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pancasila dimaknai dalam tiga dimensi: sebagai falsafah, dasar dan ideologi negara.
Sebagai falsafah, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang berisi nilai luhur dan dijadikan pedoman dalam hal sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam prikehidupan sehari-hari.
Sebagai dasar negara, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sedangkan sebagai ideologi negara, Pancasila dimaknai sebagai sekumpulan nilai, gagasan, keyakinan, dan cita-cita yang menjadi arah dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Manakala Menlu Sugiono menegaskan Pancasila sebagai landasan diplomasi, serta merta muncul pertanyaan: seberapa pentingkah ideologi dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri?
Dalam perspektif ideologi sebagai seperangkat ide, gagasan dan cita-cita, Pancasila harus menjadi inspirasi semua langkah diplomasi dan kebijakan luar negeri dalam memperjuangkan kepentingan nasional.
Diplomasi mengikuti sabda ideologi. Manakala Menlu Sugiono menyatakan diplomasi Indonesia berlandaskan Pancasila, itu artinya nilai Pancasila harus menjadi “bintang penuntun” dalam penetapan kebijakan luar negeri.
Tatkala nilai Pancasila direfleksikan ke dalam langkah diplomasi dan kebijakan luar negeri, itu artinya Kemlu “mem-Pancasilakan diplomasi”.
Namun, bagaimana benar wujudnya jika Pancasila direflkesikan ke dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri?
Terkait relasi fungsional antara ideologi dan kebijakan luar negeri, pakar hubungan internasional memetakan fungsi ideologi dalam dua lanskap utama: pertama, sebagai “pedoman nilai” untuk memaknai dan mengukur setiap fenomena politik internasional. Kedua, sebagai “instrumen” untuk melakukan tindakan politik terhadap fenomena itu (Sylvan & Majeski, Ideology and Intervention, 2008).
Pertama, sebagai pedoman ideal dalam bersikap dan bertindak terhadap isu-isu regional dan global.
Ketika pertama kali memperkenalkan Pancasila di Sidang Umum PBB, New York, 30 September 1960 melalui pidatonya berjudul To Build the World Anew, Bung Karno merumuskan nilai-nilai Pancasila dengan ketuhanan, kemanusiaan/internasionalisme, persatuan/nasionalisme, demokrasi dan keadilan.
Bung Karno menawarkan Pancasila sebagai nilai yang mendamaikan dan menyatukan dua ideologi dunia yang bersaing kala itu.
Bukan sebagai jalan tengah, tapi “jalan ketiga” yang memuat nilai-nilai pemersatu terhadap dua ideologi yang berseteru. Watak pemersatu dalam Pancasila itulah sebenarnya ruh nasionalisme/persatuan Indonesia.
Bagaimana aktualisasi nilai nasionalisme ini dalam laku diplomasi Indonesia?
Sekedar kilas balik, dalam wacana nasionalisme Indonesia, Bung Karno menggunakan terma “sosio-nasionalisme” (Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I, 2015).
Embrio nasionalisme Bung Karno berurat akar pada anti-kolonialisme. Namun, itu tidak berarti Indonesia mengisolasi diri dari pergaulan internasional.
Bagaimana relasi nasionalisme dan internasionalisme ini, Bung Karno dengan apik menggunakan metafora: “nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sari internasionalisme; dan internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar dalam bumi nasionalisme”.
Dalam dimensi praksis, ini artinya nasionalisme Indonesia diletakkan dalam bingkai ”sosial kemanusiaan”, yaitu nasionalisme berdimensi kemanusiaan, kewajiban moral seperti dititahkan sila kedua (kemanusiaan/internasionalisme) dan ketiga (persatuan/nasionalisme) Pancasila.
Senapas dengan sabda kedua sila ini, manakala Indonesia ingin berperan dalam penyelesaian konflik regional Rusia-Ukraina atau konflik internal berlatar etnik di Myanmar, misalnya, itu adalah panggilan yang menggema dari dalam nurani bangsa.
Watak diplomasi Indonesia dalam pergaulan internasional seperti itu terlanjur dikenal sebagai “bridge builder”, menghubungkan pihak yang berseberangan.
Watak pemersatu seperti itu adalah ruh sosio-nasionalisme Pancasila: mendekatkan yang terbelah, mempersatukan yang terpisah.
Jika watak bridge-builder dan pemersatu terefleksi dalam kiprah pergaulan internasional Indonesia, maka sejatinya Kemlu telah memPancasilakan diplomasi dan kebijakan luar negeri.
Kedua, Pancasila dapat digunakan sebagai “instrumen” dalam diplomasi Indonesia di pergaulan internasional.
Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO-PBB) pada Mei 2023 telah menganugerahi pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB berjudul ”To Build the World Anew” 1960 sebagai Warisan Arsip Dunia (Memory of the World).
Anugerah Memory of the World untuk Pancasila sejatinya adalah “asset for diplomacy” bagi Indonesia.
Dengan status itu, publik internasional bisa mempelajari arsip teks pidato Pancasila untuk pengembangan studi terkait pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Arsip pidato tentang Pancasila sudah menjadi milik dunia.
Lantas, bagaimana mengkapitalisasi dokumen sejarah tentang Pancasila itu untuk kepentingan diplomasi Indonesia?
Pada titik inilah sebenarnya Kemlu punya kesempatan untuk mendiplomasikan Pancasila. Diplomasi tidak saja terbatas pada mempromosikan ”benda”, tapi juga ”nilai”.
Tidak saja pada peluang ekonomi, tapi juga nilai yang tersimpul dalam Pancasila, yaitu nilai pemersatu. Nilai pemersatu Pancasila sudah teruji dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Berkat Pancasila-lah, meski menghadapi gonjang-ganjing politik nasional dan global, Indonesia tetap utuh sebagai bangsa dan negara hingga detik ini. Kekuatan nilai pemersatu dalam Pancasila ini yang harus dipromosikan dalam aktifitas diplomasi Indonesia.
Dalam beberapa dekade terakhir, setelah dunia tidak lagi dihantui ideologi Perang Dingin, sosial-budaya menjadi faktor penting dalam hubungan antarbangsa. Dengan berakhirnya Perang Dingin, faktor budaya tidak saja menjadi penting dalam hubungan antarbangsa, tetapi malah menjadi motor penggerak dalam peningkatan intensitas hubungan internasional (Michael J Mazarr, Culture in International Relations, Global Policy Forum, Spring 1996).
Pandangan Mazarr ini relevan dengan situasi dunia saat ini, di mana konflik berlatar politik-ideologis tergantikan oleh konflik sosial budaya, seperti konflik antaretnik, ras, dan agama.
Ketika kebencian berlatar sosial-budaya marak, maka dibutuhkan saling pengertian. Saling menghormati dan saling mengerti hanya akan tumbuh di masyarakat yang toleran dan moderat.
Toleran, moderat, dan menghargai perbedaan adalah DNA manusia Indonesia, yang telah berurat akar dalam perikehidupan leluhur ratusan tahun lamanya.
Karakter bangsa yang toleran, moderat, dan menghargai keberagaman itu terpatri dalam satu kesatuan nilai Pancasila.
Indonesia dengan Pancasila-nya memiliki kredensial atau kepercayaan sebagai bridge builder untuk ikut membantu negara sahabat yang dilanda konflik etnik dan agama.
Sebagai pedoman nilai, para diplomat harus mampu memPancasilakan diplomasi dan kebijakan luar negeri.
Sebagai instrumen, mereka pun harus mampu mendiplomasikan Pancasila dengan mempromosikan nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk membantu penyelesaian konflik di berbagai negara.