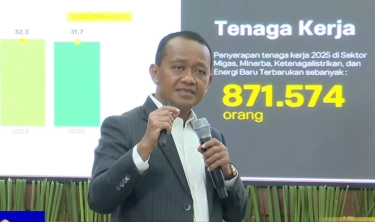Ketika Bahagia Tak Selalu Sejahtera
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia terdengar menenangkan di tengah kegelisahan ekonomi global.
Dalam pidatonya, Presiden mengaku terharu menyaksikan rakyat Indonesia yang hidup sederhana, tapi tetap mampu mengekspresikan kebahagiaan.
Narasi ini, sebagaimana disajikan media arus utama, seolah menawarkan jeda emosional dari berita tentang inflasi, ketimpangan, dan ketidakpastian masa depan.
Namun, justru di situlah letak persoalannya: kebahagiaan seperti apa yang sedang kita rayakan, dan untuk kepentingan siapa narasi itu bekerja?
Rujukan klaim tersebut adalah Global Flourishing Study, riset internasional yang mengukur kesejahteraan manusia secara multidimensi—tidak hanya kepuasan hidup, tetapi juga makna, relasi sosial, karakter moral, dan stabilitas material.
Berbeda dari indeks kebahagiaan konvensional yang lazim dipakai dalam perbandingan antarnegara, studi ini melihat kebahagiaan sebagai flourishing, yakni kemampuan manusia menjalani hidup yang dianggap bermakna, meski dalam keterbatasan.
Di titik ini, kebahagiaan tidak identik dengan kemakmuran struktural. Ia bisa lahir dari jejaring sosial yang kuat, religiusitas, dan kemampuan kultural untuk berdamai dengan kekurangan.
Klaim Indonesia sebagai negara paling bahagia, karenanya, perlu dibaca secara hati-hati—bukan dirayakan secara mentah.
Kebahagiaan dan bahaya simplifikasi
Masalah pertama terletak pada penyederhanaan makna kebahagiaan dalam ruang publik. Ketika istilah “paling bahagia” diproduksi tanpa penjelasan metodologis, publik digiring pada kesimpulan seolah-olah kondisi hidup masyarakat Indonesia telah mencapai tingkat ideal.
Padahal, flourishing bukanlah ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi, apalagi bukti tuntasnya pekerjaan negara dalam menjamin kesejahteraan warga.
Kebahagiaan dalam makna flourishing justru sering muncul di ruang-ruang di mana negara absen. Ia tumbuh dari solidaritas informal, dari keluarga yang saling menopang, dari komunitas yang belajar bertahan di tengah ketidakpastian.
Dalam konteks ini, kebahagiaan bisa menjadi mekanisme adaptif—cara masyarakat menjaga kesehatan mental dan makna hidup ketika akses terhadap pendidikan bermutu, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial masih timpang.
Merayakan kebahagiaan tanpa mengakui konteks ini berisiko menjadikannya alat kosmetik, bukan refleksi kritis.
Lebih jauh, narasi kebahagiaan yang dipisahkan dari realitas struktural berpotensi menormalisasi ketimpangan.
Rakyat yang tetap bahagia meski hidup pas-pasan kerap dipuji sebagai bukti ketangguhan budaya. Namun, pujian semacam itu mudah tergelincir menjadi justifikasi diam-diam atas ketertinggalan.
Dalam sejarah pembangunan Global South, romantisasi ketabahan rakyat sering berjalan beriringan dengan lambannya reformasi kebijakan.
Indonesia hari ini hidup dalam paradoks yang tidak sederhana. Di satu sisi, berbagai indikator objektif menunjukkan kemajuan: pertumbuhan ekonomi relatif stabil, infrastruktur terus dibangun, dan posisi geopolitik Indonesia kian strategis.
Di sisi lain, ketimpangan antarwilayah, kualitas pendidikan tidak merata, kerentanan pekerja informal, dan keterbatasan akses layanan dasar tetap menjadi kenyataan sehari-hari bagi jutaan warga.
Dalam situasi seperti ini, kebahagiaan masyarakat bisa dibaca dengan dua cara yang berlawanan.
Pertama, sebagai modal sosial berharga—energi kultural yang memungkinkan masyarakat tetap koheren di tengah tekanan struktural.
Kedua, sebagai alarm sunyi: tanda bahwa masyarakat telah terlalu lama dipaksa beradaptasi, sehingga standar kesejahteraan diturunkan agar hidup tetap terasa layak dijalani.
Tanpa kebijakan yang berpihak, kebahagiaan berisiko menjadi pelindung psikologis yang menutupi ketimpangan, bukan jembatan menuju kemajuan.
Pembangunan yang matang seharusnya tidak berhenti pada angka pertumbuhan, tetapi juga tidak berpuas diri pada indeks kebahagiaan.
Kemajuan sejati justru diukur dari kemampuan negara mengubah kebahagiaan kultural menjadi kesejahteraan struktural: memastikan bahwa makna hidup tidak harus dibayar dengan kerentanan ekonomi, dan solidaritas sosial tidak lahir dari ketiadaan jaminan negara.
Fenomena Indonesia bukanlah anomali. Banyak negara Global South menunjukkan pola serupa: tingkat kebahagiaan atau makna hidup yang relatif tinggi di tengah keterbatasan material.
Dari Amerika Latin hingga Asia Selatan, masyarakat mengandalkan relasi sosial dan nilai kultural untuk menjaga martabat hidup ketika negara belum sepenuhnya hadir.
Namun sejarah juga mengajarkan bahwa kebahagiaan semacam ini rapuh ketika tekanan ekonomi meningkat dan solidaritas diuji.
Di sinilah posisi Indonesia menjadi krusial secara geopolitik dan intelektual. Sebagai negara besar Global South, Indonesia memiliki peluang untuk menawarkan paradigma alternatif pembangunan—yang tidak meniru secara mentah model negara maju, tetapi juga tidak bersembunyi di balik narasi kebahagiaan kultural.
Tantangannya adalah menjahit kebahagiaan, pembangunan, dan kemajuan dalam satu arah kebijakan yang etis dan berjangka panjang.
Narasi “Indonesia paling bahagia” seharusnya menjadi cermin, bukan panggung. Ia mengingatkan bahwa masyarakat telah melakukan bagiannya: bertahan, beradaptasi, dan menjaga makna hidup.
Kini, tanggung jawab negara adalah memastikan bahwa kebahagiaan itu tidak terus hidup di tengah kekurangan, tetapi tumbuh seiring dengan keadilan sosial, kualitas hidup yang layak, dan kemajuan yang benar-benar dirasakan bersama.
Tag: #ketika #bahagia #selalu #sejahtera