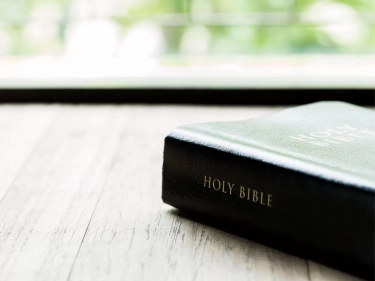Rentetan OTT Kepala Daerah, Sampai Kapan?
RENTETAN operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mewarnai awal masa pemerintahan daerah. Belum setahun menjabat, mereka tersandung kasus dugaan korupsi.
Fakta ini menyodorkan pertanyaan mendasar mengapa penindakan yang semakin masif tidak juga menimbulkan efek jera?
Dalam satu dekade terakhir, ancaman hukum terhadap korupsi kian nyata. OTT berlangsung cepat, terbuka, dan disorot publik.
Namun, keberanian kepala daerah untuk tetap melakukan korupsi menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan semata pada lemahnya penegakan hukum.
Masalahnya terletak pada sistem politik dan tata kelola pemerintahan yang memberi ruang, bahkan dorongan bagi perilaku koruptif.
Biaya politik yang mahal menjadi salah satu akar persoalan. Kontestasi pemilihan kepala daerah menuntut logistik besar.
Kampanye, mobilisasi massa, hingga mahar politik tak jarang terjadi, meski susah untuk dibuktikan.
Ketika kandidat terpilih, jabatan publik berubah menjadi instrumen pengembalian modal. Dalam kondisi seperti ini, integritas personal sering kali kalah oleh tekanan sistem.
Korupsi kepala daerah, bukan sekadar kegagalan individu, melainkan kegagalan tata kelola bersama. Lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya transparansi pengadaan barang dan jasa, serta praktik jual-beli jabatan menciptakan ekosistem yang subur bagi penyalahgunaan kewenangan.
Selama peluang itu tetap terbuka, OTT hanya akan menjadi rutinitas, bukan solusi.
Peran presiden
Dalam konteks inilah peran presiden menjadi sangat menentukan. Presiden harus mengerahkan segenap kekuatan politik dan administratifnya untuk memastikan pemerintah daerah benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok atau kroni.
Pembiaran terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di daerah hanya akan memperlebar jurang ketimpangan dan merusak legitimasi negara di mata warganya. Praktik KKN di daerah harus disudahi, bukan ditoleransi, apalagi dinegosiasikan.
Sudah bukan zamannya lagi jabatan publik diperlakukan sebagai ruang bermain atau alat transaksi. Kepala daerah adalah pemegang mandat rakyat yang harus bertanggung jawab secara moral dan politik.
Presiden, sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, dituntut hadir bukan hanya saat peresmian atau seremoni, tetapi juga memastikan sistem berjalan tegas, konsisten, dan bebas kompromi terhadap korupsi.
Sampai kapan situasi ini akan berakhir? Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa penindakan keras perlu dibarengi pencegahan sistemik.
Negara dengan tingkat korupsi rendah tidak hanya mengandalkan hukuman berat, tetapi juga membangun birokrasi profesional, sistem pendanaan politik yang transparan, serta mekanisme pengawasan yang bekerja otomatis, bukan reaktif.
Bagi Indonesia, sejumlah langkah alternatif layak dipertimbangkan secara serius. Pertama, reformasi pembiayaan politik harus menjadi agenda utama.
Tanpa transparansi dan pembatasan yang ketat, pemilu akan terus melahirkan pemimpin dengan beban politik sejak hari pertama menjabat.
Kedua, digitalisasi penuh dalam perencanaan anggaran dan pengadaan perlu dipercepat untuk meminimalkan interaksi transaksional.
Ketiga, penguatan pengawasan internal di daerah harus dilakukan secara nyata, bukan sekadar administratif. Aparat pengawas mesti independen dan berani, dengan perlindungan hukum memadai.
Selain itu, profesionalisasi birokrasi melalui sistem merit mutlak diperlukan. Jabatan struktural dan teknis harus diisi berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan politik.
Di saat yang sama, pendidikan etika publik bagi pejabat negara tidak boleh bersifat seremonial, melainkan terukur dan berdampak.
Penindakan korupsi tetap penting dan harus dijaga konsistensinya. Namun, tanpa pembenahan sistem yang melahirkan korupsi itu sendiri, kita hanya akan menyaksikan pergantian pelaku, bukan berakhirnya praktik.
Jika tidak, maka OTT demi OTT akan terus menjadi berita rutin, sementara kepercayaan publik kian terkikis.
Sampai kapan?
Korupsi kepala daerah tidak akan berhenti hanya dengan ketakutan akan ditangkap. Ia akan berhenti ketika kekuasaan tak lagi menjanjikan keuntungan pribadi, dan jabatan publik benar-benar kembali menjadi alat pelayanan.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa korupsi tidak pernah berhasil ditekan hanya dengan mengandalkan penindakan.
Negara-negara dengan tingkat korupsi rendah justru menempatkan pencegahan sebagai fondasi utama, terutama melalui reformasi pembiayaan politik dan tata kelola pemerintahan.
Transparansi dana kampanye, pembatasan sumbangan politik, serta pelaporan yang dapat diawasi publik menjadi prasyarat agar jabatan publik tidak berubah menjadi instrumen pengembalian modal.
Tanpa pembenahan pada sisi hulu ini, setiap upaya pemberantasan korupsi akan selalu tertinggal di belakang praktik yang terus beradaptasi.
Digitalisasi tata kelola juga terbukti efektif menutup ruang transaksional. Korea Selatan, misalnya, mampu menekan praktik suap dalam pengadaan publik dengan menerapkan sistem pengadaan elektronik terpadu yang meminimalkan kontak langsung antara pejabat dan penyedia barang dan jasa.
Proses yang tercatat secara digital mempersempit ruang kompromi dan memudahkan audit. Praktik serupa, bila diterapkan secara konsisten di pemerintah daerah Indonesia, berpotensi besar mengurangi korupsi yang selama ini tumbuh subur di sektor pengadaan.
Di sisi lain, penguatan lembaga antikorupsi menjadi kunci ketika dilakukan secara independen dan terintegrasi.
Singapura dan Hong Kong memperlihatkan bahwa lembaga antikorupsi yang kuat tidak hanya bekerja menangkap pelaku, tetapi juga aktif membangun sistem pencegahan dan pendidikan publik.
Pendekatan semacam ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar soal menghukum, melainkan membangun kesadaran kolektif dan ketahanan sistem.
Namun, pengalaman negara lain juga mengingatkan bahwa penindakan besar-besaran tanpa penguatan kelembagaan berisiko dilemahkan di kemudian hari oleh tarik-menarik kepentingan politik.
Pelajaran penting lainnya adalah profesionalisasi birokrasi. Negara-negara dengan tata kelola baik memastikan jabatan publik diisi melalui sistem merit, bukan kedekatan politik.
Dengan birokrasi profesional, kepala daerah tidak mudah memperjualbelikan jabatan, dan keputusan administratif lebih terlindungi dari tekanan politik jangka pendek.
Perlindungan terhadap pelapor dan keterbukaan anggaran publik juga menjadi elemen penting, karena korupsi paling rentan tumbuh dalam ruang yang tertutup dan tanpa pengawasan.
Bagi Indonesia, solusi tersebut bukanlah sesuatu yang utopis. Tantangannya terletak pada keberanian politik untuk menerjemahkan pelajaran internasional ke dalam kebijakan konkret di tingkat daerah.
Reformasi pembiayaan politik, digitalisasi pengadaan, penguatan pengawasan internal, serta konsistensi penegakan hukum harus berjalan beriringan.
Jika tidak, maka kita hanya akan terus menyaksikan drama penindakan tanpa akhir. Pada akhirnya, korupsi akan surut bukan karena ketakutan akan ditangkap, melainkan karena sistem tidak lagi memberi ruang untuk disalahgunakan.