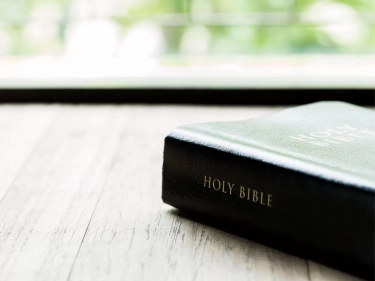RUU Jabatan Hakim: Antara Imunitas dan Impunitas
DI ATAS palu seorang hakim, nasib manusia digantungkan. Di bawah jubah hitamnya, hukum ditegakkan atau dikhianati. Karena itu, kehormatan hakim adalah kehormatan hukum itu sendiri.
Namun, di tengah maraknya kasus suap peradilan dan tekanan terhadap hakim, DPR bersama pemerintah kini tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim, yang disebut-sebut sebagai tonggak baru untuk meneguhkan kemandirian kekuasaan kehakiman.
RUU ini bukan hal baru. Sejak 2016 ia bolak-balik muncul dalam daftar Prolegnas, tetapi selalu tertunda oleh tarik-menarik kepentingan antarlembaga: Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan DPR.
Kini, menjelang akhir 2025, RUU itu kembali naik ke permukaan. Komisi III DPR telah menyepakati untuk mendorongnya masuk Prolegnas Prioritas 2026.
Mahkamah Agung bahkan sudah menyiapkan draf kerja yang mengatur seluruh aspek profesi hakim — mulai dari pengangkatan, promosi, disiplin, kesejahteraan, hingga perlindungan hukum.
Semangat resminya adalah mulia: menegakkan martabat hakim sebagai pejabat negara yang merdeka dan tidak tunduk pada kekuasaan lain.
Namun di balik kalimat ideal itu, publik menemukan aroma lain: kekhawatiran akan munculnya imunitas berlebihan, yang dalam praktik bisa menjelma menjadi impunitas.
Perubahan paling mendasar dalam RUU ini adalah penetapan status hakim sebagai “pejabat negara”, bukan lagi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Mahkamah Agung beralasan, selama hakim masih berstatus ASN, maka independensinya selalu terikat pada logika birokrasi dan jenjang karier administratif.
Hakim dianggap tak sepenuhnya merdeka karena masih tunduk pada mekanisme kepegawaian dan sistem penggajian ASN yang ditetapkan pemerintah.
RUU Jabatan Hakim ingin menghapus ikatan itu: hakim tidak lagi pegawai, tetapi pejabat konstitusional — sejajar dengan pejabat negara lainnya.
Secara filosofis, gagasan ini bisa diterima. Hakim memang bukan birokrat, melainkan organ konstitusi yang bertugas menegakkan keadilan.
Dalam sistem ketatanegaraan, hakim berada di luar lingkaran eksekutif. Karena itu, penegasan status sebagai pejabat negara dimaksudkan agar ia memiliki posisi independen dan tak dapat diintervensi oleh kementerian mana pun.
Namun, sebagaimana setiap upaya “memuliakan”, selalu ada risiko “mengistimewakan”.
Ketika status pejabat negara diberikan tanpa sistem pengawasan publik yang kuat, kemandirian bisa menjelma menjadi kekebalan. Di sinilah batas tipis antara imunitas dan impunitas mulai kabur.
Imunitas
Pasal-pasal draf RUU Jabatan Hakim menyebut bahwa hakim tidak dapat dipanggil, diperiksa, ditangkap, atau ditahan sehubungan dengan pelaksanaan tugas yudisial, kecuali dengan izin Ketua Mahkamah Agung.
Pengecualian hanya berlaku jika hakim tertangkap tangan (OTT), disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman mati, atau terlibat dalam kejahatan terhadap keamanan negara.
Mahkamah Agung menyebut ini sebagai imunitas yudisial, perlindungan agar hakim tidak bisa ditekan atau dikriminalisasi karena putusan-putusan yang tidak disukai pihak tertentu.
Argumennya: banyak hakim di daerah diadukan ke polisi atau kejaksaan hanya karena pihak yang kalah merasa kecewa. Tanpa imunitas, hakim rawan dijadikan alat tawar-menawar.
Namun pertanyaannya sederhana: siapa yang mengawasi pemberi izin itu?
Jika izin memeriksa hanya bergantung pada Ketua MA, maka seluruh pengawasan pidana terhadap hakim terpusat di satu meja.
Publik tidak lagi punya akses untuk memastikan apakah laporan terhadap hakim yang diduga menyalahgunakan wewenang diproses secara adil.
Imunitas yang dimaksudkan untuk melindungi profesi bisa berubah menjadi tameng bagi pelanggaran etik dan tindak pidana.
Apalagi pengalaman membuktikan: antara 2011 hingga 2024, sebanyak 29 hakim telah menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi dengan total nilai suap sekitar Rp 107,9 miliar (data ICW).
Dalam situasi seperti itu, imunitas tanpa mekanisme akuntabilitas bukan lagi perlindungan, melainkan penyamaran. Ia menjadikan palu hakim tak lagi simbol keadilan, melainkan simbol kekuasaan.
Kemandirian
Tak seorang pun menolak ide bahwa hakim harus mandiri. Kemandirian adalah syarat mutlak peradilan yang adil (independent judiciary). Namun kemandirian tanpa akuntabilitas ibarat ruang sidang tanpa pintu — tertutup dari koreksi publik.
RUU Jabatan Hakim seharusnya membangun keseimbangan antara independence dan accountability. Sayangnya, rancangan saat ini tampak condong pada yang pertama dan melupakan yang kedua.
Misalnya, pengawasan etik dalam draf baru ini nyaris tidak lagi menyinggung peran Komisi Yudisial (KY) secara eksplisit.
MA mendorong agar pengawasan internal sepenuhnya berada di bawah lembaga peradilan. Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, relasi MA dan KY justru harus bersifat komplementer — saling mengimbangi, bukan saling meniadakan.
Jika RUU ini dibiarkan tanpa desain ulang, maka KY bisa terpinggirkan, dan peradilan kembali pada model “satu atap” yang berisiko menciptakan korporasi tertutup di bawah MA.
Akhirnya, pengawasan hanya menjadi urusan “keluarga besar peradilan”, bukan urusan publik.
Hakim memang bukan ASN, tetapi ia tetap public servant dalam arti substantif: pelayan keadilan bagi rakyat.
Kemandirian yang dipahami sebagai kekuasaan tanpa kontrol publik justru bertentangan dengan semangat reformasi peradilan pasca-1998.
Kemandirian tanpa moralitas hanya akan melahirkan keangkuhan hukum. Publik masih mengingat kasus hakim Pengadilan Negeri Bandung yang tertangkap menerima suap dari pengusaha perkara tanah, atau hakim Tipikor Semarang yang menjanjikan vonis ringan dengan imbalan uang.
Dalam banyak kasus, pelanggaran etik dan perilaku koruptif tidak terjadi karena lemahnya undang-undang, melainkan karena rendahnya kesadaran moral dalam jabatan.
RUU Jabatan Hakim semestinya tidak hanya berbicara tentang status, imunitas, atau kesejahteraan, tetapi juga etika profesi sebagai inti jabatan kehakiman.
Etika bukan lampiran, melainkan fondasi. Karena ketika etika hilang, hukum hanyalah prosedur tanpa jiwa.
RUU ini baru akan berarti jika mampu menegaskan bahwa setiap kemandirian membawa tanggung jawab moral yang sepadan. Hakim memang tidak boleh diintervensi, tetapi bukan berarti tidak boleh dikoreksi.
Pengawasan
Hubungan antara MA dan KY menjadi titik api paling panas dalam pembahasan RUU ini.
MA menghendaki pengawasan internal penuh, sementara KY menegaskan bahwa konstitusi memberi mereka mandat menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
Dalam kerangka konstitusi, fungsi pengawasan etik tidak boleh dipisahkan dari kontrol eksternal. Karena kekuasaan kehakiman, sebagaimana kekuasaan lain, selalu rawan diselewengkan.
Ketiadaan pengawasan eksternal akan membawa kita kembali ke masa kelam peradilan pra-reformasi — saat lembaga peradilan berada dalam bayang hierarki tertutup.
Kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial sendiri fluktuatif. LSI (April 2024) mencatat kepercayaan pada Mahkamah Konstitusi sekitar 73 persen, sementara persepsi terhadap institusi penegak hukum lain jauh lebih rendah.
Data itu cukup menjadi cermin: publik menaruh harapan besar pada independensi, tetapi juga kecurigaan pada integritas. RUU Jabatan Hakim seharusnya menjembatani jurang itu, bukan memperlebar.
Perlindungan
Profesi hakim memang menghadapi ancaman nyata. Data Mahkamah Agung (2025) menunjukkan sekitar 64 persen hakim pernah mengalami intimidasi atau pelecehan di ruang sidang, baik verbal, fisik, maupun digital.
Sementara paparan DPR (April 2025) memperkirakan sekitar 25 persen hakim pernah menghadapi contempt of court dalam bentuk gangguan langsung terhadap kewenangan yudisial.
Perbedaan angka ini disebabkan metodologi berbeda, tetapi keduanya menunjukkan bahwa profesi hakim memang butuh perlindungan hukum.
Namun, perlindungan tidak boleh disalahartikan sebagai kekebalan. Dalam demokrasi, pejabat publik dilindungi agar dapat menjalankan tugasnya, tetapi tetap harus bertanggung jawab atas pelanggaran etik dan hukum.
Tidak ada profesi yang boleh kebal hukum — bahkan hakim sekalipun. Prinsip yang adil adalah: hakim dilindungi ketika menegakkan hukum, bukan ketika menyalahgunakan hukum.
RUU ini juga mengatur hak keuangan dan kesejahteraan hakim secara lebih pasti. Hakim akan mendapatkan paket remunerasi setara pejabat negara, tunjangan perumahan, dan jaminan keselamatan kerja.
Hal ini merupakan bagian dari upaya restorasi moral dalam dunia peradilan: hakim yang sejahtera diharapkan tak mudah tergoda suap.
Namun, kesejahteraan tanpa integritas hanyalah memperkaya, bukan memperbaiki. Kenaikan gaji tidak otomatis menaikkan moral.
Sejarah membuktikan: korupsi justru sering tumbuh di lembaga yang gajinya tinggi tapi pengawasannya lemah.
Karena itu, kesejahteraan harus diimbangi dengan pengawasan ketat dan mekanisme transparansi publik.
RUU ini akan menjadi langkah maju bila menautkan kesejahteraan dengan integritas — misalnya, melalui sistem evaluasi periodik atau uji etik berkala yang melibatkan KY.
Hakim yang sejahtera dan berintegritas adalah dua sisi dari keadilan yang hidup.
Arah
Pada akhirnya, pertarungan substansial RUU Jabatan Hakim bukan sekadar soal teknis hukum, melainkan soal filsafat kekuasaan kehakiman: Apakah hakim adalah pelayan keadilan, atau pemiliknya?
RUU ini akan menentukan wajah peradilan Indonesia dekade mendatang. Bila arah pembahasan lebih condong pada perlindungan diri daripada pelayanan publik, maka kita sedang menciptakan tembok, bukan jembatan.
Sebaliknya, bila ia mampu menyeimbangkan antara martabat dan pengawasan, maka RUU ini akan menjadi warisan konstitusional yang berharga.
Kekuasaan kehakiman bukan milik hakim, tetapi amanat rakyat. Hakim berhak atas perlindungan, tetapi rakyat berhak atas keadilan.
Di titik pertemuan dua hak inilah RUU Jabatan Hakim diuji: apakah ia memperkuat demokrasi hukum, atau justru menciptakan negara hukum yang tak bisa disentuh.
Kemandirian hakim adalah tiang tegaknya hukum. Namun, imunitas tanpa batas adalah lubang di dasar tiang itu.
RUU Jabatan Hakim sedang berdiri di perbatasan yang rapuh: antara menjaga martabat profesi dan memberi ruang bagi kekuasaan tanpa kontrol.
Sejarah menunjukkan, negara kuat bukan karena hakimnya kebal, melainkan karena hakimnya berani adil. Adil, bahkan ketika keadilan itu menyakitkan bagi dirinya sendiri.
Dan bagi rakyat yang setiap hari datang ke pengadilan dengan harapan tipis bahwa hukum masih berpihak pada kebenaran, RUU Jabatan Hakim seharusnya menjawab satu hal sederhana: bahwa di balik palu hakim, keadilan bukan dijaga oleh kekebalan, tetapi oleh nurani.