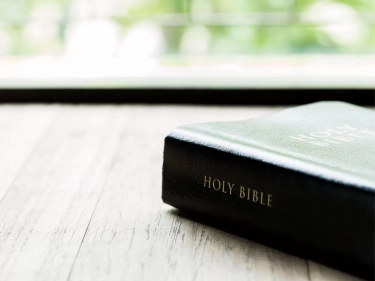Anak Muda dan Ilusi Personal Branding
PERSONAL branding kerap dibicarakan pada level yang terlalu tinggi. Ia hadir dalam seminar karier, pelatihan profesional, atau diskursus dunia kerja yang menyasar mereka yang telah mapan dalam profesi tertentu.
Dalam konteks itu, personal branding sering dipahami sebagai strategi promosi diri—bagaimana tampil menarik, meyakinkan, dan kompetitif. Tak mengherankan bila ia kerap dicurigai sebagai pencitraan.
Padahal, personal branding sejatinya berakar pada konsep diri: bagaimana seseorang mengenali dirinya, memahami nilai yang ia pegang, serta menyadari bagaimana ia ingin hadir di mata orang lain.
Proses ini justru paling menentukan ketika seseorang berada pada fase awal kehidupan—masa kanak-kanak, remaja, dan awal dewasa—ketika identitas masih lentur dan sedang dibentuk.
Ketika personal branding hanya dikenalkan di tahap akhir, yang tersisa sering kali hanyalah ilusi tentang diri yang belum benar-benar dikenal.
Masalah muncul ketika anak muda tiba-tiba diminta “menjual dirinya” saat memasuki dunia kerja atau ruang publik profesional.
Mereka dituntut menyusun narasi personal, menampilkan keunikan, dan membangun citra, padahal sebelumnya tidak pernah diajak secara sistematis untuk memahami siapa dirinya dan nilai apa yang ingin ia bawa.
Branding pun menjadi reaktif dan permukaan, bukan refleksi karakter yang matang.
Psikolog Erik Erikson, dalam Identity: Youth and Crisis (1968), menegaskan bahwa masa remaja merupakan fase krusial pencarian identitas.
Pada fase ini, individu berupaya menjawab pertanyaan mendasar tentang siapa dirinya dan peran apa yang ingin ia ambil di masyarakat.
Ketika proses ini tidak difasilitasi dengan baik, individu berisiko mengalami kebingungan identitas yang dampaknya terbawa hingga dewasa.
Dalam konteks tersebut, personal branding yang datang terlambat sering kali bukan memperkuat jati diri, melainkan menutup kekosongan identitas dengan lapisan citra.
Budaya prestasi dan kekosongan makna
Fenomena ini terlihat dalam keseharian anak muda Indonesia yang tumbuh di tengah tekanan pencapaian.
Sejak dini, banyak anak diarahkan untuk mengejar nilai, peringkat, dan prestasi, tetapi jarang diajak merefleksikan makna di balik pencapaian tersebut.
Mereka terbiasa menjawab apa yang mereka raih, tetapi kesulitan menjelaskan mengapa hal itu penting dan bagaimana kaitannya dengan nilai hidup yang mereka yakini. Identitas pun dibentuk dari pengakuan eksternal, bukan dari pemahaman diri.
Personal branding yang sehat seharusnya tidak bekerja dengan cara demikian. Ia bukan soal menjual diri, melainkan proses pengenalan dan penguatan diri yang berjalan bertahap.
Branding yang autentik tumbuh dari keaslian, konsistensi, dan kesadaran nilai. Ia hadir melalui pilihan hidup, perilaku sehari-hari, cara berinteraksi, serta kontribusi yang dijaga kesesuaiannya antara dunia nyata dan ruang digital.
Berbagai kajian psikologi perkembangan menunjukkan bahwa remaja dengan konsep diri yang jelas cenderung memiliki ketahanan psikologis yang lebih baik, tingkat kecemasan sosial yang lebih rendah, serta kemampuan mengambil keputusan yang lebih matang.
Artinya, penguatan konsep diri sejak dini bukan hanya relevan bagi masa depan karier, tetapi juga berpengaruh langsung pada kesehatan mental dan kualitas relasi sosial.
Di era media sosial, persoalan ini menjadi semakin kompleks. Banyak anak muda Indonesia telah hadir di ruang publik digital jauh sebelum mereka memiliki kesadaran identitas dan reputasi.
Unggahan dibuat secara spontan, narasi berkembang tanpa kendali, dan persepsi publik terbentuk sebelum subjeknya benar-benar memahami dirinya sendiri.
Ruang digital bukan lagi sekadar ruang ekspresi, melainkan ruang penilaian yang jejaknya bersifat permanen.
Kasus yang sempat mencuat melalui pemberitaan Kompas.com—ketika ayah penyanyi muda Farel Prayoga melaporkan manajer sang anak ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik—menunjukkan bagaimana narasi publik dapat berdampak langsung pada reputasi dan relasi sosial.
Pernyataan yang beredar di ruang publik memicu persepsi negatif terhadap keluarga sebelum ada pemaknaan utuh atas konteks dan posisi masing-masing pihak.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa reputasi dapat terbentuk dan dipelintir dengan cepat ketika identitas dan narasi diri tidak dikelola secara sadar.
Di dunia yang semakin terdigitalisasi, jejak digital telah menjadi bagian dari penilaian sosial. Survei CareerBuilder menunjukkan bahwa banyak perekrut mempertimbangkan informasi daring kandidat sebelum mengambil keputusan.
Reputasi tidak lagi dibangun semata melalui pertemuan tatap muka, tetapi melalui arsip digital yang terus hidup. Tanpa kesadaran reputasi, anak muda memasuki ruang publik seperti berjalan tanpa peta.
Pekerjaan rumah pendidikan kita
Di sinilah pendidikan menghadapi pekerjaan rumah besar. Selama orientasi pendidikan masih dominan pada capaian akademik, pembentukan konsep diri kerap terpinggirkan.
Anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang rajin dan berprestasi, tetapi rapuh dalam memaknai dirinya sendiri.
Laporan World Economic Forum (2023) menempatkan kesadaran diri, kemampuan komunikasi, dan inisiatif personal sebagai kompetensi kunci masa depan—yang sejatinya berakar pada konsep diri yang matang.
Personal branding bukan agenda elitis dan bukan sekadar tren media sosial. Ia adalah konsekuensi logis dari dunia yang semakin terbuka dan terekam.
Namun, personal branding yang sehat hanya mungkin tumbuh dari konsep diri yang kuat, dan itu harus dibangun sejak dini, secara sadar, perlahan, dan beretika.
Jika pendidikan ingin benar-benar menyiapkan generasi masa depan, maka ia tidak cukup mengajarkan apa yang harus diketahui. Ia juga harus membantu peserta didik memahami siapa dirinya dan bagaimana ia ingin berdampak.
Tanpa itu, personal branding akan terus menjadi ilusi—ramai di permukaan, tetapi rapuh di dalam.