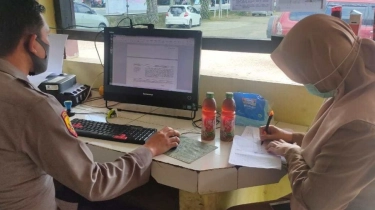Demokrasi Rusak, Kegagalan Partai, dan Korupsi Daerah yang Berulang
OPERASI tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Pati dan Wali Kota Madiun beberapa waktu lalu, kembali menegaskan bahwa korupsi di tingkat daerah bukanlah penyimpangan yang bersifat sporadis.
Sesuatu yang hadir berulang, dengan pola dan modus yang nyaris seragam, seolah menjadi produk rutin dari sistem politik lokal pasca-Reformasi.
Dalam konteks ini, OTT tidak cukup atau hanya dibaca sebagai keberhasilan penegakan hukum semata, melainkan sebagai indikator kegagalan demokrasi elektoral sejauh ini dalam memproduksi kepemimpinan yang bersih dan berintegritas.
Demokrasi lokal di Indonesia memang berjalan secara prosedural. Ditandai dengan pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara berkala, partisipasi pemilih dijaga, dan legitimasi kekuasaan diperoleh melalui mekanisme pemungutan suara.
Namun, demokrasi prosedural ini faktanya menyimpan paradoks serius. Di balik proses elektoral yang tampak sah, berlangsung praktik politik berbiaya tinggi: transaksi pencalonan lewat mahar politik mendorong relasi oligarkis dan turut membentuk kekuasaan sejak tahap paling awal.
Dalam sistem politik seperti ini, jabatan publik tidak lagi sepenuhnya dipahami sebagai amanah, melainkan sebagai aset politik dan ekonomi.
Biaya besar yang dikeluarkan selama kontestasi menciptakan logika “balik modal” yang kuat. Korupsi kemudian hadir bukan sebagai anomali, tetapi sebagai konsekuensi logis yang hampir tak terhindarkan.
Anggaran publik dijadikan instrumen kompromi politik, proyek pembangunan berubah menjadi sumber rente, dan birokrasi ditempatkan sebagai alat distribusi kekuasaan.
Selama ini, diskursus publik cenderung memusatkan perhatian pada figur kepala daerah yang tertangkap. Pendekatan ini penting dalam konteks hukum, tetapi terlalu sempit untuk menjelaskan persoalan yang sesungguhnya.
Ketika pelaku terus berganti, tetapi skema kejahatan tidak berubah, maka jelas persoalannya terletak pada sistem politik yang melahirkannya.
Dalam konteks inilah kegagalan partai politik menjadi semakin nyata. Bagaimanapun partai seharusnya menjadi institusi utama yang menjamin kualitas demokrasi melalui rekrutmen, kaderisasi, dan kontrol terhadap kekuasaan.
Namun dalam praktiknya, banyak partai politik justru berfungsi minimalis. Yaitu sekadar menjadi kendaraan elektoral untuk memenangkan kontestasi, bukan institusi yang serius membangun atau melahirkan kepemimpinan publik.
Proses pencalonan kepala daerah kerap ditentukan oleh kombinasi elektabilitas instan dan kapasitas finansial. Dampaknya, integritas, rekam jejak, dan visi kepemimpinan seringkali hanya menjadi pertimbangan sekunder.
Kaderisasi internal melemah, pendidikan politik menjadi seremonial, dan mekanisme etik internal jarang digunakan sebagai alat seleksi yang sungguh-sungguh. Partai kehilangan perannya sebagai penyaring utama kekuasaan.
Ketika kepala daerah terseret OTT, pola respons partai hampir selalu sama: menjaga jarak dan menegaskan bahwa korupsi adalah tanggung jawab pribadi. Pernyataan ini mungkin sah secara hukum, tetapi problematis secara politik.
Partai tidak bisa sepenuhnya ‘cuci tangan’ atau melepaskan diri dari tanggung jawab atas pejabat yang mereka usung, dukung, dan legitimasi. Demokrasi yang sehat menuntut akuntabilitas institusional, bukan sekadar pengorbanan individu.
Korupsi di daerah juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca-Pilkada. Jabatan birokrasi sering digunakan sebagai alat konsolidasi kekuasaan dan balas jasa politik.
Proyek strategis dijadikan sumber pembiayaan politik lanjutan, baik untuk menjaga stabilitas koalisi maupun menyiapkan kontestasi berikutnya. Dalam kondisi seperti ini, batas antara kepentingan publik dan kepentingan politik menjadi semakin kabur.
Kasus OTT di Pati dan Madiun sekaligus memperlihatkan rapuhnya sistem pengawasan internal pemerintahan daerah. Inspektorat, audit internal, dan mekanisme kontrol administratif belum berfungsi sebagai sistem pencegahan yang efektif.
Prinsip transparansi dan akuntabilitas lebih sering hadir sebagai jargon normatif ketimbang praktik yang hidup. Negara kemudian baru hadir secara tegas setelah korupsi terjadi, bukan sebelum.
Penindakan hukum memang mutlak diperlukan. Namun, ketika OTT menjadi peristiwa yang berulang tanpa perubahan mendasar pada sistem politik dan kelembagaan, maka akumulasinya justru berpotensi menormalkan kegagalan.
Korupsi dipersepsikan sebagai risiko yang melekat pada kekuasaan, sementara negara cukup hadir untuk menangkap pelakunya. Pendekatan ini menyelesaikan gejala, tetapi membiarkan sumber penyakitnya tetap utuh dan mengemuka.
Narasi “oknum” yang kerap digunakan untuk merespons setiap kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik atau kader partai juga patut dikritisi. Narasi ini menyederhanakan persoalan dan mengaburkan tanggung jawab struktural.
Demokrasi tidak akan pernah matang jika terus-menerus menggantungkan harapan pada moral individu, tanpa membangun sistem yang mampu menyaring dan membatasi kekuasaan.
Selama biaya politik tetap tinggi dan tidak transparan, selama partai politik enggan melakukan reformasi internal secara serius, dan selama jabatan publik masih diperlakukan sebagai komoditas, korupsi akan terus direproduksi.
Dalam situasi seperti ini, OTT lebih menyerupai alarm yang terus berbunyi, tetapi tidak pernah diikuti perbaikan pada sumber kebisingannya.
Karena itu, setiap OTT seharusnya menjadi momentum refleksi dan koreksi. Reformasi pembiayaan politik merupakan prasyarat utama untuk memperbaiki kualitas demokrasi elektoral.
Tanpa pembenahan di sektor ini, kompetisi politik akan terus didominasi oleh mereka yang memiliki sumber daya terbesar, bukan kapasitas terbaik.
Partai politik harus dipaksa—melalui regulasi dan tekanan atau pengawasan publik—untuk kembali menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasi secara sungguh-sungguh.
Di saat yang sama, penguatan kelembagaan pemerintahan daerah menjadi kebutuhan mendesak dan harus dilakukan dengan serius.
Birokrasi harus dilindungi dari intervensi politik jangka pendek, dan sistem pengawasan internal harus diberi independensi serta daya paksa yang nyata, tidak menjadi seolah-olah.
Tanpa pondasi kelembagaan yang kuat, bahkan kepala daerah dengan niat baik pun akan kesulitan menjaga integritas pemerintahan.
OTT di Pati dan Madiun bukanlah anomali, tetapi refleksi dari demokrasi elektoral yang belum sepenuhnya substantif dan bermakna.
Selama akar persoalan ini tidak disentuh—khususnya kegagalan partai politik sebagai pilar demokrasi—publik hanya akan terus menyaksikan siklus yang sama: penindakan demi penindakan, tanpa perubahan sistemik yang berarti.
Korupsi daerah, pada akhirnya, bukan sekadar persoalan hukum, melainkan persoalan mendasar pada desain demokrasi dan kelembagaan politik.
Tanpa keberanian untuk membenahi sistem politik termasuk pengelolaan partai politik dari hulunya, penegakan hukum akan selalu datang terlambat—menangani akibat, sementara sebabnya terus dibiarkan, menjadi duri dalam daging demokrasi.
Tag: #demokrasi #rusak #kegagalan #partai #korupsi #daerah #yang #berulang