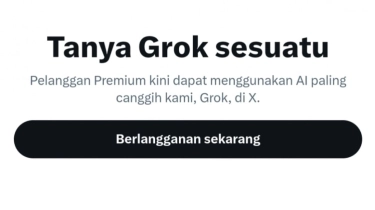Tantangan Memimpin Indonesia, Bangsa yang Bahagia Sekaligus Mudah Tersinggung
ADA satu kebiasaan orang Indonesia yang selalu membuat saya terdiam. Kita bisa sangat cepat menolong orang lain, bahkan orang yang tidak kita kenal sama sekali, tetapi kita juga bisa sangat cepat marah kepada orang yang bahkan belum tentu kita pahami sepenuhnya.
Pagi hari kita menyaksikan solidaritas yang menghangatkan hati, siang harinya kita melihat perdebatan yang memecah emosi, malamnya kita kembali terharu oleh kepedulian bersama. Semua terjadi dalam satu hari, kadang dalam satu linimasa yang sama.
Kita mudah terharu oleh kisah orang lain, cepat bergerak ketika ada musibah, dan nyaris refleks mengulurkan tangan bahkan kepada orang yang tak kita kenal. Namun di hari yang sama, kita juga bisa menyaksikan bagaimana satu kalimat, satu unggahan, atau satu potongan video cukup untuk memicu kemarahan massal. Jarak antara empati dan amarah itu terasa sangat pendek.
Dari situ saya mulai bertanya, ini bukan soal bangsa yang baik atau buruk, melainkan bangsa yang sangat perasa. Dan bangsa yang sangat perasa selalu menuntut cara memimpin yang tidak sederhana. Indonesia sedang hidup dalam sebuah ironi yang indah sekaligus menggelisahkan.
Di satu sisi, dunia memandang kita sebagai bangsa yang bahagia, bahkan paling bahagia dan makmur menurut Harvard Global Flourishing Study 2025. Di sisi lain, kita sendiri kerap bertanya dengan nada ragu, benarkah kita sebahagia itu, atau jangan-jangan kita hanya pandai menyembunyikan luka di balik senyum dan keramahan. Bangsa yang ringan tangan menolong sesama ini, mengapa juga begitu mudah marah, mudah tersinggung, dan mudah tersulut emosinya di ruang publik.
Temuan Harvard Global Flourishing Study 2025 menempatkan Indonesia di posisi teratas bukan karena kita paling kaya atau paling maju secara industri, melainkan karena kita unggul dalam hal yang sering diremehkan dalam perhitungan pembangunan modern, yaitu kualitas relasi sosial, rasa keterhubungan antar manusia, makna hidup, dan kesehatan mental kolektif.
Studi ini membaca kesejahteraan bukan sekadar dari angka pendapatan, tetapi dari bagaimana manusia merasa hidupnya berarti, merasa tidak sendirian, dan merasa memiliki tempat dalam jejaring sosialnya. Dalam ukuran ini, Indonesia menonjol. Kita kuat dalam kebersamaan, kuat dalam komunitas, kuat dalam empati yang hidup dalam keseharian.
Namun justru di titik inilah pertanyaan penting itu muncul. Jika relasi sosial kita kuat dan empati kita tinggi, mengapa ruang publik kita terasa rapuh. Mengapa percakapan dengan cepat berubah menjadi pertengkaran. Mengapa perbedaan pendapat kerap berujung pada saling mencaci. Mengapa bangsa yang dikenal ramah di dunia nyata tampak begitu keras di dunia digital.
Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan menyalahkan media sosial semata, karena akar persoalannya jauh lebih dalam dan terkait langsung dengan cara kita memimpin dan dipimpin.
Watak Bangsa dan Emosi yang Ditunda
Untuk memahami ini, kita perlu kembali pada refleksi lama tentang manusia Indonesia itu sendiri. Mochtar Lubis, dalam ceramahnya tentang manusia Indonesia, pernah menyampaikan kritik yang tajam sekaligus jujur. Ia menggambarkan manusia Indonesia sebagai manusia yang pandai menyembunyikan isi hati, perasaan, dan pikirannya.
"Manusia Indonesia memakai topeng di depan umum, menyembunyikan wajahnya yang sebenannya, serba takut dan khawatir membuka wajahnya, dan mengatakan inilah aku!"
Dalam budaya yang terlalu memuja harmoni, kejujuran emosional sering kali dikorbankan. Kata tidak jarang disamarkan, perbedaan pendapat ditahan, konflik disimpan dalam diam. Emosi tidak diselesaikan, hanya ditunda. Dalam penundaan itulah kemarahan tumbuh. Emosi yang dipendam terlalu lama tidak pernah benar-benar hilang, ia menumpuk dan mencari jalan keluar. Ketika akhirnya meledak, kemarahan itu sering muncul dalam bentuk yang tidak proporsional.
Inilah sebabnya mengapa kemarahan publik di Indonesia kerap terasa berlebihan. Ia bukan lahir dari satu peristiwa tunggal, melainkan dari akumulasi panjang rasa tidak didengar, tidak diakui, dan tidak dianggap.
Mochtar Lubis juga mengingatkan tentang kecenderungan manusia Indonesia untuk menghindari tanggung jawab. Kalimat "bukan saya" menjadi simbol budaya yang enggan berhadapan dengan konsekuensi.
Di era digital, kecenderungan ini menemukan medium baru. Orang mudah menghakimi, mudah menyerang, mudah meluapkan emosi, tetapi enggan bertanggung jawab atas dampak kata-katanya. Kemarahan dilepas, lalu ditinggalkan. Ruang publik menjadi panas, tetapi tidak pernah benar-benar pulih.
Namun kritik ini tidak berarti manusia Indonesia kekurangan empati. Justru sebaliknya. Kritik tersebut lahir karena empati itu ada, tetapi terjebak dalam struktur sosial dan politik yang tidak selalu memberi ruang aman bagi kejujuran dan ketegasan. Kita adalah bangsa yang perasa, sensitif, dan mudah tersentuh.
Empati sebagai Warisan Sejarah
Di sinilah pemikiran A Teeuw tentang citra manusia Indonesia dalam karya sastra Pramoedya Ananta Toer menjadi penting. Dalam bacaan Teeuw, manusia Indonesia adalah manusia yang utuh dengan seluruh luka sejarahnya. Ia marah karena ketidakadilan, keras karena tekanan, dan empatik karena hidupnya terlalu berat untuk dijalani sendirian. Empati dalam karya Pramoedya bukan romantisme, melainkan strategi bertahan hidup.
Sejarah panjang kolonialisme, ketimpangan, dan kekerasan struktural mengajarkan manusia Indonesia satu hal mendasar. Bertahan sendirian hampir mustahil. Dari situlah gotong royong lahir bukan sebagai slogan moral, tetapi sebagai kebutuhan eksistensial. Menolong bukan sekadar pilihan etis, melainkan naluri kolektif. Inilah yang menjelaskan mengapa Indonesia unggul dalam dimensi relasi sosial dalam Harvard Global Flourishing Study.
Kita mungkin tidak selalu sejahtera secara materi, tetapi kita jarang benar-benar sendirian. Namun empati yang lahir dari luka juga membawa konsekuensi emosional. Manusia yang sangat empatik adalah manusia yang sangat sensitif. Ia mudah tersentuh, tetapi juga mudah terluka. Dalam konteks ini, empati dan amarah bukan dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua ekspresi dari kepekaan yang sama.
Ketika keadilan terasa hadir, empati mengalir. Ketika keadilan terasa absen, empati berubah menjadi amarah. Kajian tentang manusia Indonesia dalam konteks alam dan sejarah memperkuat pemahaman ini. Indonesia adalah negeri rawan bencana, agraris dan maritim, yang sangat bergantung pada keseimbangan dan solidaritas sosial.
Dalam masyarakat seperti ini, harmoni bukan konsep abstrak, melainkan syarat hidup. Ketika harmoni terganggu, respons emosional muncul dengan cepat dan kuat. Konflik tidak pernah terasa personal semata, ia selalu dibaca sebagai ancaman terhadap keseimbangan bersama.
Kepemimpinan di Negeri yang Sangat Perasa
Di titik inilah kepemimpinan menjadi sangat menentukan. Memimpin Indonesia bukan sekadar soal membuat kebijakan yang benar secara teknokratis, tetapi tentang mengelola rasa kolektif bangsa yang sangat peka. Rakyat Indonesia bereaksi bukan hanya pada isi kebijakan, tetapi pada cara bicara, nada suara, gestur, dan rasa hormat yang mereka rasakan.
Indonesia adalah negara yang unik. Kita tidak miskin empati, tetapi mudah lelah secara emosional. Kita tidak anti kritik, tetapi sangat sensitif terhadap cara kritik disampaikan. Karena itu kepemimpinan di Indonesia selalu menantang sekaligus khas. Pemimpin harus mampu menenangkan tanpa mematikan keberanian, menegaskan tanpa merendahkan, dan merangkul tanpa kehilangan arah.
Di era media sosial, tantangan itu berlipat. Algoritma memanen emosi dan menyebarkannya kembali dalam bentuk kemarahan kolektif. Konten yang memicu amarah lebih cepat viral dibanding yang mengajak berpikir. Dalam situasi seperti ini, pemimpin tidak boleh ikut menjadi bagian dari mesin pemanas emosi. Ia harus menjadi penyangga, penjernih, dan penuntun arah. Sekali pemimpin ikut memelihara kebisingan, bangsa yang sensitif ini akan kehilangan pegangan.
Seni Merawat Manusia
Memimpin Indonesia bukan sekadar soal mengelola kebijakan, angka, dan target pembangunan. Memimpin Indonesia adalah soal mengelola rasa jutaan manusia yang sangat empatik, sangat sensitif, dan sangat bergantung pada kepercayaan.
Bangsa ini bukan bangsa yang keras, tetapi bangsa yang mudah terluka. Bukan bangsa yang anti kritik, tetapi bangsa yang sangat peka terhadap cara diperlakukan. Karena itu, kepemimpinan di Indonesia selalu menuntut lebih dari sekadar kecerdasan teknis. Ia menuntut kedewasaan emosional.
Indonesia yang diakui dunia sebagai bangsa paling bahagia menurut Harvard Global Flourishing Study 2025 sesungguhnya sedang memberi pesan halus kepada para pemimpinnya. Kebahagiaan itu lahir bukan dari kemewahan, tetapi dari kebersamaan. Bukan dari dominasi, tetapi dari rasa saling memiliki. Modal sosial ini besar, tetapi rapuh. Ia bisa tumbuh subur bila dirawat dengan empati dan keadilan, tetapi bisa runtuh bila diperlakukan dengan arogansi dan pengabaian.
Di negeri yang sangat perasa ini, kata-kata pemimpin lebih berat daripada yang sering disadari. Nada bicara, pilihan bahasa, dan sikap dalam menghadapi kritik menentukan apakah empati rakyat akan menguat atau berubah menjadi amarah. Pemimpin yang gagal membaca rasa akan mudah memicu luka kolektif, sementara pemimpin yang mampu menenangkan tanpa merendahkan akan memperkuat kebahagiaan yang selama ini menjadi kekuatan kita.
Karena itu, tantangan terbesar kepemimpinan Indonesia hari ini bukan hanya bagaimana membuat rakyat patuh, tetapi bagaimana membuat rakyat merasa dihargai. Bukan hanya bagaimana menjaga stabilitas, tetapi bagaimana menjaga kewarasan bersama. Di bangsa yang mudah menolong sekaligus mudah tersulut ini, kepemimpinan sejati bukan tentang siapa yang paling keras suaranya, melainkan siapa yang paling mampu menjaga empati tetap hidup tanpa membiarkan kemarahan mengambil alih arah bangsa.
Jika paradoks ini mampu dipahami dan dikelola, Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai bangsa yang paling bahagia di dunia, tetapi juga sebagai bangsa yang matang secara emosional. Dan di situlah kepemimpinan menemukan maknanya yang paling hakiki, bukan sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai seni merawat manusia.
Tag: #tantangan #memimpin #indonesia #bangsa #yang #bahagia #sekaligus #mudah #tersinggung