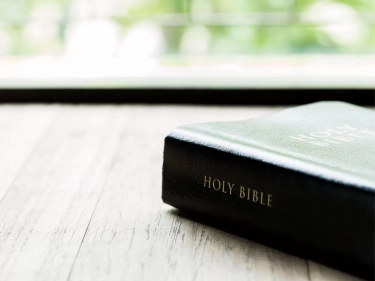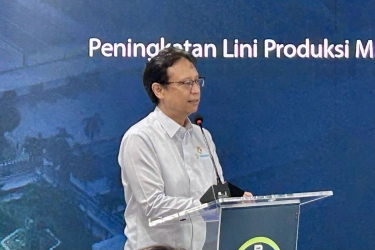Membongkar ''Clownmanship'' di Pilpres 2024
GIBRAN Rakabuming Raka disorot setelah merespons Mahfud MD di debat cawapres, Minggu (21/1/24), dengan gestur celingukan.
Ia melakukannya sebagai dalih bahwa jawaban Mahfud tentang greenflation – lagi-lagi Gibran tidak menjelaskan secara komprehensif istilah spesifik dalam pertanyaannya, meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membarui aturannya soal ini – tidak relevan.
“Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya kok enggak ketemu jawabannya,” begitu ujaran Gibran yang membarengi gestur celingukannya.
Gestur Gibran itu pasti familiar di kalangan pelaku maupun penikmat stand-up comedy di Indonesia.
Biasanya, hal itu dilakukan oleh seorang komika untuk menyinggung penampil sebelumnya yang gagal mendapatkan tawa dari penonton (disebut juga bombing atau “anyep”).
“Saya sedang nyari-nyari komika tadi lucunya di mana.” Lebih kurang, begitulah ilustrasi dalam konteks yang penulis sebut di atas.
Berdasarkan pernyataan resmi dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (22/1/24), gerakan tersebut memang upaya putra Presiden Joko Widodo yang didesain untuk membuat panggung politik nasional menjadi lebih santai.
Di ajang Pilpres 2024, Prabowo-Gibran memang pasangan yang terdepan dalam memfamiliarkan masyarakat Indonesia dengan gestur, pernyataan, hingga gimmick menghibur: dari berjoget, mencitrakan diri dengan tokoh-tokoh anime tertentu, sampai menggunakan alat peraga kampanye berbasis artificial intelligence sehingga pasangan tersebut lebih tampak seperti tokoh film animasi daripada politikus.
Pastinya, Prabowo-Gibran bukan kontestan pertama yang memakai gimmick menghibur dalam kontestasi Pilpres.
Namun jika menganggap mereka politikus yang tulus menghibur lewat gimmick-gimmick politiknya, jelas keliru. Prabowo-Gibran sedang tunjukkan sebenarnya adalah clownmanship, yaitu penggunaan strategi menghibur untuk menghindari atau menutupi sesuatu.
"Clownmanship"
Nick Butler, associate professor Stockholm University, dalam The Trouble with Jokes (2023), mendefinisikan secara harfiah bahwa clownmanship adalah perpaduan cacat antara “badut” (clown) dan negarawan (statemanship).
Sebenarnya, penulis belum sepenuhnya cocok dengan terminologi ini karena cakupannya masih terlalu sempit.
Pertama, pelabelan “clown” atau “badut” bagi para politikus inkompeten bakal makin mendegradasi badut sebagai profesi dan pelaku budaya yang perannya bagi peradaban sudah menjejak sedari tahun 2400 SM.
Rasanya tidak adil saja jika politikus inkompeten disamakan dengan court jester atau badut istana macam Abu Nawas, Nasruddin Hoja, atau Will Sommers, yang punya keahlian untuk menyambungkan aspirasi rakyat ke kerajaan dan menyadarkan raja atau ratu yang zalim lewat komunikasi humoristis.
Di era modern kini pun, badut sebenarnya sedang direstorasi marwahnya. Di bidang kesehatan, kehadiran clown doctor yang dipioniri dr. Patch Adams telah diakui sebagai intervensi yang positif untuk mendongkrak mood pasien dalam proses pemulihan.
Bahkan, keluarga pasien hingga tenaga medis bisa ikut diuntungkan secara psikis.
Sementara di ranah pendidikan, filosofi clown teacher juga sedang dipopulerkan untuk menciptakan atmosfer pembelajaran yang lebih progresif.
Nilai positif dari badut, seperti antusiasme hingga fleksibilitas, dianggap bermanfaat saat dipraktikkan dalam kelas (McCusker, 2023).
Kedua, digunakannya kata “statesman” atau “negarawan” amat membatasi klasifikasi tokoh yang bisa ditempeli cap clownmanship itu sendiri.
Barangkali, lebih baik diartikan politikus secara umum saja, alih-alih merujuk pada negarawan yang secara definitif merupakan figur yang ahli dalam kenegaraan atau pemimpin yang mampu mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan.
Namun, karena penulis belum bisa menemukan padanan untuk istilah clownmanship dari fenomena yang juga masih hangat ini, tanpa ada niatan untuk merendahkan badut dan negarawan, izinkan penulis menggunakan terminologi tersebut untuk menjelaskan fenomena gawat yang terjadi secara global dan sedang menjangkiti kita ini.
Bahaya Clownmanship
Kini, clownmanship tercatat sebagai gejala destruktif humor dalam konteks perpolitikan. Dari The Trouble with Jokes (2023), clownmanship dijadikan strategi politikus untuk menutupi hal tertentu atau melepaskan diri dari tanggung jawab.
Kebetulan, tiga ciri utama clownmanship mengarah pada jejak-jejak yang ditinggalkan pasangan Prabowo-Gibran.
Pertama, tokoh clownmanship sama sekali tidak ragu dan malu untuk menutupi kurangnya pengalaman dan wawasannya – bahkan menabrak konstitusi – dengan gimmick atau pernyataan yang sama sekali tidak menyentuh substansinya.
Contohnya, setiap ditanya soal pelanggaran etik paman Gibran sekaligus ketua Mahkamah Konstitusi yang sudah dicopot, Anwar Usman – yang mengabulkan gugatan atas UU Nomor 7 tahun 2017 mengenai batas usia capres-cawapres – pasangan tersebut memilih untuk memberikan jawaban normatif: “menyerahkan kepada masyarakat”, “kalau rakyat tidak suka Prabowo-Gibran, jangan pilih!”, dan sebagainya.
Yang dipermasalahkan masyarakat sebenarnya adalah syarat pendaftarannya yang menabrak konstitusi, bukan perkara dipilih atau tidaknya di bilik suara setelah terdaftar. Sebab begitu sudah menjadi peserta resmi, tiap paslon pastinya punya peluang untuk menang.
Strategi ini mirip seperti yang dilakukan Boris Johnson sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris.
Di periode keduanya sebagai wali kota London, ia ditanya oleh jurnalis yang ingin tahu benarkah ia politikus yang jauh dari rakyat dan tinggal di menara gading: berapa harga sebungkus roti tawar?
Johnson tampak kesulitan menjawabnya. Lalu ia pun menawarkan jawaban pengganti, “Tapi saya bisa memberi tahu Anda harga sebotol wine. Gimana kalau begitu?”
Kedua, clownmanship lekat dengan sikap dan humor yang agresif. Donald Trump, sebenarnya, bukan presiden yang anti dengan humor.
Saat dicermati, justru dia sering menyampaikan komentar humoristis. Hanya saja, gaya humornya cenderung menyerang, melecehkan, dan merendahkan pihak-pihak lain – mulai dari lawan politiknya, media massa, bahkan kaum perempuan dan imigran, sehingga ujarannya terasa bukan seperti humor, melainkan kecaman dan ujaran kebencian.
Secara strategi retorika, Prabowo beberapa kali menunjukkan agresivitasnya lewat humor. Misalnya, saat ia bercanda di hadapan kader-kader Gerindra saat Rakornas dengan perkataan “ndasmu etik”, sebagai respons atas pertanyaan Anies Baswedan tentang pelanggaran etik di keputusan MK saat debat capres putaran pertama (15/12/23).
Atau, ketika ia meledek gagasan Ganjar Pranowo bahwa internet gratis lebih penting daripada programnya, yakni makan siang gratis untuk anak-anak (20/1/24).
Prabowo di sana menyebut pengusung program internet gratis atau capres yang merasa program internet gratis lebih bagus daripada makan siang gratis “berotak lambat” dan “tidak cocok jadi pemimpin”.
Pernyataan-pernyataan tersebut tentu menjadi kontradiktif dengan pencitraan “gemoy” yang coba dibangun oleh timnya.
Tampaknya, pencitraan yang dipilih itu berbeda dengan karakter keseharian Prabowo, sehingga dalam beberapa momen, yang bersangkutan jadi kelepasan tidak bisa mengontrol emosinya.
Terakhir, pelaku clownmanship tak ragu dan tanpa malu-malu bertingkah, bahkan bersirkus layaknya badut demi kepentingannya.
Soal ini jelas, gimmick berjoget Prabowo dan celingukan Gibran adalah teknik clownmanship untuk menutupi kampanye yang kurang substantif, mengandalkan dialog, dan mengejar viralitas di media sosial semata.
Keputusan Prabowo untuk menanggalkan identitasnya sebagai anggota militer patut diduga juga berkaitan dengan pelanggengan kepentingannya agar masyarakat tidak teringat akan rekam jejak kasus penculikan aktivis.
Di awal, penulis menggunakan konsep dari Butler agar kita waspada terhadap ciri-ciri pemimpin problematik yang mempraktikkan clownmanship untuk sekadar meraih suara.
Namun ketika disinkronkan dengan fenomena di Indonesia, ketika clownmanship bisa dijadikan riasan untuk menutupi keterbatasan pengalaman, wawasan, pelanggaran etika, hingga praktik kampanye yang kurang substantif, bisa dibilang, kitalah yang sekarang menguliahi Butler.
Sebab clownmanship di Indonesia ternyata justru lebih canggih karena sudah dipraktikkan oleh capres-cawapresnya sekaligus dan menghilirisasi.