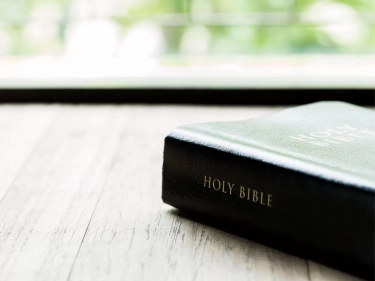Guru Besar, Dus Keberpihakan Besar
DUA panggung yang terpisah ratusan kilometer menyedot perhatian publik pada 15 Januari 2026 lalu. Pertama berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan kedua digelar di Balai Senat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Di panggung pertama, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 1.200 akademisi ---sejumlah media massa melaporkan mereka memiliki atribusi rektor, dekan hingga guru besar. Orang kampus ini berkecimpung di bidang sosial humaniora.
Di panggung kedua, seorang anak bangsa, Zainal Arifin Mochtar, dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang hukum kelembagaan negara Fakultas Hukum UGM.
Dengan itu ia menyandang gelar profesor--atribusi yang menandakan kecemerlangan seorang akademikus dan menggambarkan perjalanan intelektual tokoh yang identik dengan aktivitas dan advokasi antikorupsi itu.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan orang kampus, terlebih dengan 1.200 orang, terbilang kolosal, bersejarah dan menandai relasi penguasa dengan akademisi yang dibalut dalam tajuk dialog.
Sejak menakhodai Republik, 20 Oktober 2024, Prabowo suka mengumpulkan menteri, kepala daerah hingga orang kampus dalam jumlah besar di satu lokasi. Tidak biasanya kepala daerah hasil Pilkada 2024 dilantik secara berbarengan dan serentak di Jakarta.
Para menteri dikumpulkan di Hambalang, lalu Magelang untuk memperoleh materi pembekalan dan tak lupa visi dan misi besar dari presiden.
Pada kasus menteri, itu dilakukan karena menteri adalah pembantu presiden. Dalam kasus kepala daerah, ini agak mengejutkan sebab mereka berasal dari partai politik berbeda, dan punya agenda serta janji-janji tak sama dengan presiden ketika berlaga di Pilkada.
Hadirnya 1.200 orang kampus di Istana Kepresidenan mungkin bagus untuk menyimak kiblat kebijakan Presiden Prabowo.
Dengan mengenal visi dan misi presiden, akademikus di kampus diharapkan memahami arah kebijakan presiden memimpin negara ini di tengah geopolitik yang terus berubah, khususnya ditandai gebrakan ugal-ugalan Amerika Serikat menculik Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, karena tuduhan kasus narkoterorisme.
Berkat pertemuan di Istana itu, Presiden Prabowo bakal menambahkan dana riset sebesar Rp 4 triliun. Naik 50 persen dari pagu awal. Jadi, kini dana riset untuk perguruan tinggi naik menjadi Rp 12 triliun.
Ini layak disyukuri kendati dana itu cuma 0,51 persen dari APBN. Jangan bandingkan dengan dana riset Korea Selatan yang mencapai 4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Indonesia pun bercita-cita dapat mengalokasikan dana riset hingga 1 persen PDB di masa depan.
Dana riset sangat penting untuk kampus. Namun, ada yang lebih penting dari itu, yakni independensi dan keberpihakan orang kampus.
Akademisi kampus adalah bagian yang absah dari golongan cendekiawan. Ini golongan yang berdiri--secara metaforik--di atas menara gading dalam konstruksi Julien Benda (La trahision des clercs).
Golongan ini seyogianya menjaga jarak dengan organisasi politik, termasuk penguasa. Dengan menjaga jarak, kaum cendekiawan akan lebih jernih dalam melihat situasi dan kondisi negara dan bangsanya. Sang cendekiawan bakal obyektif, tidak bias, dan terbelit konflik kepentingan.
Dukungan negara dalam bentuk dana riset itu kewajaran belaka dalam memajukan perguruan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi dan lain-lain).
Dengan itu, perguruan tinggi tak boleh dikatakan sedang "berutang" kepada negara dan membayarnya dalam bentuk "kesetiaan" atau loyalitas kepada mereka yang berkuasa.
Sebab, loyalitas tertinggi kampus adalah kepada negara dan masyarakat. Dan itu tak tergantung kepada siapa yang sedang berkuasa--terlebih kekuasaan eksekutif berganti saban lima tahun.
Dengan elegan Mohammad Hatta mengatakan "dasar bagi berdirinya universitas adalah bahwa ia menjadi jembatan antara pengetahuan dan sari penghidupan. Universitas memberi petunjuk, tapi petunjuk yang disertai dengan ciptaan" (Cendekiawan dan Politik,
LP3ES, 1983).
Riset yang disokong pembiayaan ideal oleh negara bakal membantu perguruan tinggi untuk mencapai ucapan proklamator: Jembatan antara pengetahuan dan sari penghidupan.
Outputnya adalah apa yang disebut oleh Hatta sebagai "ciptaan"--sebuah inovasi, temuan yang bermanfaat untuk masyarakat.
Sebagian orang sangsi pertemuan 1.200 orang kampus dengan presiden itu sebagai dialog antara dua pihak. Besarnya jumlah orang kampus yang hadir, dalam pandangan ini, tak memungkinkan terjadi dialog yang intensif.
Kalau benar ada dialog, itu semata-mata dialog terbatas antara "perwakilan" perguruan tinggi dengan presiden.
Dan masalah setiap kampus sesungguhnya tak dapat diwakili oleh "perwakilan" yang tidak representatif (baca: mereka yang bicara) itu. Pertemuan tadi lebih tepat disebut acara di mana presiden ingin bicara kepada orang kampus.
Saat 1.200 orang kampus dari seluruh Indonesia berkumpul di Istana Kepresidenan Jakarta, Zainal Arifin Mochtar tak ada di sana.
Hari itu, Uceng, begitu Zainal biasa dipanggil, menghadiri pengukuhan dirinya sebagai guru besar. Ia berpidato tentang "Konservatisme yang Menguat dan Independensi Lembaga Negara yang Melemah: Mencari Relasi dan Mendedah Jalan Keluar".
Pidato itu bukan berisi kabar baik, sebaliknya suram. Ia antara lain menyoroti tumbuhnya lembaga negara independen selepas Reformasi 1998.
Setelah trauma panjang atas otoritarianisme Orde Baru, negeri kita ingin memperkuat fungsi checks and balances terhadap lembaga eksekutif dan legislatif.
Maka tak cukup empat cabang kekuasaan, termasuk pers, berkembang pula konsep "the new separation of power" hingga "the newest separation of power".
Komnas HAM telah berdiri lima tahun sebelum Soeharto lengser. Di masa reformasi, giliran KPU, KPK, MK, KY, KPI hingga Ombudsman berdiri. Kehadiran lembaga-lembaga ini, menurut Zainal, tak lain adalah bentuk rebalancing of power.
Mahkamah Konstitusi contohnya dapat dikatakan 'mengurangi' peran eksekutif dan legislatif dalam kredo "negative legislator".
Undang-Undang yang dinilai melanggar konstitusi akan dibatalkan oleh MK sebagai benteng konstitusi. Dalam kasus atau perkara tertentu, MK bahkan melampaui (ultra petitum) apa yang diminta oleh pihak yang menempuh judicial review.
Putusan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal hingga putusan wakil menteri dilarang rangkap jabatan (komisaris BUMN) dapat juga dipahami sebagai fungsi checks and balances terhadap pemerintah dan DPR sebagai pembuat Undang-Undang.
MK berperan sebagai benteng terakhir yang mengembalikan Undang-Undang agar tidak melenceng dari konstitusi.
Namun, belakangan segalanya berubah. Menurut Zainal, populisme dan konservatisme menguat sehingga turut membantu strategi politik yang membingkai demokrasi prosedural.
Ia menyaksikan pelemahan lembaga independen melalui mekanisme regulasi, anggaran, dan kooptasi kelembagaan. Alhasil posisi dan eksistensi lembaga unelected (tidak dipilih lewat pemilihan umum) itu sangat tergantung pada keputusan politik di DPR serta tafsir hukum MK.
Kecenderungan ini mengeras dalam sepuluh tahun Joko Widodo. KPK tak lagi superbody, keberadaannya dilemahkan lewat revisi UU KPK tahun 2019. Bahkan independensinya copot karena telah jadi rumpun eksekutif.
Pasal 1 ayat (3) UU KPK hasil revisi menyebutkan, KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pasca-2019, KPK tak lagi sama dengan KPK periode 2003-2018.
Mengapa? Karena eksekutif dan legislatif ingin KPK berubah. Sebetulnya angin topan yang hendak melemahkan KPK telah mencuat di masa cicak versus buaya jilid satu di masa Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, SBY correct dalam meletakkan posisi serta peran KPK yang awalnya dirancang sebagai lembaga ad hoc ini. Dan kini KPK berada pada masa di mana dukungan untuknya memudar secara drastis.
Bukan KPK saja, lembaga unelected lainnya berada dalam situasi yang sebangun dengan ucapan Sukarno dekade 1960-an: Vivere pericoloso--hidup (tapi) menyerempet bahaya.
Mereka bisa kapan saja kehilangan peran vital jika kekuatan politik elected (terpilih via pemilu) merasa kurang atau tidak membutuhkan lagi.
Zainal menegaskan rezim konservatif cenderung mengonsolidasikan kekuasaan eksekutif dan meminimalkan peran lembaga pengawas sebagai bentuk kontrol politik.
"Apakah ini khusus Indonesia? Tidak. Ini adalah kenyataan global. Ia terjadi di begitu banyak negara, seperti Polandia, Turkiye, Amerika Serikat, Hungaria, bahkan tetangga paling dekat kita, Filipina,” paparnya (Hukumonline, 15/1/2026).
Di negeri kita, paparan Zainal itu bukan lagi hipotesis. Kini lembaga eksekutif sangat kuat. Seluruh parpol di DPR tidak mengumumkan diri sebagai kekuatan oposisi dengan dalih formalistik yang segera rontok jika digugat.
Fungsi checks and balances oleh DPR hanya terjadi jika partai politik merasa bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah dalam isu atau topik tertentu.
Dalam arsitektur koalisi gemuk yang menjangkau seluruh parpol pemilik kursi di DPR, fungsi kontrol dan kritik lembaga yang mengagregasi dan mewakili aspirasi rakyat (konstituen) ini mati suri.
Tepat di sini, Zainal benar. Perkawinan populisme dan konservatisme menjadi kombinasi yang bagus untuk membawa demokrasi kita sekarat.
Apa yang bisa dikatakan dengan ide pemilihan kepala daerah via DPRD tempo hari? Ide ini tak lain karena partai politik terpesona dengan konservatisme (baca: Pilkada via DPRD di masa Orde Baru yang diklaim murah meskipun kenyataannya diselimuti politik uang dan merampas kedaulatan rakyat).
Awalnya ide itu muncul dari presiden, lalu partai-partai yang tergabung dalam koalisi setuju. Bahkan Partai Demokrat, yang terindikasi berubah haluan, tampak senada dengan demokrasi tak langsung ini.
Seperti cek ombak, ketika ide ini ditolak oleh mayoritas publik, kekuatan politik mundur teratur. Sulit ditolak bahwa ide ini sebetulnya merupakan kepanjangan tangan dari "demokrasi komando" (meminjam istilah Tempo).
Inilah demokrasi yang langgam serta aturannya mengikuti kemauan dan kode dari pemimpin tertinggi.
Dalam situasi demikian, negeri kita perlu keberpihakan besar dari guru besar serta mereka yang terhimpun dalam golongan cendekiawan.
Pada 1976, Sekjen Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, Letnan Jenderal Rachmat Kartakusuma, membandingkan resi dengan cendekiawan. Resi bertumpu pada intuisi, sementara cendekiawan bertopang pada rasio (akal).
Perkakasnya adalah ilmu yang memiliki fungsi sosial. Karena itu, cendekiawan punya kewajiban moral untuk mengabdikan kemampuan dan kecakapannya demi kemajuan masyarakat.
"Bagi saya menjadi profesor itu relatif hanya persoalan administratif. Tapi memiliki sikap dan kiprah intelektual serta tanggung jawab sebagai seorang profesor sesungguhnya relatif sulit," ucap Zainal di akhir pidato pengukuhannya sebagai guru besar.
Dia punya harapan agar para profesor berperan sebagai intelektual organik yang mau bekerja untuk kaum tertindas---mereka yang mendapat perwakilan tak adil dan sewenang-wenang.
Kata kunci yang dibagi oleh aktor Dirty Vote itu adalah keberpihakan. Satu hal yang gampang diucapkan, tapi sulit dikerjakan secara ajeg. Saya tahu seruan itu, pertama dan terpokok, adalah untuk dia sendiri.
Satu Zainal mungkin tak bisa bikin perubahan. Namun, jutaan kaum cendekiawan atau intelektual dapat mengubah bangsa.
Peganglah selalu pesan Bung Hatta ini. Kaum intelektual adalah bagian dari rakyat, warga negara terpelajar yang tahu menimbang baik dan buruk, benar dan salah.
Dalam Indonesia yang mengambil jalan demokrasi, ia ikut serta bertanggung jawab untuk memperbaiki nasib bangsa. Itulah panggilannya, dan begitulah keberpihakan seorang intelektual harus diarahkan.
Tag: #guru #besar #keberpihakan #besar