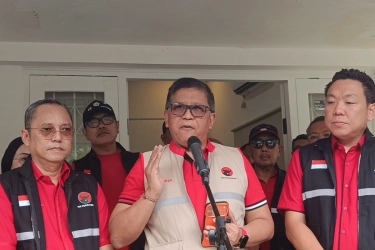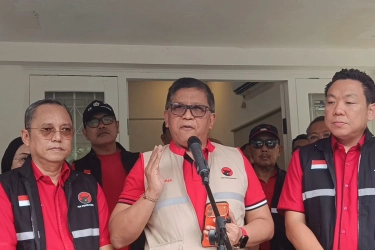Memaknai Demonstrasi Indonesia Gelap (Bagian II)
PIDATO-pidato Soekarno yang menggugah semangat kebangsaan dan visi Pancasila sebagai dasar negara bukan sekadar rangkaian kata-kata politik.
Ini adalah pancaran dari pemahaman mendalam bahwa bangsa ini lebih dari sekadar sekumpulan individu, melainkan entitas hidup dengan jiwa kolektif yang merangkul seluruh elemen, bernapas, dan bergerak bersama dalam sejarah.
Julukan "penyambung lidah rakyat Indonesia" tidak hanya menggambarkan Soekarno sebagai orator ulung, tetapi juga sebagai juru bicara dari jiwa kolektif bangsa, yang menyuarakan aspirasi rakyat dengan kejelasan dan keyakinan yang luar biasa.
Melalui kata-katanya, Soekarno membangkitkan semangat yang terpendam, menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam visi yang sama.
Kepemimpinan Soekarno menegaskan betapa pentingnya Pemahaman Tingkat Keempat sebagai kekuatan pemersatu yang mampu melampaui perbedaan dan tantangan.
Dengan visi yang menyeluruh dan kemampuan untuk merespons kebutuhan rakyat secara mendalam, Soekarno berhasil mengarahkan Indonesia menuju kemerdekaan dan membangun dasar negara yang kuat.
Tanpa jenis kepemimpinan yang memahami kedalaman ini, Indonesia berisiko terjebak dalam siklus konflik dan ketidakstabilan yang terus berulang.
Hanya melalui kesadaran lebih tinggi, yang menempatkan jiwa kolektif bangsa di atas kepentingan sempit, kita dapat melangkah maju menuju kemajuan dan kesejahteraan nasional yang sejati, membentuk masa depan yang tumbuh dari kebijaksanaan dan aspirasi bersama (from the emerging future).
Belajar dari Krisis 1998
Sebagai “veteran” aktivis Reformasi 1998, penulis mencatat ada satu terminologi yang semakin sering diungkapkan pada masa itu sebelum terjadinya demonstrasi besar di seluruh Indonesia, yaitu “krisis kepercayaan”.
Seperti kita tahu, kepercayaan (trust) adalah hal yang paling mahal di dunia ini. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun kepercayaan, tapi hanya dalam sekejap ia bisa runtuh.
Sebelum gelombang demonstrasi mahasiswa pecah pada 1998, serangkaian kebijakan ekonomi yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, ditambah krisis finansial yang melanda Asia, menyebabkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat itu.
Dalam situasi saat ini, tanda-tanda awal kontroversi kebijakan seperti kenaikan PPN 12 persen serta pembagian elpiji subsidi yang akhirnya dibatalkan telah mempercepat erosi kepercayaan masyarakat.
Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, perbedaan mendasar antara demonstrasi 1998 dan demonstrasi mahasiswa saat ini adalah kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial.
Teknologi komunikasi yang semakin canggih mempercepat mobilisasi massa, baik secara fisik maupun wacana.
Namun, bersamaan dengan itu, ancaman hoaks dan manipulasi informasi berbasis kecerdasan buatan seperti deepfake juga memperumit dinamika politik.
Lalu bagaimana cara meredam gejolak demonstrasi mahasiswa ini agar tidak membesar dan melebar? Jawabannya tidak lain adalah melalui pendekatan yang lebih reflektif dan berbasis dialog.
Pemerintah harus melepaskan berbagai apriori, membuka diri terhadap kritik, serta mendengarkan secara seksama aspirasi mahasiswa dengan penuh empati.
Dialog yang jujur dan bermakna antara mahasiswa dan pemerintah bukan sekadar alat diplomasi, tetapi juga sarana transformasi sosial yang fundamental.
Pemerintah harus bertransformasi dengan meningkatkan kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, sementara mahasiswa juga dapat memahami konteks kebijakan yang diterapkan.
Di sinilah titik temu bisa dicapai: bukan sekadar adu argumentasi, tetapi mencari solusi bersama.
Dalam konteks ini, pemahaman tingkat keempat seperti yang diperkenalkan oleh Otto Scharmer menjadi sangat relevan.
Pemimpin yang memiliki kesadaran tingkat keempat tidak hanya bertindak berdasarkan data atau pertimbangan teknokratis semata, tetapi juga mampu memahami aspirasi rakyat dengan empati dan kebijaksanaan.
Kepemimpinan semacam ini tidak melihat mahasiswa sebagai ancaman atau oposisi, melainkan sebagai bagian dari ekosistem demokrasi yang harus dirangkul dan diajak berdialog.
Represi terhadap demonstrasi hanya akan mempercepat erosi kepercayaan publik, seperti yang terjadi pada 1998.
Sejarah telah mengajarkan bahwa gerakan mahasiswa, baik pada 1966 maupun 1998, telah menjadi titik balik bagi perjalanan politik Indonesia.
Cukuplah kita belajar dari dua peristiwa besar itu agar tidak perlu mengalami gelombang krisis yang sama di masa depan.
Seperti yang dikatakan filsuf George Santayana, "Mereka yang tidak belajar dari sejarah akan terkutuk mengulanginya lagi."
Untuk itu, kepemimpinan yang berlandaskan pemahaman tingkat keempat harus menjadi acuan dalam menghadapi dinamika sosial-politik saat ini.
Kepekaan terhadap tuntutan rakyat, kemampuan untuk merespons dengan bijaksana, serta kesediaan untuk membangun kepercayaan yang autentik adalah kunci bagi stabilitas dan keberlanjutan bangsa.
Krisis kepercayaan bisa dihindari jika pemimpin memahami bahwa kepemimpinan bukan sekadar tentang kekuasaan, tetapi juga tentang merangkul aspirasi kolektif menuju masa depan yang lebih baik.