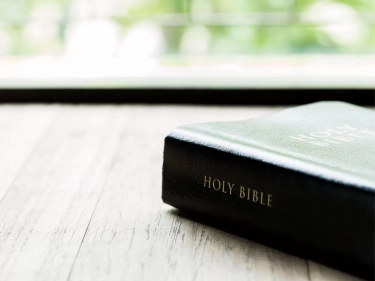Menakar Senjakala Jamaah Islamiyah
SEJARAH sering kali berulang dengan cara yang tak terduga. Di penghujung Juni 2024, pernyataan mengejutkan datang dari Jamaah Islamiyah (JI) Indonesia, kelompok yang selama dua dekade terakhir menjadi subjek perdebatan dan pengawasan ketat di berbagai level.
Pengumuman resmi tentang pembubaran organisasi ini seolah menandai babak baru dalam dinamika kelompok yang telah lama dianggap sebagai salah satu jaringan jihad paling berpengaruh di Asia Tenggara.
Peristiwa ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Sejak dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada 2008 dan dimasukkan ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT) pada 2018, JI telah menghadapi berbagai tekanan, baik dari dalam maupun luar.
Enam bulan setelah pengumuman pertama, pada Desember 2024, JI kembali mengumumkan pembubaran massal dalam forum resmi yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara.
Hingga kini, tercatat sekitar 8.000 anggota yang telah menyatakan diri meninggalkan organisasi tersebut.
Dalam waktu yang hampir bersamaan, dunia menyaksikan kemenangan Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) di Suriah. Organisasi yang semula merupakan cabang al-Qaeda itu berhasil menggulingkan rezim Bashar al-Assad.
Keberhasilan HTS tidak hanya mengubah peta politik Suriah, tetapi juga membawa dampak lebih luas terhadap gerakan jihad global.
Kemenangan tersebut menjadi bukti bahwa strategi yang fokus pada lokalitas, dipadukan dengan pendekatan politik pragmatis, mampu menciptakan legitimasi dan dukungan publik, bahkan di tengah tekanan geopolitik.
Dari hibernasi ke reposisi
Keputusan JI untuk membubarkan diri dua kali dalam satu tahun bukan sekadar peristiwa biasa, melainkan pola adaptasi yang halus, cerdas, dan sarat teka-teki.
Di saat publik masih menelaah makna di balik pembubaran ini, muncul inisiatif dari Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, yang menggulirkan wacana pendataan narapidana untuk diberikan amnesti dan abolisi.
Umumnya skema ini memiliki dua model: bisa menjadi langkah rekonsiliasi menyeluruh atau justru mekanisme penyortiran untuk menentukan siapa saja yang layak mendapatkan grasi dari presiden.
Dinamika ini semakin kompleks jika melihat dari perspektif kelompok lain yang masih terjerat proses hukum.
Potensi kecemburuan di kalangan kelompok teror lainnya sangat mungkin terjadi, terutama bagi mereka yang merasa diperlakukan secara berbeda dalam sistem peradilan.
Sebab di Indonesia, narapidana kasus terorisme bukan hanya dari jaringan JI, tetapi juga dari berbagai kelompok lain yang memiliki spektrum ideologi dan strategi berbeda.
Dengan demikian, pembebasan ini berisiko menciptakan efek domino; bisa menjadi model deradikalisasi yang sukses, tetapi juga dapat memicu ketidakstabilan baru jika kebijakan ini dianggap tidak adil.
Di sisi lain, kita harus kembali pada sejarah yang menunjukkan bahwa JI bukanlah organisasi yang mudah benar-benar menghilang.
Mereka telah membuktikan kapasitasnya untuk bertahan melalui fase-fase represi, baik dengan menyesuaikan narasi maupun memperkuat struktur internal.
Jika kemenangan HTS menawarkan pelajaran baru, maka JI juga berpotensi beralih dari pola jihad transnasional yang menjadi ciri khas Al-Qaeda menuju pendekatan yang lebih lokal.
Kemenangan HTS di Suriah merupakan tonggak sejarah yang mencerminkan keberhasilan reposisi strategis.
Setelah memisahkan diri dari Al-Qaeda, HTS tidak lagi memproyeksikan dirinya sebagai gerakan transnasional, tetapi sebagai aktor lokal yang berfokus pada isu-isu domestik.
Mereka membangun aliansi dengan kelompok-kelompok lokal, memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim Assad dan mengurangi elemen ideologis yang dianggap terlalu ekstrem oleh masyarakat umum.
Pendekatan ini memberikan legitimasi bagi HTS di mata pendukung lokal, sekaligus menciptakan ruang gerak baru untuk bertahan di bawah radar tekanan internasional.
Transformasi HTS bukan hanya strategi militer, tetapi juga langkah politik yang matang; menggabungkan ideologi jihad dengan pragmatisme politik.
Pola inilah yang kemungkinan besar menjadi inspirasi bagi kelompok teror mana pun dalam membentuk ulang identitasnya.
Kemenangan HTS tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik global. Cerminan bagaimana gerakan jihad semakin cerdas dalam menyesuaikan diri dengan konteks lokal.
Jika Taliban di Afghanistan mengajarkan strategi memanfaatkan kekosongan kekuasaan domestik, maka HTS menunjukkan bahwa keberhasilan juga bergantung pada kemampuan membangun dukungan masyarakat melalui pendekatan lebih pragmatis.
Kemenangan HTS menawarkan model baru yang berpotensi untuk diikuti faksi-faksi teror lainnya.
Indonesia harus mewaspadai kemungkinan bahwa pembubaran JI hanyalah fase hibernasi sebelum mereka muncul kembali dengan strategi yang lebih matang, lebih relevan secara lokal, dan lebih sulit diantisipasi.
Dengan mengumumkan pembubaran secara formal, JI memberikan kesan meninggalkan masa lalu yang terkait dengan tindakan kekerasan dan ekstremisme.
Langkah ini berpotensi menarik simpati dari pemerintah dan masyarakat yang mungkin memandangnya sebagai sinyal rekonsiliasi.
Alih-alih berfokus pada aktivitas militer seperti sebelumnya, JI dapat mengarahkan kembali anggotanya untuk membangun komunitas berbasis nilai-nilai keagamaan yang lebih fleksibel di permukaan.
Strategi ini memungkinkan mereka mempertahankan relevansi sambil memperkuat jaringan sosial yang dapat diaktivasi di masa depan.
Strategi proaktif atau perangkap kebijakan?
Kemampuan Indonesia untuk tidak hanya menghindari menjadi bagian dari penggalangan narasi JI, tetapi juga mengambil peran aktif dalam mengelola dan mengarahkan transformasi organisasi ini, menjadi ujian besar bagi kebijakan keamanan nasional.
Pembubaran formal JI pada 2024, yang tampaknya membuka peluang bagi reorganisasi mereka dalam bentuk baru, adalah momen kritis yang memerlukan pengawasan dan strategi yang cermat.
Jika negara hanya menjadi objek dalam narasi yang dikelola JI—misalnya, melalui kebijakan yang dimanfaatkan untuk membangun citra positif—Indonesia berisiko menjadi bagian dari agenda JI tanpa sadar.
Dalam skenario ini, negara dapat terjebak dalam retorika "rekonsiliasi" atau "rehabilitasi" yang sejatinya merupakan taktik untuk mengaburkan jejak dan mempersiapkan reposisi strategis.
Akibatnya, potensi kebangkitan JI dalam bentuk baru yang lebih terselubung akan semakin berbahaya.
Sebaliknya, jika Indonesia mampu memanfaatkan pembubaran ini untuk menggalang kendali terhadap eks-JI, negara dapat memainkan peran proaktif dalam menentukan arah transformasi mereka.
Dengan memanfaatkan kebijakan reintegrasi yang tegas, tapi terukur, pemerintah dapat memastikan bahwa mantan anggota JI benar-benar meninggalkan ideologi esktremnya dan tidak kembali ke aktivitas terlarang.
Hal ini mencakup pengawasan ketat terhadap jaringan sosial dan politik yang mungkin mereka bangun pasca-pembubaran. Namun, untuk menjadi “penggalang” alih-alih “digalang”, Indonesia membutuhkan strategi yang komprehensif dan berlapis.
Jika negara tidak berhasil mengambil peran sebagai aktor yang aktif, maka potensi bahaya akan meningkat secara eksponensial.
Kegagalan untuk memahami dan mengantisipasi pola adaptasi JI dapat membuka jalan bagi mereka untuk mengeksploitasi celah kebijakan dan memanfaatkan momentum untuk kebangkitan baru.
Dalam hal ini, keberhasilan Indonesia bergantung pada kemampuan untuk memahami dinamika sosial-politik yang lebih besar dan menempatkan dirinya sebagai arsitek yang menentukan arah evolusi suatu kelompok.