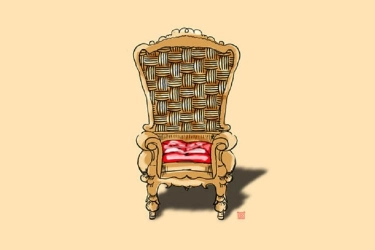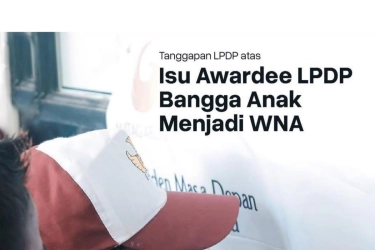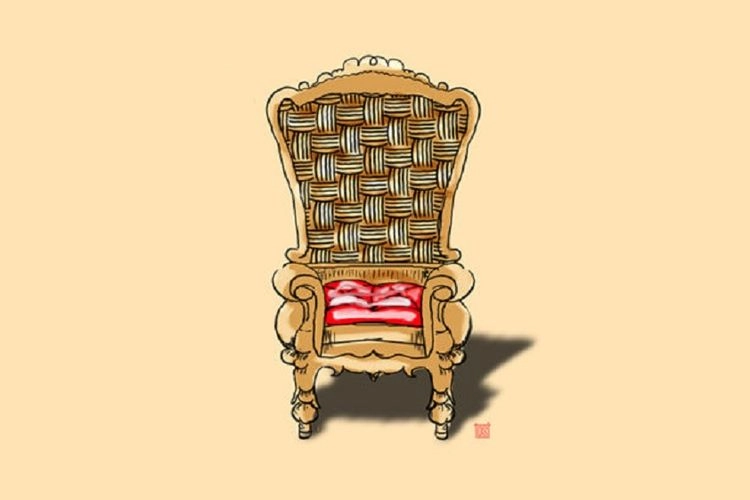
Sinisme Presidential Threshold
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menandakan kemenangan bagi demokrasi. Putusan tersebut menghapus ambang batas persentase minimal pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.
Di balik euforia dan momentum ini, ikhtiar yang dilakukan pada Januari 2025, oleh beberapa mahasiswa dari Komunitas Pemerhati Konstitusi, tidak terlepas dari kritik dan sinisme. Bahkan beberapa di antaranya bernada ad hominem.
Tulisan ini hadir untuk menjawab serta mendiskusikan beberapa komentar di balik keberhasilan penghapusan presidential threshold.
Inkonsistensi MK
Sinisme pertama adalah kritik kepada Mahkamah Konstitusi yang tidak konsisten dalam memutus. Ada 33 putusan sebelumnya pada pengujian UU Pemilu yang selalu menilai ketentuan tersebut open legal policy dan sah untuk diterapkan.
Argumentasi yang dihadirkan oleh para pengkritik menilai adanya kepentingan besar di balik para hakim sehingga memaksa mengubah haluannya dalam memutus.
Terhadap hal tersebut, perlu dipahami dua hal pokok. Pertama, sistem hukum Indonesia, khususnya dalam peradilan konstitusi, tidak mengenal doktrin stare decisis (asas preseden) secara ketat yang mewajibkan ketaatan ekstrem terhadap putusan-putusan yang ada terdahulu.
Dengan demikian, perubahan haluan putusan ‘halal’ terjadi.
Kedua, praktik perubahan haluan ini dikenal dengan istilah “overruling” yang di antara sebabnya karena faktor permohonan, adanya perkembangan penafsiran hakim (termasuk komposisi), serta perkembangan kebutuhan hukum.
Sekalipun dalam praktik terjadi overruling, menariknya Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo justru menunjukkan adanya konsistensi sikap yang sedari beberapa putusan sebelumnya selalu menolak presidential threshold.
Hal positif dalam perubahan haluan ini adalah upaya perwujudan responsive judicial review berupa praktik perbaikan demokrasi melalui peradilan konstitusi yang berubah drastis (dalam konotasi buruk, inkonsisten) dari praktik abusive judicial review (pengujian UU yang mengarah pada merusak demokrasi) dalam tren putusan-putusan Mahkamah sebelumnya.
Intervensi Parpol
Sinisme kedua adalah adanya penilaian terdapat konflik kepentingan dari partai tertentu yang ‘mengintervensi’ serta memengaruhi hadirnya putusan monumental ini.
Beberapa komentar bahkan spesifik menjuruskan tuduhan ini kepada partai-partai yang kalah dalam Pemilu yang seakan mengambil peran menjadi oposisi.
Para pengkritik berdasarkan argumentasi ini seakan justru skeptik dengan kemenangan demokrasi dan menganggap kepentingan ini sebagai noktah yang seakan membuat hal positif di baliknya terlupakan.
Untuk menjawab sinisme ini, sederhananya tinggal menjawab bahwa itu argumentasi yang asumtif. Namun, sekadar menganggapnya sebagai perkiraan tanpa bukti.
Sebab, rational choice dalam politik mungkin saja mengarah kepada kecenderungan kepentingan politik tertentu untuk memberi pengaruh atas kebijakan yang sedang dibuat atau sedang diuji.
Karena bagaimanapun, enam dari sembilan hakim konstitusi dipilih oleh lembaga yang erat kaitannya dengan politik.
Tidak menghindari kritik ini, UU Pemilu yang diuji salah satu pasalnya memang mengatur tentang kekuasaan yang tentunya akan berbenturan dengan kepentingan yang tarik-menarik.
Namun ketika itu berwajah konflik yang merugikan demokrasi, maka sepatutnya ditolak.
Berdasarkan syarat ini, sekalipun secara rasional (yang asumtif) bahwa ini dapat dipengaruhi oleh aktor politik tertentu, kemenangan demokrasi serta tidak dilanggarnya supremasi hukum menjadikan kritik semacam ini semakin tidak bernilai.
Jadi, di sini demokrasi yang menjadi titik dan tolok ukur.
Efisiensi pencalonan
Sinisme ketiga adalah risiko calon presiden dan wakil presiden yang akan membludak. Risiko ini sebetulnya tidak bergantung pada ada atau tidaknya presidential threshold.
Sebab, potensi membludaknya calon memang dampak dari sistem multipartai di Indonesia yang disertai ketentuan dalam konstitusi bahwa calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik. Semakin banyak partai politik, semakin besar pula kemungkinan banyak calon.
Pada poin ini, para pengkritik menghadirkan argumentasi yang rasional dan ilmiah.
Perlu digaris bawahi, mekanisme ini menjamin dan memastikan adanya dukungan bagi calon presiden dengan minimal dua puluh persen kursi di DPR serta membuat efisiensi pencalonan.
Pandangan ini yang sering dibawakan oleh para pendukungnya. Namun, apakah hanya presidential threshold yang menjamin hal tersebut?
Pertanyaan ini harus dijawab, sebab selain presidential threshold membawa banyak dampak buruk, memang diperlukan mekanisme pengganti yang menjamin presiden memiliki dukungan serta merangkai efisiensi pencalonan.
Untuk itu, perlu dilacak bagaimana mekanisme selainnya diterapkan di negara-negara lain.
Berdasarkan sejarah, sistem presidensial dan multipartai di negara-negara (khususnya Amerika Latin) tidak mengadopsi ketentuan presidential threshold ini.
Solusi pada negara-negara tersebut adalah pelaksanaan pemilu serentak sehingga menimbulkan coattail effect (efek ekor jas) yang memastikan presiden memiliki dukungan, sebab pemilih yang memiliki partai tertentu akan cenderung sekaligus memilih calon presiden dari partai yang sama.
Pada sisi lain, ini juga menghindarkan dari divided government (pemerintahan terbelah) yang membuat kekuasaan pemerintah menjadi pincang.
Dengan demikian, pada dasarnya tanpa presidential threshold sudah terdapat mekanisme asli yang terlebih dahulu dipraktikkan.
Satu lagi persoalan yang harus terjawab adalah efisiensi pencalonan. Saat ini di Indonesia, telah terdapat mekanisme pemilu presiden dua ronde (two round system) yang betapapun banyak calon yang ada, pada akhirnya akan terfilter menjadi dua pasangan calon terkuat yang akan dipilih.
Sehingga, sekalipun tidak benar-benar membatasi secara nominal khusus, sistem pemilu membatasi banyaknya calon dengan menyisakan dua terkuat untuk dipilih kembali.
Lantas apakah mekanisme ini lebih efisien dari presidential threshold?
Karena pemilu presiden secara langsung yang pertama di tahun 2004 diterapkan dengan mekanisme ini, maka tidak terdapat perbandingan langsung di Indonesia.
Namun secara kuantitatif, memang jumlah calon presiden terbanyak adalah lima calon di Pilpres tahun 2004, kemudian menjadi tiga calon di 2009 dan 2024, dan hanya dua calon di 2019 dan 2014.
Dalam praktik tersebut, tiga dari lima pemilu tetap dilaksakanan secara dua ronde, meskipun terdapat presidential threshold.
Saya kira, dengan pendekatan kemenangan di pemilu secara rasional, partai-partai juga tidak sembarang untuk mengambil koalisi dan mengusung calon tertentu.
Sebab, selain ongkos politik pencalonan yang cukup tinggi, hasrat untuk bergabung dan menang juga secara strategik menjadi pertimbangan untuk mengusung calon atau tidak.
Untuk lebih membuktikan, selanjutnya kita perlu melihat jumlah calon pada negara presidensial-multipartai yang tidak menggunakan presidential threshold.
Pada pemilu presiden terbaru (2020-2024), pada lima belas negara, hanya enam di antaranya yang proses voting dalam pemilu langsungnya diikuti oleh tiga calon dan selainnya hanya diikuti oleh dua calon presiden.
Tentunya negara-negara tersebut memiliki mekanisme sendiri-sendiri untuk memfilter tokoh-tokoh politik yang kuat maupun populer.
Namun yang perlu digaris bawahi adalah tidak diberlakukan ambang batas presidential threshold seperti Indonesia dan pencalonan tetap dapat efisien.
Pragmatisme baru
Sinisme keempat ini jarang disuarakan, namun ini mungkin jadi persoalan. Pengkritik menghadirkan argumentasi ini sebab pertimbangan rekayasa konstitusional dari Mahkamah Konstitusi yang salah satunya adalah mengharuskan kewajiban bagi partai-partai untuk mencalonkan atau terlibat dalam koalisi yang mencalonkan presiden dalam pemilu.
Sama hal-nya dengan pengkritik efisiensi pencalonan, argumentasi ini rasional dan ilmiah.
Dengan adanya kewajiban untuk tetap mencalonkan tersebut, partai yang betul-betul tidak mempunyai kandidat akan terpaksa secara pragmatis bergabung dalam koalisi tertentu.
Sehingga, sekalipun pragmatisme dua puluh persen sudah hilang, dapat hadir pragmatisme baru berupa “harus mencalonkan atau disanksi”.
Dalam pandangan pribadi, saya mengakui bahwa ini merupakan keluputan dan celah dari suatu sistem.
Namun, menyikapi ini, sebenarnya pada dasarnya pragmatisme itu selalu menjadi soal sebab karakter kepartaian yang amat heterogen dan ideologinya yang abu-abu sehingga pada akhirnya selalu ada kecenderungan koalisi berdasarkan pragmatisme.
Dengan demikian, kesadaran dan etika berpolitik adalah hal yang harus hadir agar keberpihakan partai dalam koalisi dan pencalonan benar berdasarkan visi politik, bukan prgamatisme.
Ad Hominem
Sinisme terakhir berbau personal, ialah mengkritik dan mengutarakan kelucuan atas permohonan dari mahasiswa yang bisa diterima, sementara pemohon para pakar yang pernah mengajukan sebelumnya selalu ditolak.
Pengkritik melihat individu pemohon daripada argumentasi dan hasil yang diperoleh.
Sinisme ini beberapa juga disuarakan oleh pihak yang sebenarnya menyetujui dihapusnya presidential threshold ,sementara beberapa yang lain mengaitkannya dengan permohonan Almas Tsaqibbiru, mahasiswa penggugat umur minimal Wakil Presiden yang berkonotasi negatif.
Ini adalah sinisme yang paling mudah dijawab. Sebab dengan karakter ad hominem telah menunjukan logical fallacy sehingga meruntuhkan argumentasi itu sendiri.
Pada sisi lain, hal yang luput di sini adalah para pengkritik seakan memisahkan keberpihakan pemohon mahasiswa ini dengan permohonan-permohonan yang ada sebelumnya.
Sebab, jika ditelaah, permohonan yang diajukan mengutip dan berangkat dari adanya permohonan-permohonan sebelumnya sekalipun mendalilkan hal yang sedikit berbeda.
Dengan demikian, lebih tepatnya memandang keberhasilan penghapusan presidential threshold ini sebagai gunung es yang turut menyempurnakan ikhtiar judicial review dan begitu banyaknya kajian ilmiah serta sikap politik untuk menghapus presidential threshold daripada gedung pencakar langit yang berdiri sendiri yang untuk membangun pondasi saja perlu meruntuhkan bangunan-bangunan di sekitarnya.