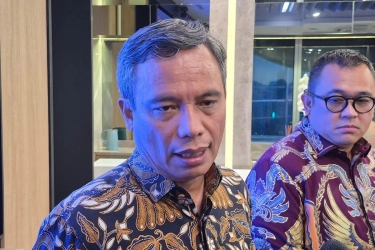Mewaspadai Harga Sosial di Balik Optimisme atas Kelapa Sawit
PRESIDEN Prabowo Subianto menyebutkan bahwa kelapa sawit adalah aset strategis Indonesia dan pohon yang mampu menyerap karbon dioksida. Menurutnya, tidak perlu terlalu dikhawatirkan dalam konteks deforestasi.
Pernyataan ini mencerminkan optimisme terhadap kelapa sawit sebagai komoditas unggulan nasional yang tidak hanya menopang ekonomi, tetapi juga dianggap ramah lingkungan.
Namun, apakah kenyataannya seindah klaim tersebut?
Pertanyaan kritis muncul: Apakah ekspansi besar-besaran perkebunan sawit benar-benar membawa kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat?
Apakah masyarakat adat, petani kecil, dan buruh perkebunan sawit mendapatkan manfaat setara, atau justru menjadi korban utama dari kesenjangan yang semakin melebar?
Bagaimana pula dampak nyata ekspansi sawit terhadap lingkungan, terutama hutan tropis yang selama ini menjadi penyangga ekosistem global?
Optimisme terhadap sawit sebagai aset strategis perlu dikaji ulang, terutama dengan mempertimbangkan harga sosial yang harus dibayar oleh masyarakat lokal dan lingkungan.
Dari sinilah kita perlu menelusuri lebih dalam, khususnya terkait ketimpangan sosial yang menyelimuti ekspansi sawit di Indonesia.
Ketimpangan sosial dalam ekspansi sawit
Ekspansi perkebunan sawit di Indonesia sering kali berbenturan dengan hak-hak masyarakat adat dan petani kecil.
Dalam banyak kasus, tanah masyarakat dirampas atau dialihkan tanpa proses yang transparan, dan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi sandaran hidup mereka semakin dibatasi (Dewi et all, 2024).
Masyarakat adat yang selama ini menjaga kelestarian lingkungan sering kali menjadi korban dari kebijakan yang memprioritaskan kepentingan korporasi besar dibandingkan komunitas lokal.
Menurut perspektif Marxis, ketimpangan ini adalah manifestasi dari konflik kelas antara kapitalis (pemilik modal) dan kaum proletar (buruh dan petani).
Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi sektor sawit bertindak sebagai kapitalis yang memaksimalkan akumulasi keuntungan dengan mengeksploitasi tanah dan tenaga kerja, sementara masyarakat lokal kehilangan alat produksi utama mereka—yaitu tanah.
Hubungan ini tidak hanya mempertegas dominasi ekonomi kapitalis, tetapi juga menciptakan alienasi, di mana masyarakat adat dan petani kecil kehilangan kendali atas sumber daya yang sebelumnya menjadi bagian integral dari kehidupan mereka (Wibowo & Firdaus, 2020).
Ironisnya, perusahaan besar sering kali menjadi pihak yang paling diuntungkan dari ekspansi sawit, sementara masyarakat lokal kehilangan tanah yang menjadi sumber utama kehidupan mereka.
Ketimpangan ini mencerminkan kurangnya keadilan dalam pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia. Hak masyarakat adat sering kali terabaikan, dan mekanisme hukum yang ada tidak cukup kuat untuk melindungi mereka dari dominasi kapital.
Kondisi buruh perkebunan sawit
Selain konflik agraria, nasib buruh di sektor kelapa sawit juga mencerminkan sisi gelap dari industri ini. Banyak pekerja di perkebunan sawit harus bekerja dalam kondisi berat, dengan upah rendah, tanpa jaminan sosial, dan minim perlindungan keselamatan kerja (Maftuchan & Harja, 2021).
Dalam konteks Marxis, buruh perkebunan sawit dapat dianggap sebagai bagian dari proletariat yang dieksploitasi oleh kapitalis untuk menghasilkan surplus ekonomi.
Nilai kerja mereka sering kali tidak sebanding dengan upah yang diterima, sementara keuntungan besar mengalir ke tangan pemilik modal.
Ketidakadilan ini mencerminkan bagaimana kapitalisme dalam sektor sawit mengutamakan keuntungan dibandingkan kesejahteraan tenaga kerja.
Kondisi ini juga memperlihatkan bagaimana buruh menjadi "komoditas" dalam sistem ekonomi yang memprioritaskan produktivitas tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya.
Jika kelapa sawit disebut sebagai aset strategis nasional, maka kondisi kerja buruh yang menopang industri ini harus menjadi perhatian utama.
Perjuangan buruh untuk mendapatkan upah layak dan perlindungan sosial seharusnya menjadi bagian dari agenda besar reformasi sektor sawit di Indonesia (Pratiwi, 2020).
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebutkan bahwa kelapa sawit mampu menyerap karbon dioksida, sehingga tidak perlu terlalu dikhawatirkan dalam konteks deforestasi.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan sawit sering kali menggusur hutan hujan tropis yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global.
Hilangnya hutan ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat adat yang menggantungkan hidup mereka pada hutan (Risal, 2018).
Klaim ramah lingkungan ini juga patut dipertanyakan. Penyerapan karbon oleh pohon kelapa sawit tidak sebanding dengan emisi karbon yang dihasilkan dari pembukaan lahan, terutama jika dilakukan dengan pembakaran hutan.
Selain itu, hutan hujan tropis yang digantikan oleh perkebunan sawit memiliki fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks, termasuk sebagai habitat bagi spesies langka dan penyerap karbon lebih efisien.
Pidato Prabowo, yang cenderung menyederhanakan isu lingkungan ini, justru menutupi kerusakan ekosistem yang tak tergantikan akibat ekspansi sawit.
Perspektif Marxis menyoroti bahwa kerusakan lingkungan ini adalah konsekuensi dari "eksternalitas" yang diabaikan oleh kapitalis.
Dalam upaya mereka memaksimalkan keuntungan, kerugian lingkungan sering kali dianggap sebagai biaya yang tidak signifikan, padahal dampaknya sangat besar terhadap masyarakat dan ekosistem.
Dalam konteks sawit, masyarakat lokal menjadi korban ganda: mereka kehilangan tanah dan akses sumber daya, sekaligus harus menghadapi dampak lingkungan seperti banjir, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Keuntungan ekonomi atau keadilan sosial?
Keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit memang signifikan, tetapi apakah cukup untuk menggantikan kerugian sosial dan lingkungan yang ditimbulkan?
Hingga kini, pendekatan pemerintah terhadap sawit lebih banyak berfokus pada manfaat ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat dan lingkungan.
Dalam konteks Marxis, hal ini mencerminkan bagaimana negara sering kali menjadi alat kapitalis untuk melegitimasi eksploitasi sumber daya, alih-alih melindungi rakyatnya (Fadhlillah, 2022).
Sebagaimana dikatakan dalam kutipan, "Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, tetapi kita meminjamnya dari anak cucu kita," kelapa sawit seharusnya tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, tetapi juga simbol keberlanjutan sosial dan ekologi.
Pidato Prabowo yang hanya menyoroti potensi ekonomi sawit tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan justru mengabaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat adat, buruh, dan ekosistem.
Kini, pertanyaannya adalah: apakah kita siap mengubah paradigma pengelolaan sawit menjadi lebih adil dan berkelanjutan? Ataukah kita terus membiarkan industri ini menjadi simbol ketimpangan dan kerusakan?
Transformasi sektor sawit membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk memastikan bahwa kelapa sawit tidak hanya menjadi aset strategis ekonomi, tetapi juga alat untuk menciptakan masyarakat lebih adil dan dunia lebih lestari.
Jika tidak, maka kita hanya akan mewariskan kerusakan dan ketidakadilan kepada generasi mendatang.
Tag: #mewaspadai #harga #sosial #balik #optimisme #atas #kelapa #sawit