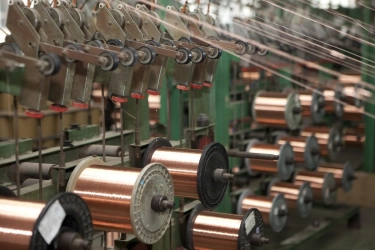Kebijakan Proteksionisme Trump, Ancaman bagi Ekonomi Indonesia
SETELAH dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47 pada 20 Januari mendatang, Donald Trump akan memiliki wewenang untuk membuat dan menerapkan kebijakan yang strategis bagi bangsa dan negaranya.
Masyarakat dunia, termasuk Indonesia, hanya bisa menunggu sembari berharap agar Presiden Trump membuat dan menerapkan kebijakan politik-keamanan dan ekonomi, yang berdampak positif bagi negaranya masing-masing dan bagi masyarakat global secara keseluruhan.
Merujuk ke materi kampanye Trump menjelang pemilu Oktober 2024 lalu, dan kondisi global saat ini, sejumlah kalangan memperkirakan bahwa Trump akan mendahulukan hal yang paling penting bagi AS dan dunia, yaitu memperbaiki kembali hubungan geopolitik Amerika yang menegangkan dengan Rusia dan China.
Walau belum ada yang dapat menggambarkan secara jelas apa yang akan dinegosiasikan Trump dengan Vladimir Putin, tetapi tampaknya posisi AS terhadap Ukraina akan bermula dari sini.
Lalu bagaimana sikap Trump terhadap China?
Para pengamat melihat bahwa Trump sepertinya menganggap bahwa ‘pembenahan’ hubungan dengan China sebagai hal yang kurang mendesak.
Menurut mereka, bagi Trump hal yang paling mendesak saat ini adalah memperkuat ekonomi dalam negeri AS melalui penguatan ekonomi global dan stabilitas internasional.
Proteksionisme Trump hanya retorika?
Yang menarik, hingga menjelang pelantikan, para pengamat lokal AS dan global bersama para investor, dan pejabat pemerintah asing belum menemukan isyarat kuat bahwa Trump akan menindaklanjuti ancaman tarif tambahan pada impor Tiongkok.
Sebaliknya, mereka jutru berharap bahwa janji-janji kampanye Trum hanyalah retorika.
Artinya mereka meragukan bahwa Trump benar-benar akan mengejar agenda proteksionis yang berpusat pada tarif yang ia kampanyekan.
Keraguan itu mencuat ketika mereka melihat penampilan Trump baru-baru ini di acara "Meet The Press," di mana ia kembali menegaskan bahwa ia adalah "orang yang sangat percaya pada tarif" yang "tidak merugikan orang Amerika," memperkuat ancaman sebelumnya untuk mengenakan tarif 25 persen pada semua barang yang datang dari Meksiko dan Kanada dan 10 persen pada China.
Strategi perdagangan Trump itu mencerminkan pandangan dunia yang berakar pada merkantilisme abad ke-19, yang menekankan proteksionisme dan penggunaan tarif yang agresif.
Trump tampaknya melihat tarif sebagai alat serbaguna: terkadang sebagai sarana untuk mencapai tujuan—sebagai daya ungkit negosiasi untuk mencapai kesepakatan—dan terkadang sebagai tujuan itu sendiri—baik untuk mendorong kembalinya manufaktur AS ke negara asal dan untuk menghasilkan pendapatan guna membayar pemotongan pajak dan pengeluaran.
Berdasarkan pendekatan ini, tarif diasumsikan "tanpa biaya", tanpa dampak negatif yang ditanggung oleh konsumen dalam negeri (melalui harga yang lebih tinggi) atau oleh bisnis (melalui input dengan harga yang lebih tinggi dan rantai pasokan yang terganggu).
Namun, Trump sepertinya mulai menyadari bahwa bagi AS dan mitra dagangnya, kebangkitan proteksionisme di dunia yang saling terhubung menimbulkan serangkaian risiko ekonomi, strategis, dan kelembagaan.
Pada sisi lain, bagi China, pengumuman tarif 10 persen—yang tidak seagresif sebelumnya yang diancamkan sebesar 60 persen—mungkin menimbulkan kelegaan.
Reaksi awal China kemungkinan terbatas pada devaluasi renminbi (RMB), yang secara efektif mengimbangi tarif dengan menurunkan harga dollar barang yang diekspornya. Ini adalah taktik yang digunakan China secara efektif selama masa jabatan pertama Trump.
Sementara renminbi sudah lemah, China mampu melemahkan RMB lebih jauh untuk mempertahankan daya saing ekspor tanpa secara langsung meningkatkan ketegangan dengan AS.
Jika Trump mengeluarkan ancaman tambahan berupa tarif dan tindakan perdagangan lebih lanjut, maka Presiden Xi Jinping akan melakukan perlawanan.
Bahkan, pada kondisi tertentu, China dapat mengerahkan berbagai alat pembalasan terhadap kepentingan AS.
Selain penerapan tarif balasan yang langsung, China dapat lebih meningkatkan penggunaan pembatasan ekspor pada mineral penting, memanfaatkan "Daftar Entitas yang Tidak Dapat Diandalkan" miliknya sendiri, dan memberlakukan kontrol ekspornya sendiri yang mirip dengan Aturan Produk Langsung Asing AS, yang berpotensi memengaruhi perdagangan global di mana pun AS terlibat.
Langkah-langkah ini akan memungkinkan Beijing bisa membuat target yang lebih tepat dalam melumpuhkan perusahaan-perusahaan AS tertentu atau industri-industri penting, dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi signifikan tanpa memicu perang dagang skala penuh.
Memperpanjang ‘ketakpastian’
Ketakjelasan sikap Trump terkait tarif dagang atas China dapat berdampak bagi perekonomian Indonesia. Setidaknya hal itu dapat memperpanjang rasa gamang Indonesia terhadap kepastian hubungan dagangnya dengan kedua negara dengan kekuatan ekonomi raksasa itu.
Ketakpastian tersebut membuat Indonesia harus lebih banyak bersabar dan menunggu atau menunda untuk mengambil kebijakan moneter yang tepat.
Dampak dari kebijakan moneter yang tertunda adalah Indonesia akan sulit menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi yang cepat.
Dengan kata lain, keterlambatan dalam transmisi kebijakan moneter akan membuat roda perekonomian Indonesia berputar secara melambat.
Sebetulnya, hal yang lebih perlu diwaspadai Indonesia adalah ancaman Trump akan mengenakan tarif 100 persen pada BRICS jika mereka menciptakan mata uang saingan bagi dollar AS.
"Gagasan bahwa Negara-negara BRICS mencoba menjauh dari dollar sementara kita hanya berdiam diri dan menonton sudah BERAKHIR," tulis Trump di media sosial pada hari Sabtu, awal Desember lalu.
China dan Rusia merupakan bagian dari aliansi BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.
Pernyataan Trump tersebut mencerminkan tren konfrontasi ekonomi lebih luas yang melampaui China.
Kembalinya perang ekonomi yang diantisipasi ini menandakan era yang menantang bagi negara-negara berkembang, khususnya mereka yang berada dalam aliansi BRICS.
Sejumlah pengamat menilai sikap negatif Trump terhadap BRICS dapat memperkeruh suasana perekonomian global.
Menuurut mereka, seharusnya Trump perlu menyadari bahwa negara-negara BRICS tidak berusaha membongkar hegemoni AS. Namun sebaliknya, mereka bertujuan mengatasi efek merugikan dari dominasi dollar AS yang luar biasa.
Konteks historis sangat penting di sini adalah: negara-negara berkembang telah berulang kali menderita di bawah kebijakan moneter AS, seperti kenaikan suku bunga yang mendorong pelarian modal, yang memperburuk tekanan ekonomi mereka.
Jika AS ingin mempertahankan dominasinya, maka ia harus mempertimbangkan kembali berapa lama ia dapat melakukannya secara tidak bertanggung jawab.
Upaya negara-negara BRICS untuk membangun mata uang alternatif bagi kerja sama perdagangan muncul dari keinginan yang tulus untuk meredakan ketegangan ekonomi ini.
Meskipun meluncurkan mata uang alternatif, BRICS masih memerlukan banyak pekerjaan, meningkatnya persenjataan dollar oleh AS akan mendorong negara-negara ini untuk lebih bergantung pada mata uang lokal mereka.
Daripada mengancam tarif, Trump seharusnya lebih aktif terlibat dengan negara-negara ini untuk mengusulkan jalur yang layak menuju stabilitas moneter.
Para pengamat berpandangan bahwa meskipun Trump dapat mewujudkan ancamannya secara bertahap, ia tidak boleh berasumsi bahwa pendekatannya akan menang.
Stabilitas ekonomi telah menjadi prioritas yang tidak dapat dibatalkan bagi negara-negara berkembang, dan AS berisiko mengalami kerugian lebih besar karena kepercayaan terkikis.
Pergeseran ke arah kebijakan proteksionis ini dapat menyebabkan negara-negara lain menolak produk-produk AS, yang merusak kepentingan ekonomi AS.
Selain itu, kata para pengamat, deklarasi Trump menimbulkan masalah hukum, karena tidak sejalan dengan peraturan dan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Hal ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana AS akan tampak mengabaikan hukum internasional?
Sepertinya, ancaman Trump lebih merupakan sikap politik daripada kebijakan yang dapat ditindaklanjuti. Namun, jika menjadi kenyataan, ancaman tersebut dapat menandakan berakhirnya tatanan internasional stabil yang mampu mengelola persaingan global antarnegara.
Dampaknya bagi Indonesia
Ancaman Trump tersebut mulai menimbulkan ‘perlawanan’ dari BRICS. Mesir misalnya, membeberkan laporan dinamika perdagangannya dengan AS.
Volume perdagangan antara Mesir dan AS mencapai 7,3 miliar dollar AS pada 2023. Dari jumlah tersebut, nilai ekspor Mesir ke AS mencapai 1,9 miliar dollar AS, sedangkan impor Mesir dari AS mencapai 5,4 miliar dollar AS pada tahun yang sama.
Berdasarkan data tersebut, Mesir tidak yakin bahwa ancaman Trump akan menimbulkan banyak kepanikan di negaranya. Sebaliknya, AS berpotensi kehilangan pasar Mesir jika perang dagang AS vs BRICS benar-benar meletus.
Kondisi Indonesia justru sebaliknya dari Mesir. Neraca perdagangan Indonesia – AS berada dalam kondisi surplus, karena nilai ekspor Indonesia ke AS lebih besar dari nilai impor Indonesia dari AS.
Sebagai contoh, nilai ekspor non-migas Indonesia ke AS per Agustus 2024 sebesar 448,9 juta dollar AS, 20,80 persen dari Juli 2024, sedangkan nilai impor Indonesia dari AS sebesar 20,67 juta dolar AS.
Ekspor non migas periode Januari – Agustus 16,952 miliar dollar AS, sedangkan impor non-migas, 6,307 miliar dollar AS.
Dalam dinamika perdagangan bilateral yang demikian, maka ancaman proteksi Trump atas BRICS dapat menjadi malapetaka bagi Indonesia. Indonesia berpotensi kehilangan pasar ekspornya ke AS.
Jadi, sebagaimana negara yang memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan dengan AS, Indonesia memang perlu terus memantau gerak-gerik Trump terkait kebijakan tarif.
Lebih daripada itu, Indonesia juga perlu mengambil langkah antisipatif, misalnya dengan terus memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan sesama anggota BRICS.
Tag: #kebijakan #proteksionisme #trump #ancaman #bagi #ekonomi #indonesia